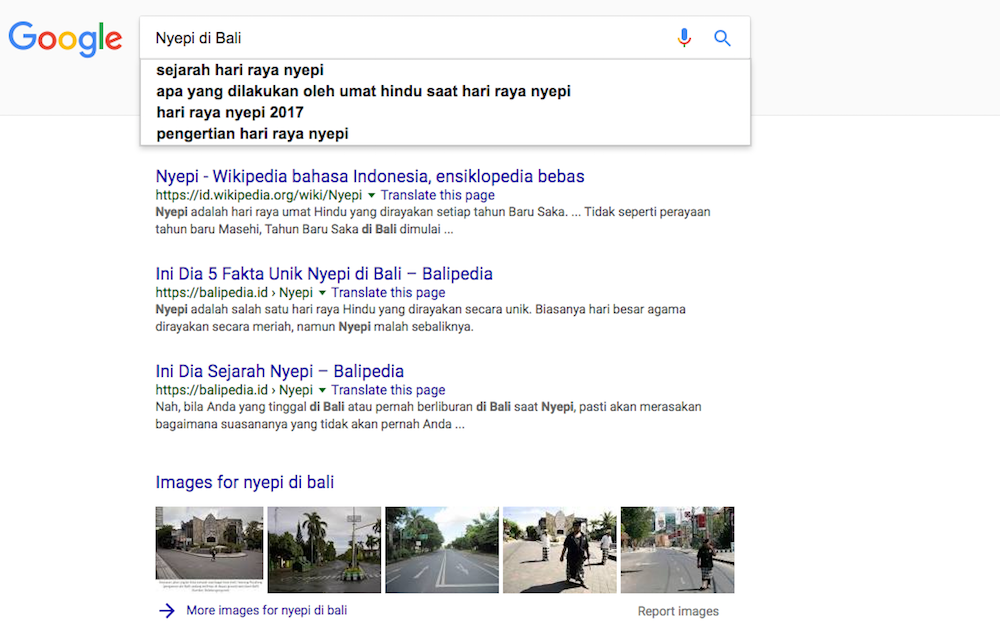Mari merayakan dan memaknai Nyepi di Google.
Mesin pencari ini telah menjadi rumah bagi banyak orang, rumah kita yang baru. Google adalah ranah di mana segala narasi hidup kontemporer kita muarakan, tempat segala ketidaktahukan kita tanyakan, kita kembalikan, kita awalkan.
Mesti diakui, Google telah bergerak menjadi “kawitan” baru bagi kita.
Mari kita mulai merayakan dan memaknai Nyepi di Google ini dengan memasukkan kata kunci “sejarah nyepi” di kotak persegi panjang yang kosong dan ajaib itu. Enter, lalu buka salah satu hasil penelusuran, kita akan menemukan narasi ini: Konflik antarsuku yang berkepanjangan di India, perebutan kuasa, terbentuknya kelompok-kelompok kepercayaan keagamaan yang berbeda, krisis sosial yang mengguncang.
Lalu semua diakhiri oleh kemenangan Suku Saka, di bawah kuasa Raja Kaniskha I, yang dinobatkan pada pinanggal kapisan Caitramasa 1 Saka (tahun 78 M). Kuasa Raja Kaniskha I membawa sebuah tatanan baru ke arah kebersamaan, kedamaian, toleransi, kerukunan.
Jika narasi di atas benar adanya, maka selain sebuah monumen kebangkitan ke arah tatanan baru yang damai, Nyepi sebagai perayaan tahun baru Saka adalah juga prasasti bagi sebentuk kekuasaan baru. Ia yang kita rayakan sebagai momen untuk mulat sarira, punya dimensi perebutan hegemoni di belakangnya. Ia yang kita maknai filsafat, memiliki jejak politik.
Saya teringat sebuah pemeo yang entah kapan dan di mana saya pernah membacanya: “Bahkan bertapa sendiri di hutan rimba pun, manusia tidak bisa bebas dari politik.”
Membaca narasi tentang asal usul penanggalan Saka di atas, saya teringat sejarah Pura Samuan Tiga. Ada keserupaan narasi antara keduanya. Pura yang terletak di wilayah yang diduga sebagai pusat pemerintahan Bali Kuna ini adalah sebuah situs musyawarah, di mana konsepsi Tri Murti di Bali bertonggak. Inilah situs dialog antar-yang-berbeda, namun bukan medan perang seperti yang melatarbelakangi tatanan baru yang dikomandoi Kaniskha I.
Pasamuan Agung yang dipimpin Mpu Kuturan di Pura Samuan Tiga dilatarbelakangi oleh riak-riak konflik antarsekte—yang jumlahnya dianggap terlalu banyak—di Bali ketika itu. Musyawarah besar ini kemudian melahirkan konsepsi anyar, semacam orde baru, yang kita gunakan hingga kini di Bali: Kahyangan Tiga.
Tatanan baru ini artinya meleburkan seluruh sekte, dan mengarahkannya untuk mengutamakan tiga dewa. Ada narasi penyeragaman di sini. Ada pemerian tentang penyamaan, bukan memelihara yang berbeda. Dengan bahasa yang lebih diplomatis: yang dipilih untuk meredam ledakan konflik antarsekte adalah pengerucutan dari banyak sekte (artinya, masing-masing memuja dewa utama) menjadi aliran tunggal dengan tiga dewa utama.
Untuk menuju tatanan damai, tentu rapat besar di Pura Samuan Tiga tidak lepas dari narasi kuasa politis. Penyeragaman adalah sebuah strategi politis. Konon ketika itu pemegang kendali Bali adalah Gunapriyadharmapatni dan Udayana, yang mengangkat Mpu Kuturan sebagai senapati sekaligus ketua dewan penasihat kerajaan yang membawahkan para senapati dan pendeta istana lainnya.
Konon pula sebelumnya, ketika masih di Jawa, Mpu Kuturan adalah seorang kepala pemerintahan di Girah. Dalam tubuh Mpu Kuturan bukan hanya ada kualitas kapandhitan, namun juga dimensi seorang politikus. Bahkan seorang politikus ulung, sebab dialah arsitek musyawarah agung itu.
Aji Saka
Kembali ke “sejarah nyepi” menurut Google. Setelah narasi tentang Kaniskha I, Google memberikan kita saran sosok yang berkali-kali disebut: Aji Saka.
Konon, ia adalah seorang pandhita yang tiba di Jawa pada tahun 456 M untuk menyosialisasikan sistem kalender Saka, termasuk perayaan pergantian tahunnya, yang kini kita kenal sebagai Nyepi. Jika mengikuti angka tahun kisah ini, maka umat Hindu di Jawa baru mulai mengetahui penanggalan Saka saat sistem itu sendiri telah berumur 378 tahun.
Pada sosok Aji Saka ini, kita menemukan jembatan antara peradaban sistem waktu nun jauh di India dengan yang kita pakai hingga saat ini di Bali.
Siapa sih Aji Saka ini?
Tampaknya, dialah pahlawan utama yang membuat kita bisa merayakan Nyepi hingga hari ini di Bali. Mari kita masukkan keyword “aji saka” ke dalam kotak ajaib Google. Enter, buka hasil teratas, kita diberi pemerian tafsiran ini: Aji Saka berasal dari Jambudwipa (India), seorang keturunan Suku Saka.
Ia jadi simbol kedatangan dharma (ajaran Hindu dan Budha) ke Tanah Jawa, dan karena namanya Saka (bahasa Jawa: pangkal), ia ditafsir sebagai tonggak peradaban dan tatanan baru di Tanah Jawa yang sebelumnya dikuasai raja raksasa yang zalim.
Pada sosok Aji Saka, kita bertemu lagi dengan narasi tentang tatanan anyar, ketenteraman baru, peradaban mulia, paralel dengan narasi tentang Raja Kaniskha I dan Mpu Kuturan. Dan Aji Saka juga tak lepas dari dimensi politik. Setelah mengalahkan Dewata Cengkar, sang raja raksasa zalim, ia kemudian mengambil alih tampuk kuasa atas Tanah Jawa (Medang Kemulan).
Kuasa mesti diraih untuk menyebarkan suatu tatanan baru. Kekuasaan baru hampir selalu identik dengan tatanan baru.
Yang menarik, Aji Saka juga dianggap sebagai asal-muasal carakan, sistem aksara yang dipakai hingga kini di Jawa, Sunda dan Bali. Aji Saka, sebagai tonggak peradaban, membawa aksara sebagai simbol peradaban.
Dari sini kita menemukan simpul pemaknaan sastra sebagai sebagai simbol luhur dan core dari suatu peradaban. Konon, carakan adalah prasasti yang ditulis Aji Saka untuk menghormati kesetiaan dua abdinya yang gugur karena pertarungan keduanya, yang konfliknya berpangkal pada kesalahpahaman atas tugas yang diberikan Aji Saka sendiri terhadap keduanya.
Tonggak aksara, sastra, sebagai pangkal peradaban, di sini dinarasikan sebagai sebuah penghormatan, pemuliaan. Namun kita tahu, ketika sastra masuk ranah politik, ia menjadi silat lidah, lidah yang lebih tajam dari silet.
Prasasti yang ditulisnya itu berbunyi: ha na ca ra ka da ta sa wa la pa dha ja ya nya ma ga ba tha nga. Inilah carakan atau 20 aksara Jawa, yang jika diuntai akan menjadi kalimat, “Hana caraka, data sawala, padha jayanya, maga bathanga.” Artinya, “Ada (dua) utusan (yang) punya perselisihan, sama-sama tangguh, (dan) inilah mayat (mereka).”
Anehnya, di Bali kini kita hanya mengenal carakan yang berjumlah 18. Aksara dha dan tha tidak ada dalam carakan Bali (namun masuk dalam kategori khusus). Saya sering berseloroh tentang hal ini: mungkin keduanya tenggelam di Selat Bali saat diangkut dari Jawa. Pada dasarnya yang terjadi adalah bahwa, tidak sebagaimana bahasa Jawa, bahasa Bali tidak membedakan ucapan antara da dan dha, serta ta dan tha.
Aji Saka, Syaikh Subakir dan Nabi Ishaq
Mari lihat-lihat lagi penelusuran Google tentang Aji Saka. Ada nama Jaka Linglung di sana, varian lain dari legenda Aji Saka di Jawa.
Abaikan hasil penelusuran Aji Saka sebagai nama kereta kelas ekonomi. Yang menarik bagi saya, Google menyajikan hubungan Aji Saka dengan Syaikh Subakir dan Nabi Ishaq. Ini tiba-tiba saja mengingatkan saya pada narasi tentang Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman.
Lalu memori saya terbawa kepada narasi protes terhadap sinetron Angling Dharma pada 2002 dan 2011. Memang, rumah Google yang penuh hyperlink itu bisa menyinggahkan memori kita ke mana-mana. Tinggal klik saja, maka kita bisa keluyuran.
Oke, mari klik satu tautan tentang Aji Saka dan Syaikh Subakir. Narasi yang kita temukan adalah pemerian tentang nama Aji Saka yang tidak lain adalah gelar dari Syaikh Subakir, spesialis ekologi Islam kelahiran Persia yang dulu berdakwah di sekitar Magelang. Lalu tentang hubungan Aji Saka dengan Nabi Ishaq, narasi yang disajikan Google menguraikan tentang Aji Saka yang ditafsirkan sebagai Haji Saka, yang merupakan keturunan Nabi Ishaq.
Saya tidak paham dan tak punya pengetahuan tentang narasi-narasi ini, dan terlalu sensitif jika dibahas berpanjang-panjang.
Namun saya membaca Jawa sebagai ranah yang menarik justru karena banyaknya narasi yang tumpang tindih semacam itu. Narasi-narasi seperti di atas hampir lumrah di Jawa. Tentang asal usul wayang Jawa, misalnya, Sunan Kalijaga yang dipercaya sebagai pembaharu wayang Jawa diceritakan sebagai pangkal penafsiran Kalimasada (pusaka sakti yang dipegang Yudistira) sebagai “kalimat Syahadat”.
Kisah pertemuan Yudistira dengan Sunan Kalijaga termaktub dalam Serat Centhini, di mana Yudistira menjelang ajalnya menyerahkan Kalimasada kepada Sunan Kalijaga, dan sang sunan lalu memakamkan jenazah Yudistira secara Islam.
Saya membaca narasi-narasi yang demikian paralel dengan narasi tentang kedatangan suatu tatanan baru, peradaban baru, yang niscaya membawa (atau dibawa oleh) kekuasaan baru, kekuatan politik baru. Kuasa baru selalu mencoba membuat narasi-narasi agung untuk ditanamkan kepada rakyat, atau merebut narasi-narasi yang telah tertanam mendalam di benak rakyat dan kemudian mengkonstruksinya sebagai bagian integral dari tatanan baru yang dibawanya. Kita mesti menyadari bahwa dengan cara-cara demikianlah dinamika sejarah peradaban kita di bumi ini berjalan.
Nyepi di Bali
Oke, lewat Google saya jadi keluyuran dan melantur ke mana-mana. Kepala saya terlalu disetir oleh silang sengkarut hyperlink. Saya ingin mengakhirinya. Saya kosongkan kotak ajaib Google, lalu ingin kembali ke topik Nyepi dengan memasukkan kata kunci “nyepi di bali”.
Wow! Saya menemukan hasil fantastis: berbagai tawaran paket wisata di hotel-hotel saat Nyepi di Bali! Rupanya hasil saya mengulik sisi politis yang melekat pada sejarah Nyepi kalah pamor dibanding narasi tentang dimensi ekonomis di balik Nyepi bagi para penguasa kapital! So, mari merayakan (wisata) Nyepi di Bali.
Oke, Google, tunjukin promosi paket wisata Nyepi murah di Bali. [b]