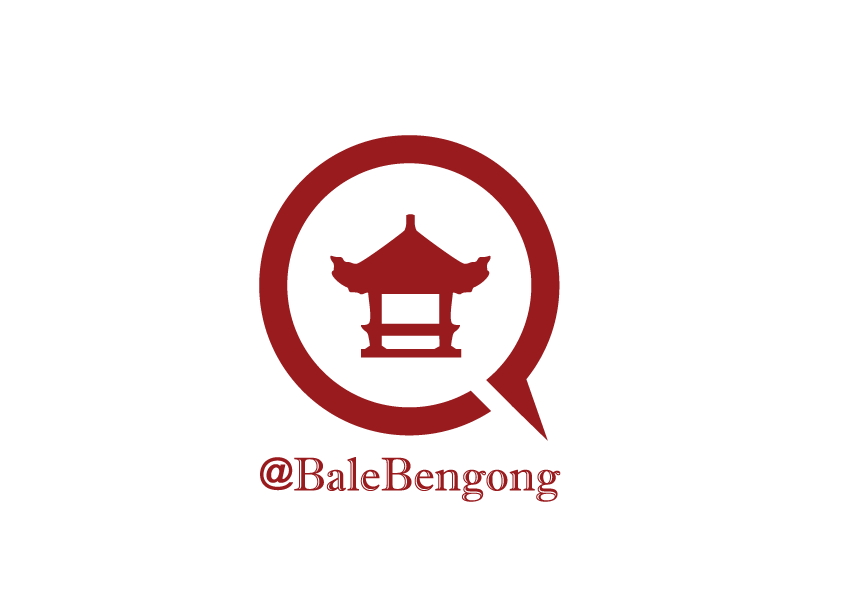Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang pembangunan masif menerjang kawasan peri-urban Bali, wilayah transisi antara pusat pariwisata dan kawasan pedesaan, seperti Mengwi, Abiansemal, dan Gianyar Barat yang bersinggungan langsung dengan koridor wisata Canggu-Ubud dan Denpasar-Gianyar. Villa-villa mewah, kos-kos eksklusif untuk digital nomad, dan gated housing tumbuh bak jamur di musim hujan, sering kali tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis maupun tata ruang berbasis budaya.
Fenomena urbanisasi spontan ini bukan hasil dari perencanaan yang berakar pada nilai-nilai budaya atau keberlanjutan lingkungan, melainkan dorongan algoritma platform digital pariwisata dan tuntutan mobilitas instan wisatawan. Kawasan yang semula berfungsi sebagai buffer zone antara wilayah adat dan destinasi wisata kini berubah menjadi enclave komersial, menciptakan benturan kepentingan antara industri pariwisata, komunitas lokal, dan kelestarian lingkungan. Di balik kemudahan layanan berbasis aplikasi, tersembunyi ancaman fragmentasi ruang hidup masyarakat Bali dan tekanan ekologis yang kian mengkhawatirkan.
Bali bukan satu-satunya yang menghadapi tekanan ini. Kota Lisbon di Portugal pernah mengalami lonjakan digital nomads dan gentrifikasi akibat Airbnb yang menyebabkan warga lokal terusir, mendorong pemerintahnya menerapkan regulasi ketat terhadap penyewaan jangka pendek. Barcelona menghentikan pembangunan hotel baru di pusat kota dan mendorong penyebaran wisata ke area lain. Bali perlu belajar dari kota-kota ini, dengan menerapkan regulasi zonasi yang partisipatif dan membatasi spekulasi properti.
Kota Tanpa Peta: Urbanisasi yang Tak Lagi Mengindahkan Tata Ruang
Data Badan Pertanahan Nasional (2024) mencatat bahwa lebih dari 33% lahan pertanian di Badung dan Gianyar telah beralih fungsi dalam lima tahun terakhir. Denpasar sebagai pusat kota mengalami lonjakan harga tanah hingga 250%, memaksa banyak warga lokal mencari hunian di pinggiran. Alih-alih sekadar pergeseran geografis, ini mencerminkan pergeseran sosial dari komunitas agraris ke enclave hunian pekerja digital dan wisatawan jangka panjang.
Yang mengkhawatirkan, pembangunan ini kerap terjadi tanpa infrastruktur dasar yang memadai: drainase buruk, minim transportasi umum, ruang hijau menyusut hingga di bawah ambang 30% yang direkomendasikan pemerintah. Fenomena ini menempatkan Bali pada risiko krisis ekologis dan kualitas hidup.
Mobilitas Digital dan Kemacetan Nyata
Transportasi digital semula hadir sebagai solusi, tetapi kini menjadi bagian dari masalah. Di Denpasar dan sekitarnya, kepadatan kendaraan telah mencapai 1.350 kendaraan/km² angka yang melampaui Jakarta Selatan. Jalan-jalan di Canggu, Seminyak, dan Sanur kini padat oleh armada ojek online dan kendaraan pribadi, menghambat mobilitas yang seharusnya dipercepat oleh teknologi.
Lebih parah lagi, wilayah seperti Bangli dan Karangasem belum menikmati akses mobilitas yang layak. Ketimpangan ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam menyediakan transportasi publik yang inklusif dan berkeadilan. Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan transportasi digital justru memperparah emisi karbon serta ketimpangan sosial.

Kebijakan yang Tertinggal dari Disrupsi
Perencanaan ruang dan sistem transportasi publik tampak tertinggal jauh. Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan nyaris tak menggigit. Layanan Trans Metro Dewata yang semestinya menjadi tulang punggung transportasi publik justru kalah saing dari ojek online karena tidak terintegrasi dan minim inovasi digital.
Padahal, kota-kota lain di Indonesia seperti Yogyakarta dengan konsep angkutan terpadu dan Jakarta dengan integrasi JakLingko telah menunjukkan arah yang lebih progresif dalam membangun ekosistem mobilitas cerdas.
Platform Mobility-as-a-Service (MaaS) milik Amsterdam yang menggabungkan tram, sepeda, dan pembayaran digital, dapat menjadi inspirasi bagi Trans Metro Dewata untuk bermitra dengan layanan ojek daring lokal. Kebijakan “Zero Car Growth” di Singapura, yang membatasi kepemilikan kendaraan pribadi sambil berinvestasi besar dalam infrastruktur transportasi, membuktikan bahwa pengurangan kemacetan dan inovasi bisa berjalan seiring. Program “Heritage Farming Zone” di Kyoto, yang mensubsidi lahan pertanian tradisional, bisa ditiru Bali untuk melindungi sistem irigasi subak sambil tetap membuka ruang untuk pertumbuhan.
Dari Pulau Tujuan ke Pulau Percontohan
Kini saatnya Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai percontohan nasional dalam menata mobilitas dan ruang di era digital. Untuk mencapainya, sejumlah langkah strategis perlu segera dijalankan. Pertama, integrasi antara layanan transportasi digital dan angkutan publik harus diperkuat. Skema last mile connection yang menghubungkan halte bus dengan hunian melalui aplikasi dapat menjadi jembatan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan mobilitas harian masyarakat.
Selain itu, penerapan konsep “15-minute city” di kawasan seperti Ubud, Sanur, dan Nusa Dua layak dijadikan pilot project. Dengan pendekatan ini, seluruh kebutuhan dasar warga seperti pasar, sekolah, dan layanan kesehatan dapat diakses dalam waktu 15 menit hanya dengan berjalan kaki atau bersepeda, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Penataan ulang zonasi wilayah pun perlu dilakukan secara partisipatif, berbasis data spasial terkini, dan melibatkan aktor-aktor lokal seperti desa adat, generasi muda, serta pelaku industri pariwisata.
Tak kalah penting, pemerintah harus mulai menerapkan pajak lingkungan yang progresif bagi aktivitas pembangunan yang berisiko merusak ekosistem, sembari memberikan insentif bagi mereka yang mengedepankan prinsip pembangunan ramah lingkungan. Dan akhirnya, kesadaran publik terhadap konsumsi ruang dan dampak gaya hidup digital perlu dibangun melalui edukasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, warga tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi turut menjadi aktor utama dalam menentukan arah dan makna pembangunan Bali ke depan.
Momen untuk Mengambil Kendali
Apa yang terjadi di Bali hari ini sesungguhnya bukan isu lokal. Ini adalah cerminan tantangan nasional dalam mengelola disrupsi digital, urbanisasi tanpa arah, dan ketimpangan akses terhadap ruang. Bila Bali gagal mengatasi ini, kota-kota lain dengan sektor pariwisata dan mobilitas digital tinggi bisa mengalami nasib serupa
Namun, jika Bali berhasil, maka pulau ini dapat menjadi laboratorium hidup kebijakan spasial dan mobilitas digital berkelanjutan untuk seluruh Indonesia. Keberhasilan Bali akan menjadi bukti bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Perubahan memang datang lewat genggaman. Tapi arah perubahan tetap harus ditentukan bersama. Kini saatnya Bali mengambil kendali.
kampungbet kampungbet