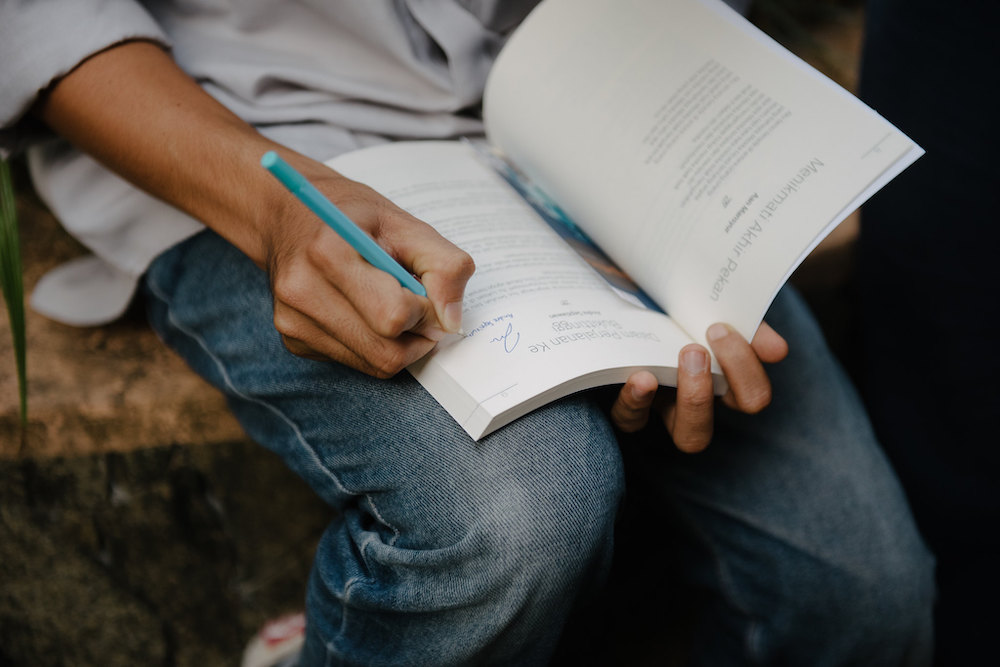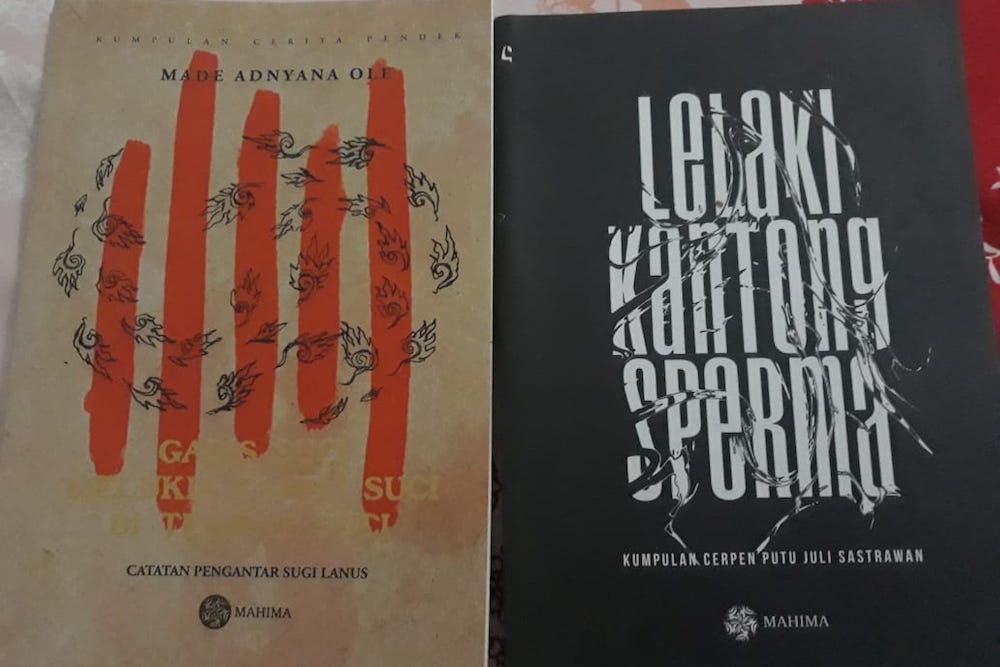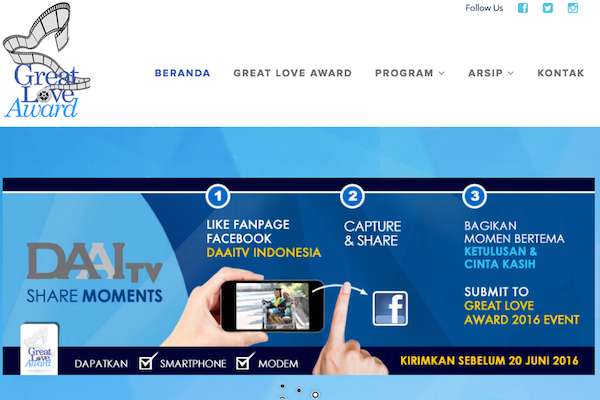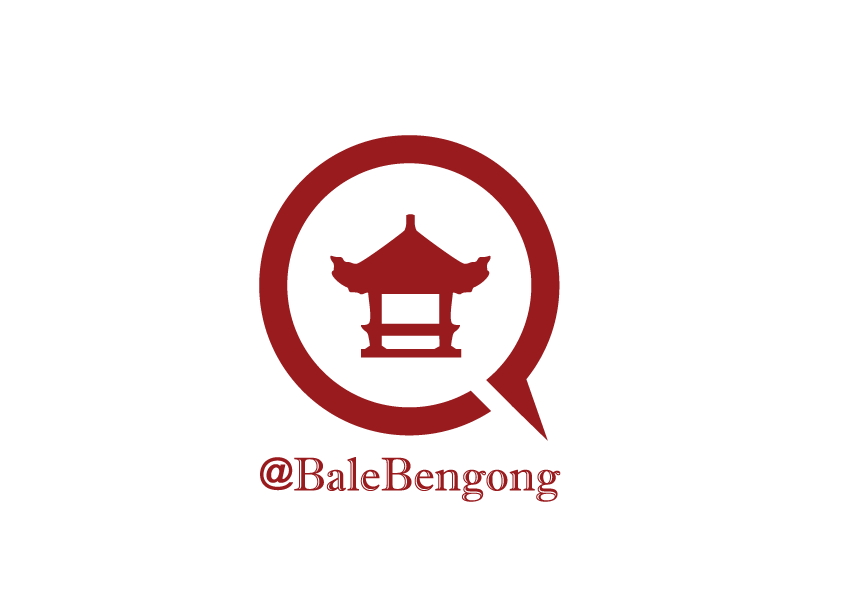Tahun ini, tema PKB ke-38 adalah Karang Awak. Ungkapan ini diambil dari kutipan karya Ida Pedanda Made Sidemen dalam puisi (geguritan) berjudul Selampah Laku. Karang Awak, dalam tafsir karya Ida Pedanda Made Sidemen, bermakna diri kita. Melihat diri. Refleksi.
Dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-38, makna Karang Awak direduksi menjadi tagline (interpretasi?): Mencintai Tanah Kelahiran.
Tema ini serupa dengan tema Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2011 Nandurin Karang Awak. Agar lebih bisa memahami apa makna Karang Awak, kami bagi kembali tulisan Sugi Lanus yang disampaikan dalam pembukaan UWRF 2011 lalu.
—
Nandurin Karang Awak diambil dari sebaris kalimat yang ditulis Ida Pedanda Made Sidemen dalam puisi (geguritan) berjudul Selampah Laku.
‘Karang‘ berarti tanah, ‘awak‘ berarti diri (di dalamnya mencakup diri saya, kamu atau pribadi lainnya), sedangkan ‘nandurin’ berarti mengolah atau menanam. Frase “nandurin karang awak” merupakan ucapan atau nasihat sang penyair kepada sang istri ketika memulai pengisahan perjalanan hidupnya, sebagaimana yang disurat dalam Geguritan Selampah Laku.
Kutipan sebait bait lengkap dari Geguritan Selampah lagu yang berisi ‘karang awak’ sebagai berikut:
“Beline mangkin, makinkin mayasa lacur, tong ngelah karang sawah, karang awake tandurin, guna dusun, ne kanggo ring desa-desa.”
Syair itu dapat diartikan:
“Kanda sekarang, bersiap menjalani hidup dalam kesederhanaan, tidak punya tanah sawah, pekarangan badan-lah yang (kita) tanami, menjalani hidup dengan pedoman pengetahuan dan kesahajaan pedesaan, sebagaimana berlaku di desa-desa.”
Entitas ‘karang‘, ‘awak‘ dan ‘tandurin‘ sebenarnya independen. Namun, dalam kehidupan, ketiganya justru saling tergantung satu sama lain, dalam relasi oleh manusia dengan alam dan budaya agraris. ‘Nandurin‘ menjadi representasi dari kegiatan pertanian, ‘karang‘ menjadi representasi alam, dan ‘awak‘ adalah representasi diri manusia.
Melalui gagasan ini, Ida Pedanda Made Sidemen mengajak setiap pembacanya untuk melihat ke dalam diri sendiri dan tidak lagi menoleh ke mana-mana untuk memulai hidup yang bersahaja.
Ketika beliau mengatakan bahwa “karang awake tandurin” ketika itu beliau menganjurkan kita untuk tak menoleh kemana-mana, bahkan tidak lagi perlu kita melanjutkan kalimat-kalimat dalam karya sastra beliau yang sedang kita baca: “Masuki diri sendiri, pahami diri, renungi sampai ke akar-akarnya diri”.
Beliau menulis sastra untuk berhenti “bersastra” lalu menuju “laku diri”.
Kesastraan kita, jika bercermin dari karya Selampah Laku, sejauh ini cenderung bersastra untuk ‘mendebat’. Menjadi rumit dengan diri. Peranda Made dalam karya-karya beliau–Selampah Laku dll– mengembalikan esensi kata ‘sastra’, yang berakar pada SAS-TRA, yaitu aliran yang membebaskan..
Beliau mengajak kita menuju ke aliran sastra yang mengalir di bumi bermuara di dalam hulu diri. Yang paling radikal, beliau mengajak kita terbebas dari sastra itu sendiri, setelah cukup mengantar kita di tepian diri, kita dimintanya meletakkan ‘perahu sastra’ itu di luar, untuk menjadi berani berhadap-hadapan dengan diri sendiri, merenungi diri.
Jika bandingkan dengan filsafat Barat, “Selampah Laku” adalah karya perenungan essensialis sekaligus ekstensialis. Esensi dan eksistensi diri direnungi, dimasuki, lebih jauh untuk ditanami (tandurin).
Bagi anak petani seperti saya, kata ‘karang‘ dan ‘awak‘ itu adalah ‘variable identitas’ dan ‘variable spiritualitas’; petani ‘mengada’ dengan adanya ‘awak‘ dan ‘karang‘. Jika petani ‘tanpa karang’ ia bukan petani. Jika petani tanpa ‘awak’, ia bukan manusia berkesadaran.
Ketika 2 kata ini (karang+awak) digabung menjadi frase “Karang awak“, frase ini telah berdiri dan mengkristal menjadi formula filsafati berakar pada masyarakat pertanian yang menjunjung harga diri petani, petani yang menempuh jalan ‘ketuhanan’ dengan cara memasuki diri. Menjadi petani, dengan berbekal petunjuk sastra filsafati ini artinya petani mencangkul dan menyemai benih-benih di ladang tegalan dan sawah di luar, sekaligus berladang-tegalan-sawah di dalam diri ‘karang awak‘.
Ida Pedanda Made Sidemen mewariskan karya-karya filsafati yang sangat mendalam. Kadang kita baru membacanya sepenggal-sepenggal, tapi sudah latah mendiskusikan dan pongah menjadikannya slogan atau pamflet; akibatnya kitapun terhantar menuju pemahaman “sepenggal-sepenggal”, dan melahirkan pola tingkah “setengah-setengah” (nyalah-nyalah).
Ida Pedanda Made Sidemen lahir pada tahun 1878 di Intaran, Sanur, Bali, dan berpulang pada tahun 1984. Selain menghasilkan geguritan, beliau juga mencipta kidung, teks religius, dan puisi tradisional yang biasa disebut kakawin. Selain dikenal luas sebagai penulis karya tulis di atas daun lontar, Ida Pedanda juga dikenal sebagai pengukir topeng, pembuat kulkul (kentongan dari kayu), arsitek tradisional atau undagi yang banyak merestorasi dan renovasi Pura-Pura di Sanur sampai Gianyar.
“Nandurin Karang Awak” adalah metafor dunia agraris, metafor yang memancing kerinduan kita untuk menengok hijau sawah dan kemuning tegalan. Ida Pedanda Made Sidemen mengajak kita kembali membumi. Setelah kita menginjakkan kaki pikiran kita di atas di bumi, beliau menyapa kita untuk ingat diri, kembali ke ‘awak’, yang ternyata di dalamnya menunggu bentangan ‘karang’ persawahan yang harus kita garap sendiri, dalam sunyi, dan harus kita garap sendiri. [b]