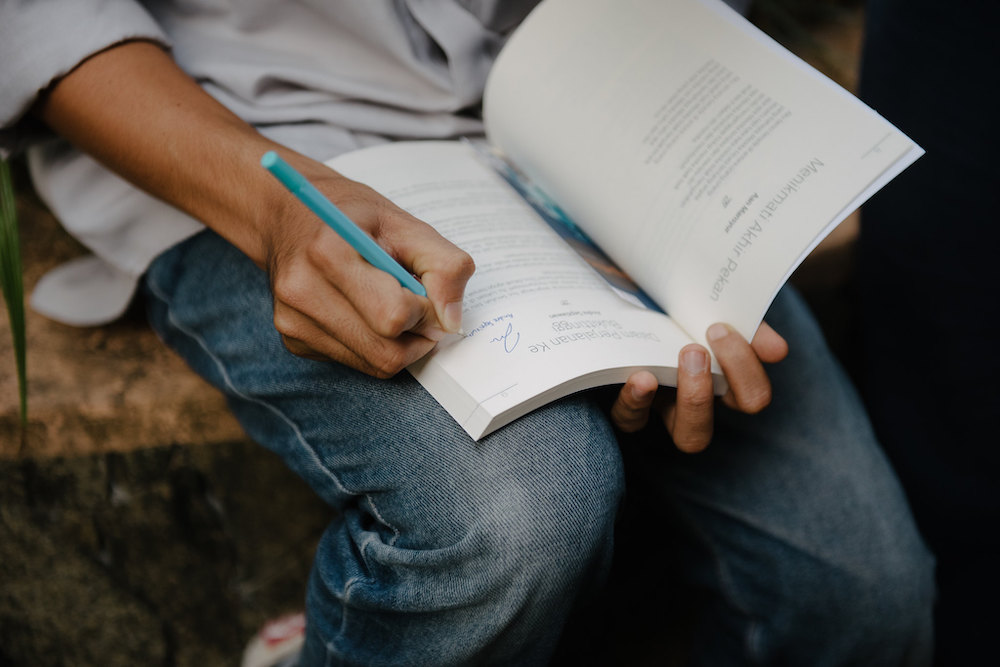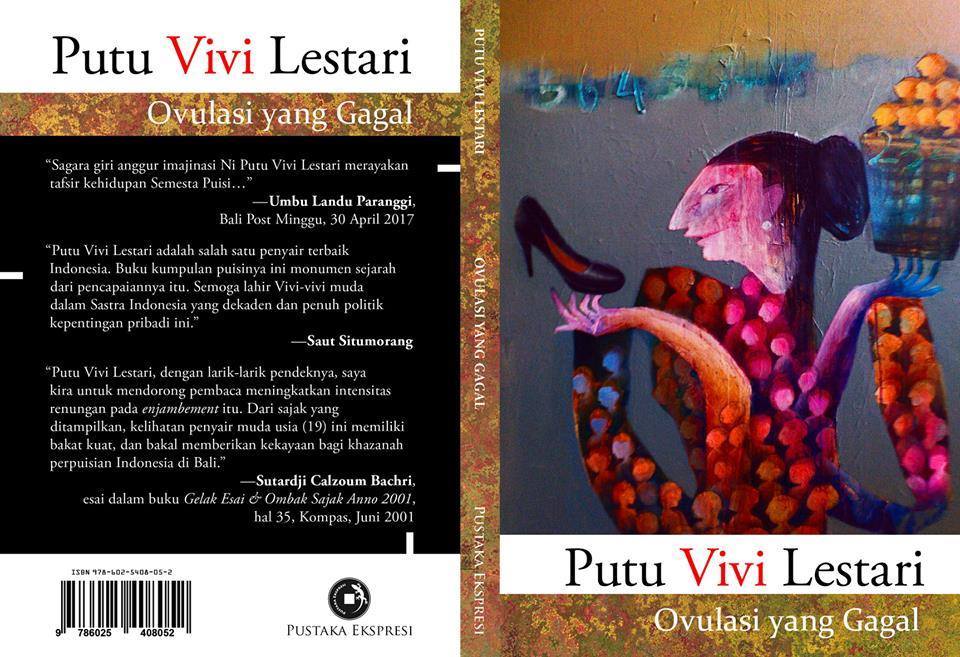Menulis cerita pendek dan menerbitkan novel tak membuatnya tinggi hati.
Jauh dari hiruk-pikuk publikasi membuat namanya dikenal hanya segelintir orang. Di tengah isu kanonisasi dalam dunia sastra yang mengemuka belakangan ini, agaknya benar fakta bahwa di Indonesia banyak penulis “tak bernama”; mereka bekerja dalam hening. Tak mau menonjolkan diri, menepuk dada dan selalu ingin diakui.
Namun, karya mereka tak bisa dipandang sebelah mata baik dari pencapaian maupun konsistensi dan ketekunan menulis.
Salah satu penulis itu adalah Ni Putu Dian Purnama Dewi. Saya mengenalnya sewaktu duduk di bangku kuliah, saat sering kelayapan di kampus Universitas Udayana (Unud) Sudirman, Denpasar. Nongkrong di markas Akademika, UKM Pers kampus yang banyak melahirkan penulis dan jurnalis andal. Meski bukan anggota aktif, saya dalam banyak kesempatan hadir dalam acara diskusi di sana. Ikut merasakan atmosfer intelektual dan pergolakan pemikiran khas mahasiswa.
Dian adalah anggota pers kampus itu. Pendiam dan tak banyak bicara, suka membaca dan menulis, menorehkan banyak prestasi sebagai mahasiswa Sastra Inggris kala itu.
Sejak 2014 ia mengelola lembaga kursus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta bahasa Bali untuk penutur asing di Kesambi, Badung. Bersama sang suami yang selalu mendukung kariernya sebagai guru, penerjemah dan penulis, mereka mendedikasikan diri pada dunia pendidikan. Juga membuka warung bernama Guru’s Corner, tempat yang menyenangkan untuk bersantai dengan panorama sawah dan menu yang membuat pengunjung ingin selalu datang kembali.
Berikut wawancara saya bersama penulis yang baru meluncurkan novel perdananya Astangga. Kami berbincang tentang perjalanan kepengarangannya, pentingnya buku dalam keluarga, kegelisahannya melihat banyaknya buku bajakan, dan menulis sebagai sebuah terapi psikologis yang sangat penting dalam mengekspresikan gejolak batin.
Sejak kapan Anda mulai menulis?
Saya suka menulis sejak dulu saat masih sekolah. Awalnya karena suka membaca, mulai dari komik, cerita pendek hingga novel. Ketika SMP tulisan pertama yang terpublikasi adalah puisi. Waktu itu dimuat di koran Wiyata Mandala, berkisah tentang peristiwa bom Bali. Puisi tersebut awalnya tugas sekolah, oleh guru saya dipilih yang terbaik lalu dikirim ke koran. Itu pertama kali tulisan saya dimuat di media.
Semenjak itu saya mulai terus menulis, dan saat SMA mulai menekuni cerita pendek. Pembaca awal adalah teman-teman saya. Mereka menyarankan untuk mengirim karya saya ke majalah dan koran, tapi saya belum percaya diri. Itu tahun 2003.
Saat masuk kuliah tahun 2006, cerita pendek saya dimuat pertama kali di Bali Post judulnya Suatu Fajar dengan Sakura. Berkisah tentang seorang laki-laki yang menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Ia tidak punya waktu untuk anak istri dan keluarganya. Pekerjaan baginya nomor satu, kemudian di hari tuanya dia jadi jauh dengan anak dan istrinya serta merasakan kesepian. Dia akhirnya dirawat oleh perawat di negeri sakura, tempat dia mendedikasikan pekerjaan selama hidupnya.
Terakhir saya menulis cerita pendek tahun 2011 untuk Bali Post juga. Selama ini saya menulis untuk harian tersebut selain di tabloid pers kampus Akademika Universitas Udayana di mana saya bergiat sewaktu mahasiswa.
Apakah kegemaran membaca ada pengaruh dari lingkungan keluarga Anda?
Ya. Bisa jadi karena di rumah saya banyak buku. Ayah saya seorang guru, beliau punya lemari penuh berisi buku, ada buku fiksi dan nonfiksi. Sejak kecil saya suka curi-curi baca di sana. Buka bukunya walau kadang belum mengerti isinya, seperti buku fisika dan astronomi. Itu menarik. Saya melihat gambar-gambar yang ada pada buku itu.
Ibu saya juga suka membaca. Dulu beliau pernah bertugas di sebuah perpustakaan SMA di Karangasem dan saya sering ikut. Bisa dibilang buku sudah jadi bagian dari hidup saya sejak kecil.
Selain puisi dan cerita pendek Anda juga menulis apa?
Saya menulis novel yang diambil dari salah satu cerita pendek yang pernah dimuat di Bali Post, judulnya Astangga. Novel itu adalah pengembangan dari cerita pendek yang pernah ada. Astangga bisa dibilang sebuah pelarian dari angan-angan yang nggak kesampaian. Saya tuh orangnya punya cita-cita tinggi, saya punya banyak mimpi dan tentunya sambil jalan nggak semuanya bisa tercapai. Jadi itu adalah ungkapan kekecewaan-kekecewaan atas apa yang saya targetkan atau mimpikan namun tidak tercapai.
Memang kalau sepintas kita lihat novel itu berisi kisah cinta antara dua orang, tapi sebenarnya yang mengakari adanya Astangga itu adalah kekecewaan atas obsesi yang tidak tercapai. Sama seperti Maya, salah satu karakter di novel tersebut yang begitu terobsesi untuk mencintai sosok Astangga yang digambarkan sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Tapi “membatu” karena dia diceritakan sebagai seorang pertapa yang tidak tergoda dan kukuh dengan meditasinya. Maya itu seperti kita yang punya mimpi, kita yang menginginkan sesuatu tapi sesuatu itu ada di depan mata tetapi tidak terjangkau.
Pada novel itu saya tidak menargetkan untuk memberikan pesan atau nasihat kepada pembaca. Hanya sebagai sebuah curahan perasaan, sebagai hal yang untuk dinikmati saja. Banyak orang ketika membaca Astangga itu bilang mereka terbawa karena mereka mungkin bisa related atau terhubung dengan perasaan yang ada pada novel itu.
Ada yang bilang novel Astangga memberikan motivasi walau memang tujuannya bukan untuk memberikan motivasi melalui kata-kata di sana. Ada juga yang bilang novel itu seperti puisi yang panjang, ketika mereka membaca seperti puisi yang berjumlah 108 halaman. Tanggapan dari para pembaca seperti itu.
Tentang kekecawaan atas mimpi dan obsesi tidak tercapai sebagai ide novel Astangga, apakah bisa dikatakan menulis adalah sebuah terapi?
Betul sekal. Menulis adalah sebuah terapi. Saya melihat kecenderungan penulis yang karya tulisnya imajinatif dan emosional, mereka memendam sesuatu di dalam dirinya. Kita bisa melihat Virginia Woolf, Ernest Hemingway atau Haruki Murakami. Mereka seperti merefleksikan kehidupan di dalam kepalanya ke dalam karya sastra. Itu kalau kita lihat dari dalam.
Kalau kita lihat dari segi terapi menulis seperti saya bilang tadi merupakan refleksi dari dalam keluar. Itu bisa menjadi ruang bagi seseorang yang kalau sekarang banyak orang yang mengalami depresi. Dengan menulis dia bisa mengekspresikan dirinya melalui tulisan jika tak berani bicara dengan orang atau merasa sungkan untuk berkomunikasi dengan keluarga misalnya, dia bisa melakukan itu dengan menulis. Karena kalau nggak dikeluarin sakitnya itu di dalam, tekanan-tekanan yang kita terima juga perasaan batin kalau nggak dikeluarin bisa menjadi penyakit di dalam diri.
Jadi menulis adalah cara yang sangat bagus untuk mengekspresikan gejolak batin seseorang.
Novel Astangga diterbitkan secara mandiri?
Betul, novel itu adalah proyek berdua, saya dan suami saya. Kebetulan dia suka menggambar dan seorang ilustrator. Jadi itu proyek kami berdua dengan dana yang terbatas. Kami sudah coba mengirim naskah novel itu ke penerbit besar tapi belum ada respon. Jadi kami putuskan untuk menerbitkan secara mandiri.
Daripada menganggur di komputer, mending kita sharing, berbagi dengan orang lain yang mungkin mau membaca dan menikmati karya sastra. Kami tak mau menunggu punya dana besar dulu baru orang lain bisa menikmati bacaan yang kami buat atau menunggu ada penerbit yang berkenan untuk menerbitkan.
Selain menulis novel apakah ada proyek lain ke depan?
Rencana kami ada dua. Pertama, kami membuat buku dongeng untuk anak-anak. Buku itu tidak hanya diperuntukkan untuk pembaca Indonesia tapi juga pembaca asing yang baru belajar bahasa Indonesia. Story line-nya sudah selesai tapi gambar masih dalam proses. Kami buat bilingual, dalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Selain itu, saya juga menulis novel kedua, judulnya Dedalu. Novel ini bercerita tentang lelaki Bali yang merantau demi meraih cita-citanya sebagai wartawan sebuah media ternama di Indonesia. Untuk itu ia harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumah dan keluarganya di Bali.
Saat ini banyak buku sastra terbit yang ditulis oleh penulis muda Bali. Tak hanya penulis laki-laki tapi juga penulis perempuan. Bagaimana Anda melihatnya?
Saya senang sekali karena itu seperti titik di mana banyak orang mau mengekspresikan dirinya dengan cara menulis. Berarti literasi kita, ketertarikan orang Indonesia atau orang Bali terhadap karya sastra itu meningkat. Dan orang tidak hanya menikmati saja sekarang tapi menulis juga. Itu sesuatu yang patut diapresiasi.
Apakah ada perbedaan penulis Bali kini dengan penulis generasi terdahulu seperti misalnya Oka Rusmini dan Cok Sawitri?
Saya melihatnya dari segi penulisan. Pemilihan kata dan tema dari penulis Bali generasi sekarang lebih modern. Tapi jika kita membaca buku terkini Oka Rusmini Koplak, saya pikir beliau mulai tidak hanya mengangkat tema-tema seperti perempuan zaman dulu tapi juga ada unsur apa yang terjadi di masa kini, apa yang menjadi fenomena atau peristiwa kekinian. Jadi saya lihat beliau mengikuti alur dan konsisten mengangkat tema-tema yang terjadi di masyarakat Bali.
Kalau Cok Sawitri saya lihat jika beliau menulis dalam sekali, lebih pada tema yang berkaitan dengan filsafat dan tradisi Bali. Itu perlu riset mendalam, tidak hanya sekadar menulis tapi juga harus mengalami, harus meriset lontar atau sumber-sumber tradisi, dan beliau punya akses ke sana.
Kalau generasi muda sekarang temanya lebih pada sosial kemasyarakatan seperti tentang presiden Jokowi dalam bahasa Bali. Itu temanya modern dan pembaca generasi sekarang lebih merasa terhubung. Ada juga tema spiritual misalnya sebuah cerita tentang Sang Suratma atau Dewa Kematian dari penulis belia Carma Citrawati.
Saya berpikir itu tema sudut pandang yang sangat baru. Dia berani mengambil sudut pandang yang tidak biasa ditulis penulis lain, karena biasanya orang takut kalau sudah masuk ke tradisi dan ketuhanan, nanti banyak yang tersinggung. Tapi yang ini saya lihat baru dan dia berani.
Ada anggapan penulis perempuan Bali ketika setelah menikah produktivitas menulisnya menurun dibandingkan saat mereka mulai menulis sejak menjadi siswa atau mahasiswa. Bagaimana menurut Anda?
Karena saya juga punya kesibukan lain ketika menikah, ada kewajiban adat dan kewajiban keluarga dan untuk anak terutama saya rasa support atau dukungan dari keluarga sangat diperlukan untuk produktivitas penulis perempuan. Saya sangat beruntung karena punya pasangan hidup yang mau berbagi kewajiban, jadi saya tak harus rutin membanten, harus cari kerja dan mengurus anak yang semua dilakukan sendiri.
Kami terbiasa berbagi tugas. Ketika saya mau menulis suami saya mengerjakan pekerjaan domestik yang mesti diselesaikan, jadi kami bisa berbagi. Tetapi banyak orang yang memang karena merasa sangat bertanggung jawab denga kehidupan ketika menikah dengan kesibukan-kesibukan rumah tangga dan mungkin tidak ada yang mengimbangi dia. Itu membuat itu bisa membuat dia berhenti menulis.
Karena terus terang kalau kita menulis perlu mood, tak bisa begitu duduk di depan komputer ide tulisan mengalir begitu saja. Pasti harus ada waktu kontemplasi atau permenungan, diam dulu dan berpikir kemudian membaca kembali, mencari mood baru kita menulis lagi. Dan itu perlu waktu dan dukungan dari pihak lain juga untuk mengkondisikan seseorang bisa menulis. Jadi tergantung dari pasangan dan keluarga pasangan.
Selain itu yang terpenting tergantung diri, kalau dia memang cuek, “ya udah aku nulis aja aku nggak peduli sama yang lain” cuma pasti akan ada yang terbengkalai jika seperti itu.
Tentang pilihan hidup untuk menjadi penulis sebagai profesi menurut Anda apakah bisa diwujudkan?
Total sebagai penulis bisa, tapi kalau kita berpikir tentang kemapanan itu bisa berbeda. Saya pikir untuk Indonesia sulit, karena meskipun apresiasi terhadap profesi penulis itu kini ada, banyak pujian datang, tapi apresiasi dari segi keuangan itu masih kurang. Saya mengerti media juga punya kesulitan dengan hal itu, jadi tidak bisa memberikan value of money cukup untuk penulis ketika mereka mengkontribusikan tulisannya di sebuah media cetak atau media online.
Saya sendiri mengalami ketika menulis mendapat honor sekian lalu bukannya naik tapi malah turun sampai kemudian rubrik sastra tidak ada lagi. Kemudian ketika kita punya karya, banyak yang tidak bisa mengapresiasi keberadaan buah pikiran kita dengan adanya buku bajakan.
Padahal satu-satunya income atau pendapatan seorang penulis itu dari dari royalti sementara kalau bukunya digandakan tanpa izin dan banyak orang lebih memilih itu ketimbang buku aslinya yang notabene mungkin itu lebih murah atau bahkan ada yang mau fotokopian itu menjadi kendala.
Saya pernah membaca kutipan: “Kalau mau jadi orang kaya tidak usah menjadi penulis”. Jadi kalau memilih menjadi penulis kita harus benar-benar kuat untuk tidak tergoda dengan gaya hidup atau mengikuti standar kebutuhan pada saat ini. Istilahnya kalau di Bali kanggo-kanggoang (menerima apa adanya).
Ada tips untuk generasi muda yang mulai menulis?
Saya pernah mendapat kartu pesan yang isinya menarik dari Geg Ary Suharsani, penulis perempuan Bali yang selain menulis juga bekerja: Kalau kamu ingin menulis, tulis saja. Itu menjadi motivasi berharga bagi saya, ketika saya punya sesuatu yang ingin saya tulis saya segera corat-coret dalam notebook, tidak harus menunggu sekian lama di depan komputer. Ketika ide atau inspirasi muncul tulis saja dulu, mau jadi apa nantilah kalau sudah ada waktu yang lebih panjang.
Sewaktu merilis novel Astangga saya sempat mendapat pertanyaan dari seorang teman yang ingin menulis tetapi terkendala kesibukan domestik seperti mengurus anak, membuat banten atau sarana upakara dan mengajar karena dia guru honorer. Saya katakan pada teman saya itu ketika kamu punya ide, ketika rangkaian kata pertama muncul segera catat di suatu tempat, misalnya di ponsel yang kita bawa ke mana-mana. Nanti jika ada waktu lebih luang misalkan malam menjelang tidur catatan itu bisa dibaca lagi, di sana waktu kita untuk mengembangkan saat kita punya waktu lebih untuk duduk dan bersantai.
Sementara kalau tulisan yang lebih panjang seperti cerita pendek atau mungkin novel, saran saya buatlah sebuah kerangka, karena itu akan menjaga kita untuk tetap pada landasan dan ide awal.
Kalau tanpa kerangka takutnya nama karakter biasanya kita ubah, dan lupa pada tema yang di awal ingin kita bangun. Ceritanya juga akan bisa seperti cerita sinetron, tambal-sulam di sana-sini. Jadi harus ada kerangka awal, dari situ baru kita bisa masuk pelan-pelan dan ketika terakhir naskah novel selesai baru kita revisi lagi agar lebih terstruktur. [b]