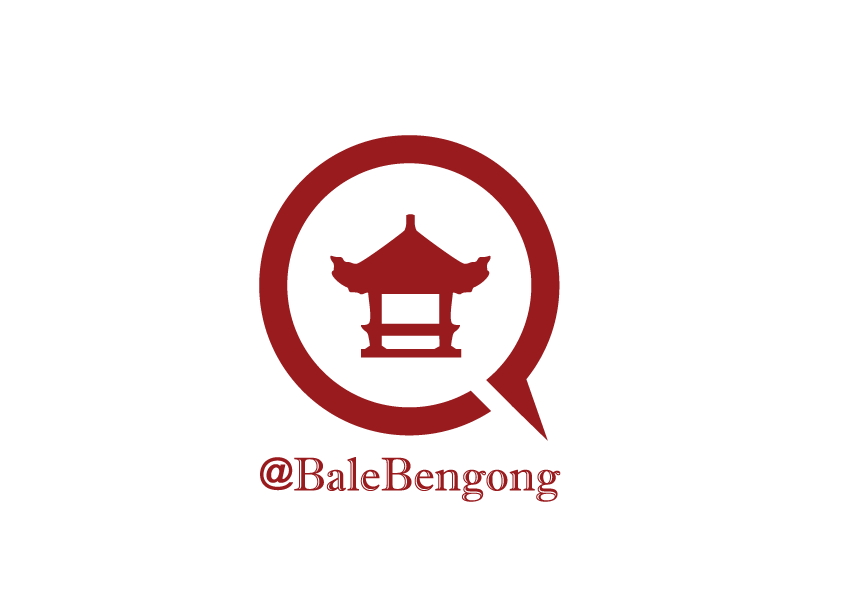https://www.instagram.com/p/CyVdyxGyrHC/?igshid=MzY1NDJmNzMyNQ==
Oktober lalu saya datang ke pemutaran film dokumenter “Memukul Jatuh Mengadili PLTU.“ Film ini merupakan hasil kolaborasi antara TV Tempo dan Trend Asia. Pemutaran film digelar di MASH Denpasar, Minggu 13 Oktober 2023.
Film dokumenter pendek berjudul “Memukul Jatuh Mengadili PLTU“ agaknya menjadi potret setitik cahaya di tengah gelap menyoal sumber energi dan keberlanjutan lingkungan. Film ini bercerita mengenai kemenangan masyarakat Cirebon pada gugatan pembangunan proyek PLTU Tanjung Jati A, di Jawa Barat.
Yang paling menarik dari kemenangan ini tentu saja adalah bagaimana hakim yang memutuskan perkara ini mempertimbangkan dampak pemanasan global dan perubahan iklim dalam putusannya. Hal ini bisa menjadi preseden yang baik bagi perkara serupa di masa mendatang.
Selain pemutaran film, ada juga diskusi kecil untuk mengulik lebih dalam terkait film yang ditayangkan.
Diskusi film dokumenter “Memukul Jatuh Mengadili PLTU“ menghadirkan, Dewa Putu Adnyana, Praktisi Hukum, Oktaria Asmarani seorang Penulis dan Peneliti, Suriadi Darmoko dari Juru Kampanye 350.id dan Wahyudin (Iwank), Direktur Walhi Jawa Barat yang hadir melalui sambungan zoom.
Setitik Harapan dari Cirebon
Wahyudin atau akrab disapa Iwank, selaku direktur WALHI Jawa Barat menceritakan kembali proses perjuangan masyarakat Cirebon menolak PLTU Tanjung Jati A. Perlu diketahui, sudah ada dua PLTU di kawasan ini yaitu, PLTU Cirebon 1 dan sedang dibangun PLTU Cirebon 2. Tak cukup dengan dua PLTU tadi, pemerintah berencana membangun PLTU Tanjung Jati A, sebut Wahyudin.
Wahyudin memberikan latar belakang mengapa pemerintah ingin membangun PLTU Tanjung Jati A. Salah satu alasan pencanangan PLTU baru ini adalah untuk mencapai proyeksi 35 ribu megawatt untuk kebutuhan listrik di Jawa-Bali. Hal ini dilakukan dalam skema proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Wahyudin, ada tiga wilayah yang masuk dalam lokasi rencana pembangunan PLTU yaitu, PLTU 1 Pelabuhan Ratu, yang kedua PLTU 1 Indramayu dan PLTU Tanjung Jati A di Cirebon.
“Nah, yang PLTU Tanjung Jati A inilah yang kami menangkan gugatannya,” kata Wahyudin, selaku pendamping warga yang mengajukan gugatan.
Menilik kembali bagaimana gugatan ini dimenangkan, Wahyudin bercerita bahwa gugatan ini mempunyai banyak tantangan. Mulai dari aspek regulasi, hingga kriminalisasi terhadap warga melalui UU ITE.
“7 orang dipenjara dengan 2 pasal karet yang kemudian dituduhkan kepada masyarakat yang sedang berjuang membela hak, membela lingkungan, menyelamatkan manusia, menyelamatkan lingkungan baik di darat maupun di lautan,” paparnya.
Dia kemudian mengemukakan bahwa pengajuan gugatan ini salah satunya bermula dari ditemukannya pelanggaran dari dokumen perizinan yang sudah expired atau kadaluarsa. Selain itu, draft gugatan juga menyoal mengenai bentuk-bentuk kerugian negara, ada juga terkait perusakan lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia.
PTUN Bandung yang mengadili gugatan ini sendiri mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan warga. Ketua Tim Advokasi Keadilan Iklim, Meiki Paendong, menilai putusan ini seakan menjadi setitik harapan agar pemerintah lebih serius mencegah perubahan iklim di Indonesia terutama akibat pembangunan PLTU.
“Nah ini sejarah yang paling kita banggakan, ketika hakim memiliki perspektif seperti itu (perubahan iklim dan kerusakan lingkungan) dan patut dicontoh oleh masyarakat yang sedang berjuang di wilayah lain saat ini,” tambah Wahyudin atau Iwank, Direktur WALHI Jawa Barat.
Sejatinya perjuangan penolakan masyarakat terhadap kehadiran PLTU telah dimulai ketika pembangunan PLTU 1 Cirebon, PLTU 2 Cirebon, hingga rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A. Wahyudin menyebut, pada prinsipnya, masyarakat memang tidak menghendaki berdirinya PLTU yang akan merampas ruang hidup, alih fungsi lahan, serta menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekitar.
“Otomatis ketika ada pembangunan PLTU terganggu kehidupannya, terganggu kesehatannya, kualitas udaranya semakin buruk, juga menyebabkan suhu di daerah mereka itu menjadi panas dan tidak nyaman, gersang dan lain sebagainya,” jelas Wahyudin.
Di sisi lain, Wahyudin menuturkan, dalam perjuangannya menolak PLTU Tanjung Jati A, Pemerintah malah merespon keluhan dan aspirasi masyarakat dengan pembungkaman, intimidasi bahkan berujung kriminalisasi.
Pembukaman dan intimidasi membuat penolakan masyarakat jadi melemah, namun Wahyudin menyampaikan bahwa, mulai dari PLTU 1, PLTU 2 hingga PLTU Tanjung Jati A, masyarakat tidak pernah menghendaki dan menyetujui pembangunan PLTU mengingat dampak yang begitu besar yang mereka rasakan.
Wahyudin juga menggaris bawahi bahwa praktek energi atau industri ekstraktif ini bukan hanya kotor cara produksinya, namun, juga kotor dalam hal proses perizinan yang sering melibatkan suap dan korupsi.
Selain menyebabkan kerusakan lingkungan dan mempercepat perubahan iklim, pembangunan PLTU Tanjung Jati A menurut WALHI Jawa Barat tidak ada urgensinya. Karena menurutnya, untuk ketersediaan energi listrik telah melebihi atau sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Barat berdasarkan RUED atau Rencana Usaha Daerah dan RUPTL PLN dengan Mikrohidro, PLTA, dan sebagainya.
Selain itu, untuk kebutuhan energi di Jawa Bali, saat ini juga sudah melebihi atau over supply di angka 6 Gigawatts.
“Tapi anehnya, celakannya juga pemerintah sampai hari ini terus memaksakan untuk pembangunan PLTU yang ekstraktif, yang kotor, yang berbahan fosil, yang itu berdampak secara signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan maupun juga dampak mata pencaharian serta kesehatan masyarakat,” Ujar direktur WALHI Jabar tersebut keheranan.
Kembali soal cerita dan setitik harapan mengenai kemenangan masyarakat Cirebon atas dibatalkannya pembangunan PLTU Tanjung Jati A, menurut Wahyudin, film ini menggambarkan bagaimana proses perjuangan masyarakat masyarakat di Cirebon dalam memukul jatuh PLTU serta mengadili PLTU yang prakteknya tidak hanya kotor secara industri, tapi praktiknya pun juga kotor.
Menengok Kembali ke PLTU di Bali Utara
Tidak seberuntung gugatan PLTU Tanjung Jati A di Cirebon, gugatan atau sengketa PLTU di Bali Utara atau PLTU Celukan Bawang mengalami nasib yang berbeda. Seperti yang diketahui, gugatan tersebut berakhir dengan penolakan majelis hakim terhadap penundaan pelaksanaan pembangunan pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II.
Dewa Putu Adnyana, Praktisi Hukum dan pengacara di LBH Bali menceritakan panjang lebar perihal sejarah pembangunan PLTU Celukan Bawang. Dia juga bercerita lebih detail mengenai gugatan terhadap izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang Tahap II 2018 lalu.
Sebenarnya tak sampai di situ, Dewa bercerita bahwa warga bersama LBH Bali melakukan proses banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, namun hasilnya sama yaitu menguatkan putusan PTUN Denpasar.
Melalui penjelasan Dewa, penolakan hakim terganjal di syarat formil pengajuan gugatan. Hal ini menurutnya sangat disayangkan mengingat syarat materiil menurutnya sudah cukup kuat.
Menengok kembali dampak PLTU Celukan Bawang, berbagai laporan menyebutkan bahwa PLTU membawa dampak dan berbagai masalah lingkungan, ekonomi, kesehatan dan sosial. Liputan yang dilakukan Mongabay, mengungkap berbagai tanaman masyarakat mengalami kerusakan. Selain itu, beberapa warga juga mengaku menjadi kerap sakit dan mengalami gangguan pernafasan. Di sisi lain, nelayan juga menuturkan bahwa tangkapan ikan di laut juga semakin berkurang.
Untuk menambahkan, beberapa laporan jelas menyebut bahwa PLTU atau pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar paling berdampak terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa langsung terhadap polusi udara, emisi karbon, penggunaan air, hingga pemindahan satwa.
Balebengong juga merilis laporan panjang soal Sengketa PLTU Celukan Bawang, dalam laporan tersebut juga disebut bahwa kondisi pasokan listrik di Bali mengalami kelebihan. Bahkan, PLTU Celukan Bawang mengirim kelebihan listrik ke Jawa dan Jakarta. Sebagai tambahan, dalam laporan tersebut peneliti dari Greenpeace juga menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada batubara sebagai sumber energi.
Ketergantungan Energi
Suriadi Darmoko telah lama bergelut di isu lingkungan, pernah menjadi ketua WALHI Bali, kini dirinya merupakan juru kampanye 350.id. Moko, sapaan akrabnya menyoroti beberapa poin. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap energi berbahan fosil, dan atau batubara.
Dia mengingatkan kembali bahwa, kebergantungan terhadap energi fosil atau batu bara sebagai sumber energi bisa dibilang sebuah anomali. Mengingat bahwa produksi dari sumber energi fosil maupun batubara tidak berada di Bali.
“Nah, kita bergantung banget sama industri energi fosil, tetapi sebenarnya terutama Jawa-Bali itu nggak punya supply-nya. Kan supply-nya nggak entah dari Kalimantan atau dari Sumatra,” jelasnya.
Dari hal ini, menurut Darmoko, walaupun Bali mewacanakan dan memberikan label pariwisata hijau, green, eco, berkelanjutan, atau apapun istilahnya, kalau dicek kembali emisi dari sektor tenaga listriknya berasal dari sumber yang “kotor” seperti, batubara.
Mengaitkan kembali soal ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan batubara dengan over-supply listrik Jawa-Bali yang telah dibahas sebelumnya, akar permasalahan ini menurut Darmoko karena miss management pengelola kelistrikan negara.
Alhasil, untuk mengatasi kelebihan produksi energi listrik, menurut Darmoko PLN tidak sekali memberi saran untuk boros menggunakan listrik. Moko menyebut pemerintah beberapa kali pernah menyarankan untuk menambah jumlah AC di rumah, membagi kompor induksi atau kompor listrik, mendorong penggunaan kendaraan listrik, hingga membagi rice cooker.
Hal ini menurut Darmoko menjadi sangat aneh ketika dahulu pelajaran SD menganjurkan untuk hemat listrik, sekarang malah berkebalikan untuk menggunakan listrik lebih banyak alias boros.
Menurut Darmoko, bagian itulah yang menunjukan bahwa ada mismanagement yang terjadi di dalam tubuh PLN. Dia mengatakan, proyeksi pertumbuhan energi yang dilakukan dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan.
“Mereka gagal memprediksi kebutuhan energi, salah satunya karena ada perkembangan teknologi. Terutama di efisiensi alat-alat kelistrikan,” kata Darmoko.
Kemudian dia juga menjelaskan bahwa PLN juga terjebak skema take or pay, karena perjanjian jual beli listrik antara PLN dan IPP (independent power producer) terikat pada produksi, bukan pada konsumsi. Artinya, ketika alat kelistrikan menjadi semakin efisien, konsumsi listrik menjadi menurun. Namun, di sisi lain PLN tetap harus membayar produksi listrik yang telah ditransaksi.
Keadilan Gender dalam Sumber Energi dan Perubahan Iklim
Oktaria Asmarani, seorang penulis dan peneliti yang menghadiri pemutaran film dan diskusi menyampaikan bahwa dirinya senang dengan film yang ditayangkan. Menurutnya, film “Memukul Jatuh Mengadili PLTU” memberinya harapan.
Dia menilai, kerja-kerja advokasi oleh berbagai organisasi yang bergiat di lingkungan hidup memberi dampak nyata. Meskipun ada beberapa yang masih belum menemui keberhasilan.
“Menurut saya hal-hal yang seperti itu juga tetap perlu dirayakan, dan menjadi pengingat yang baik untuk kita bahwa masih ada harapan,” ujar Rani, saapan akrabnya.
Pengabulan gugatan yang menggunakan pertimbangan perubahan iklim bagi Rani cukup mengejutkan. Dalam film ditampilkan bagaimana masyarakat memang merasakan sendiri perubahan yang ada. Mereka merasakan perbedaan kondisi lingkungan yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari. Melalui hal inilah, menurut Rani kita bisa memahami masalah yang terjadi.
“Karena ketika testimoni itu berdasarkan dari masyarakat, dan itu mungkin terkesan sangat kecil ya, justru itu yang menjadi powerful karena memang kerap kali isu-isu tentang perubahan iklim itu menihilkan atau mengenyampingkan testimoni yang berasal dari keseharian masyarakat,” jelasnya.
Menurut Rani, harapannya adalah bagaimana “Memukul Jatuh Mengadili PLTU” dan apa yang diperjuangkan masyarakat Cirebon bisa menjadi pelajaran dan diduplikasi di wilayah lain di Indonesia.
Kemudian, Rani juga menggarisbawahi bahwa suara perempuan perlu mendapatkan ruang untuk didengarkan. Menurutnya, jika berbicara menyoal lingkungan hidup atau dalam hal ini sesuatu yang rigid yaitu sumber energi seperti PLTU, dia mempunyai asumsi bahwa permasalahan gender melekat di sana. Rani beralasan, menurutnya perempuan biasanya paling banyak berurusan dengan keluarga dan urusan domestik.
“Dan ketika berurusan dengan domestik pemenuhannya adalah tentang makanan, tentang air, tentang udara, dan lain sebagainya,” terangnya.
Dalam sebuah sesi dengan tema Perempuan dan Perubahan Iklim, Rani juga menjelaskan bahwa terkait perubahan iklim, perempuan cenderung terdampak langsung. Dia menambahkan, perubahan juga iklim berdampak jauh lebih besar di negara berkembang, komunitas lokal dan masyarakat adat.
Bagi Rani, di tengah masyarakat yang masih berada di dalam ketimpangan gender, ketika perempuan diasumsikan sebagai makhluk yang pasif, pekerja domestik, second sex, dampak perubahan iklim hanya memperkuat masalah yang telah ada.
Beberapa faktor menurut Rani yang menyebabkan perempuan cenderung mendapatkan dampak dari perubahan iklim adalah seperti kondisi sosio-kultural atau beban ganda, diskriminasi aturan, ketimpangan bidang teknologi dan informasi, dan kondisi biologis.
Sebagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap perempuan, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan perempuan dan kelompok marginal mendapatkan akses dan kontrol, serta partisipasi dan manfaat dalam pembangunan.
Selain itu, dia juga menekankan keterbukaan informasi dan edukasi terhadap perempuan dan kelompok rentan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pemberdayaan. Perlu juga untuk melakukan peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membuat peraturan yang ramah gender dan mempunyai perspektif gender.
Ide dan solusi Alternatif
Terkait film “Memukul Jatuh Mengadili PLTU,” dan bagaimana pemerintah masih berencana membangun PLTU, menurut Darmoko hal ini malah kontradiktif. Mempertimbangkan oversupply, dan energi fosil, batu bara, dan minyak bumi merupakan sumber krisis iklim yang sedang dunia hadapi.
Dia mengatakan bahwa dalam seratus persen elektrifikasi yang pemerintah klaim, nyatanya masih ada kampung-kampung yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Di tengah gemerlap pariwisata di Bali selatan, hingga tahun 2022 lalu ada wilayah di Desa Ban, di Karangasem masih belum teraliri listrik.
Selain belum semua daerah yang mendapatkan aliran listrik, salah satu masalah yang sering timbul menurut Darmoko adalah sistem kelistrikan yang ketinggalan zaman atau masih jadul. Dia memberikan contoh Kampungnya di Probolinggo, dia mengatakan jika angin sedikit listrik akan langsung padam. Alhasil, menurut pengamatannya, orang-orang yang tinggal di kampung, kerugiannya menjadi berlipat.
“Alat-alat listriknya cepat rusak. Karena sistemnya tidak bagus,” jelasnya.
Di sesi tanya jawab, dengan keadaan demikian serta berkaitan dengan transisi energi, “apakah saat ini infrastruktur sudah siap untuk melakukan transisi energi?”
Darmoko balik bertanya, “Secara anggaran, mau enggak?”
Dia kemudian menjelaskan bahwa jika diberi pemahaman dan pengetahuan yang memadai, dia meyakini bahwa tidak ada yang tidak siap. Dia memberikan contoh salah satu Kampung di Kulon Progo Yogyakarta yang listriknya bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
PLTMH ini beroperasi dan bekerja dari saluran irigasi sungai yang ada di Kulon Progo.
Darmoko bercerita bahwa yang mengoperasikan PLTMH ini adalah seorang petani bernama Pak Erjo yang memulai semuanya dari nol.
“Jadi, bukan lagi seberapa siap kita mengimplementasikan. Kalau kita tidak mau, nggak ada siap-siapnya. Nah, memang political will-nya, kemauannya memang nggak mau,” terangnya.
Lalu apa ide dan solusi dari ketergantungan energi “kotor” seperti batubara dan fosil yang telah terjadi? Darmoko mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa organisasi masyarakat mendorong supaya pendanaan untuk transisi energi dilakukan secara besar-besaran.
“Industri energi fosil ini kotor, tadi sudah disebut prakteknya kotor, produksinya juga kotor. Nah, kalau transisi energi kita ke energi terbarukan, maka praktek penggusuran, pengalihan lahan dan lain-lain tidak terjadi ketika kita mengimplementasikan energi terbarukan,” kata Darmoko.
Kemudian, dia memberi sedikit gambaran yang bisa dilakukan untuk transisi energi. Dia mengatakan, yang bisa dilakukan adalah dengan menutup PLTU atau melakukan pensiun dini serta mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor ketenagalistrikan dari pembangkit energi listrik terbarukan berskala komunitas.
Darmoko menyebut ada banyak contoh bagaimana pembangkit energi terbarukan berbasis komunitas yang berjalan dan tanpa terkoneksi dengan grit besar PLN. Menurutnya, transisi energi harus dimulai dengan mengurangi ketergantungan pada pada IPP (independent power producer) skala besar seperti PLTU. Yang dia harap, Independent Power Producer (IPP) bisa datang dari RT5, Desa A, atau Kabupaten C.
“Jadi, pembangkit energi terbarukan dan terdesentralisasi, dan itu saya kira banyak contohnya, hal itulah yang jadi bagian dari tawaran dan solusi yang coba kita bangun,” kata dia.
Terkait dengan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT), baru-baru ini pemerintah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung atau Floating Solar PV berkapasitas 192 Mega Watt peak (MWp). Dikatakan, PLTS ini merupakan PLTS apung terbesar di Asia Tenggara.
Kabar ini tentu menjadi angin segar dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, Portugal juga baru saja melakukan uji coba untuk mengoperasikan jaringan listrik tanpa bahan bakar fosil dan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan selama enam hari berturut-turut. Dan hasilnya, selama seminggu, negara dengan populasi sekitar 10 juta orang ini memenuhi kebutuhan energi bagi warganya dengan tenaga angin, hidro, dan surya.