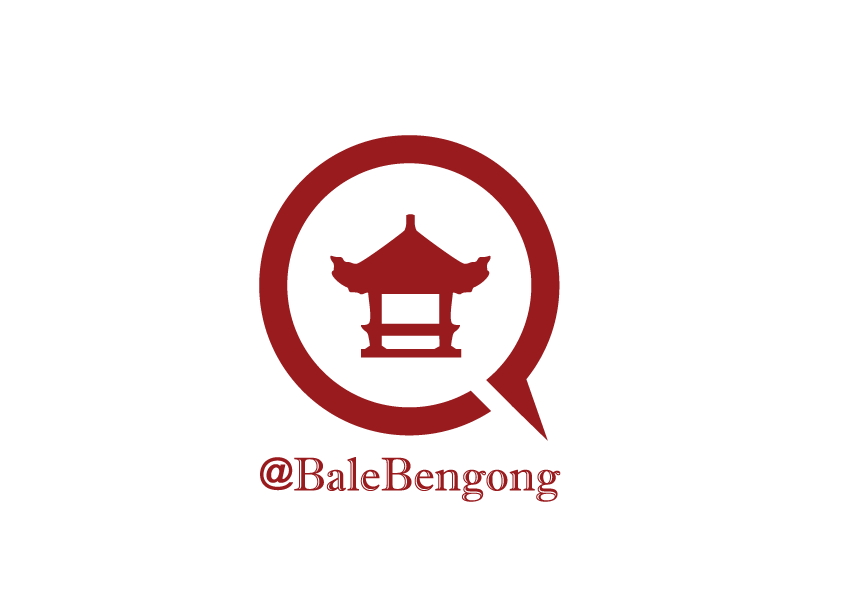Pekan Iklim Balli pada 25 Agustus 2025 turut mendiskusikan ketahanan pangan dengan tema diskusi “Jejak Pangan, Jejak Iklim: Ketahanan Pangan dari Ladang ke Masa Depan”. Diskusi tematik ini dihadiri oleh lima narasumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, dan komunitas masyarakat. Diskusi ini membahas peran pemerintah pusat dan daerah beserta para stakeholders dalam membangun atau mewujudkan kedaulatan pangan Bali dan Indonesia.
Noor Avianto selaku Perencana Ahli Madya dari Kementerian PPN/Bappenas memaparkan urgensi pemerintah pusat dalam membangun kebutuhan pangan yang berkelanjutan dari dampak perubahan iklim. “Ada dilema pemerintah, sisi satunya bagaimana bisa meningkatkan (hasil) produksi, tapi sisi lain kita harus menjaga lingkungan kita, Maka dari itu, pemerintah melakukan aksi konvergensi sistem pangan dan climate action ke dalam dokumen perencanaan negara,” ucap Noor.
Pemerintah Pusat mewujudkan kedaulatan pangan nasional dengan membentuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 terkait Arah Kebijakan terkait Pangan dan Pertanian. Aturan hukum tersebut berisi dua poin utama rencana pemerintah pusat, yaitu transformasi ekonomi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Rencana transformasi ekonomi berisi upaya-upaya pemerintah pusat dalam peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, sedangkan pada rencana ketahanan sosial budaya dan ekologi itu berisi pelaksanaan ekoregion sistem pangan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal.

“Hal-hal tersebut dilakukan demi mencapai salah satu visi-misi Presiden Prabowo-Gibran dalam mewujudkan ketahanan pangan, upaya langkah-langkah ini selanjutnya dikunci dengan peraturan presiden, supaya ada tata cara kerja dan sinkronisasi dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Noor.
Sementara itu, I Wayan Sunada, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Bali menjelaskan tantangan dan langkah strategis sektor pertanian. Tantangan Pemprov Bali ada dua, yaitu persoalan data pemetaan potensi pangan daerah kabupaten/kota dan persoalan kontradiksi Lahan Baku Sawah (LBS).
Menyinggung persoalan data, Pemprov Bali melakukan langkah-langkah pemetaan potensi yang ada di masing-masing daerah dengan cara turun langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan potensi pangan benar-benar valid. “Karena selama ini data yang kita (Dinas Pertanian Provinsi Bali) dapatkan dari kabupaten adalah estimate (estimasi – red), belum pernah kita melakukan secara langsung turun ke lapangan itu loh. contohnya jembrana, disana ada kakao, potensinya sekian hektar, sekian tanaman, benarkah? Nah itu pertanyaan saya,” ucap Sunada. Sunada menjelaskan Pemprov Bali harus turun ke lapangan untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang paling ideal dan melakukan pembenahan-pembenahan pada kebijakan yang telah diambil.
Ada pula persoalan tentang Lahan Baku Sawah (LBS), areal tanah yang siap dijadikan lahan usaha pertanian sawah. Pemprov Bali telah menyelidiki LBS bersama dinas kabupaten/kota se-Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat, terutama yang membidangi subak. Hasilnya menyoroti tingginya alih fungsi lahan sawah yang masih terjadi di Bali saat ini.
“Ternyata sawah dari kita melakukan perbandingan-perbandingan itu ada 68.000 hektare dari sebelumnya 74.000 hektare, betapa tingginya alih fungsi lahan, ternyata banyak hotel-hotel yang tidak memiliki izin. Nah keinginan pemerintah provinsi adalah menertibkan hotel-hotel itu dan merancang Perda untuk menyelamatkan sawah kita,” ucap Sunada.

Terkait sepuluh pangan strategis nasional, Sunada menjelaskan Provinsi Bali hanya satu yang defisit atau kekurangan, yaitu bawang putih tahun 2023. “Beras walaupun tahun 2023 terjadi El-Nino yang sangat panjang di Bali, kita (Pemprov) juga sampai kewalahan dan sempat stres juga apakah Bali akan minus atau tidak karena kehilangan satu putaran musim tanam, itu di bulan Desember 2023 – Januari 2024, kita sudah melakukan panen raya,” ungkap Sunada.
Selama ini pangan yang menyebabkan Bali inflasi adalah cabai rawit. Pemprov Bali mengatasinya dengan memperbanyak tanaman cabai dengan cara membagi-bagikan bibit cabai kepada masyarakat. Bibit cabai itu ditanam di pekarangan rumah, di kebun, di telajakan rumah masyarakat karena Bali tidak memiliki lahan khusus untuk menanam cabai.
Sunada juga mengungkapkan bahwa Bali mengalami surplus beras sebanyak 56.000 ton. “Dari tahun 2024 ke 2025 masih carry over (sisa stok) kita masih 56.000 ton beras. Nah bagaimana dengan tahun 2025? Kita punya target dari (pemerintah) pusat, LTT (Luas Tambah Tanam) ini sangat luar biasa dari luas lahan kita 68.000 hektare sawah, kita bisa realisasikan 155.000-157.000 hektare sawah sampai akhir tahun nanti (2025),” ucapnya. Saat ini Pemprov Bali sudah merealisasikan 94.000 hektare sawah. Seandainya 155.000 hektare ini bisa direalisasikan sampai akhir tahun 2025, Bali akan surplus beras sekitar 200.000 ton.
Pemprov Bali telah mendata luas lahan 68.000 hektare sawah dengan 65% pertanian organik (tanpa pestisida). Targetnya sampai tahun 2027 nanti secara keseluruhan pertanian Bali itu sudah organik semua. “Tak henti disitu, kita juga punya lab terkait dengan keamanan pangan. Ya, keamanan pangan kita uji produk-produk pertanian, kita langsung turun ke lapangan, kita ambil sampelnya,” ujar Sunada.
Said Abdullah selaku Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan memaparkan permasalahan kedaulatan pangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Pertama, menyoal ketidakadilan sistem pangan yang kurang menyejahterakan para petani Indonesia.
Said menyinggung dalam sepuluh tahun terakhir dari tahun 2013-2023 setidaknya 5 juta keluarga petani keluar dari sektor pertanian karena semakin tidak menjanjikan sektor pertanian ini. Sementara, selama 10 tahun terakhir, petani muda di Indonesia tidak pernah bergeser dari angka 11%.
Kedua, persoalan resilience (daya tahan). Bali memiliki kesuburan tanah yang tinggi, tetapi sayangnya praktik moda produksi pangan di Bali justru mengeliminasi dan mendegradasi keragaman pangan itu. “Pola produksi pangan yang dikembangan di wilayah kayak NTT, NTB atau wilayah semi arid (daerah agak kering) lainnya dipaksa untuk mengembangkan komoditas yang cocok di Jawa, misalnya padi dan didorong besar-besaran di sana. Saya lebih memilih mempertahankan resiliensi itu dengan mengembangkan keragaman pangan yang kita punya dr jenis tanaman, budaya, dan sistem yang ada,” ujar Said.

Jika sistem pangan harus sesuai orientasinya dengan kedaulatan pangan, negara harus menggeser model produksinya lebih beragam sesuai dengan konteks agro-ekosistem dan budaya wilayahnya. Misal tahun 1970an, kita masih mengenal empat jenis pangan pokok seperti umbi-umbian, jagung, beras, sorgum, sagu, dan seterusnya. Hari ini kita tinggal mengenal dua jenis pangan saja, yaitu beras dan gandum.
“Agak sulit membayangkan Indonesia itu pangan pokoknya nomor satu adalah gandum, Ketika Ukraina dan Rusia berperang, Presiden Jokowi sampai datang ke Rusia untuk melobi supaya melepaskan ekspor gandum dari Ukraina ke Indonesia, pertaruhan yang besar bagi bangsa kalau kita jatuh memilih sistem pangan kita diletakkan pada pangan pasar global. Menurut saya itu sesuatu yang keliru besar bagi kita,” ujar Said.
I Gusti Agung Ayu Ambarawati dari Center on Food Availability for Sustainable Improvement (CFASI) Universitas Udayana juga ikut memaparkan upaya dan temuannya di lapangan terkait ketahanan pangan. Ayu Ambarawati meninjau program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diterapkan pemerintah tahun 2015 dengan mencari metode-metode dan antisipasi program tersebut, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat petani terkait manfaat asuransi dan mempercepat mitigasi risiko antara pembeli asuransi dan klaimnya.
Tomy Haryadi selaku Direktur Pangan, Lahan, dan Air WRI Indonesia (Mitra Koalisi Sistem Pangan Lestari/KSPL), menjelaskan bahwa ketahanan pangan yang baik itu terwujud jika kita memikirkannya secara holistik dari perencanaan sampai ke implementasi. Ada empat hal yang harus dilakukan semua pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, perencanaan yang paling tepat dengan menggunakan basis riset, informasi, dan teknologi yang tepat dari awal. Kedua, implementasi yang melibatkan banyak pihak, baik itu mitra pembangunan, penerima manfaat, ataupun pendana/pendonor. Ketiga, program/kebijakan tidak akan berjalan kalau tidak ada insentif bagi siapapun yang terlibat baik. Keempat, pengelolaan keseimbangan antara produksi dan konsumsi itu harus dicapai dengan cara mengembalikan pangan lokal sebagai step of food mereka itu yang paling penting karena low cost dan lebih bergizi.