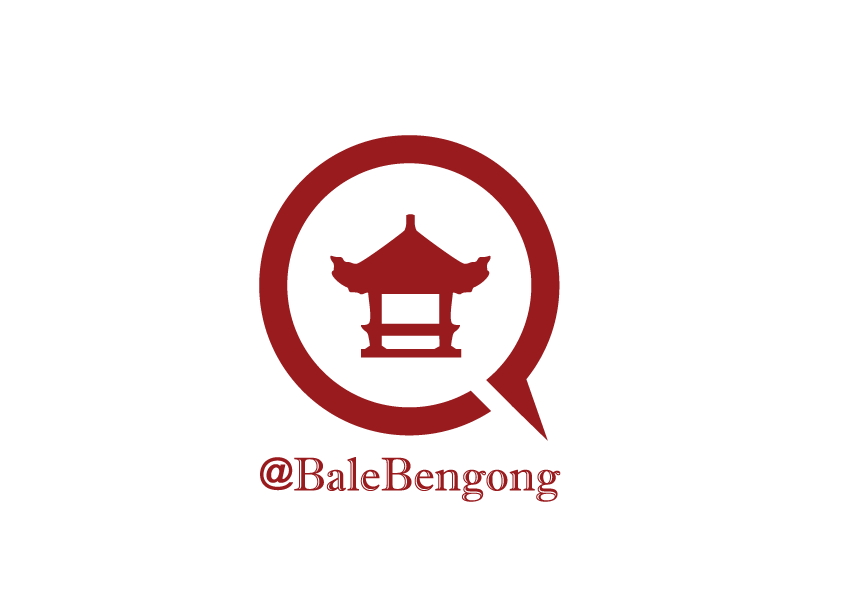Photo bencana banjir 10 September 2025 di Bali oleh Antara
Respon terhadap banjir besar di Bali pada September 2025 langsung menguji seberapa siap pemerintah daerah dalam mengelola dana darurat. Begitu status tanggap darurat ditetapkan, pemerintah provinsi mengumumkan ketersediaan dana sekitar Rp40 miliar dari APBD yang dapat digunakan untuk membantu warga terdampak. BNPB dan BPBD pun segera menurunkan bantuan logistik, sementara janji kompensasi untuk pedagang pasar dan korban rumah rusak disampaikan secara terbuka (JakartaDaily, 2025). Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah. Namun, di balik itu, masyarakat tetap mempertanyakan satu hal penting: apakah dana benar-benar dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan cepat ?
Dalam teori manajemen bencana, dana darurat memang dirancang sebagai instrumen vital pada fase tanggap darurat. Ia berfungsi sebagai sumber daya finansial pertama yang harus bisa digunakan segera untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, air, tenda, obat-obatan, hingga bantuan tunai bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian (Sonata, 2021). Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang jelas melalui UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.22 Tahun 2008, yang mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan Belanja Tak Terduga (BTT) serta pemerintah pusat menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) (Pemerintah RI, 2008). Dengan sistem ini, semestinya tidak ada alasan keterlambatan dalam menyalurkan dana darurat.
Meski demikian, praktik di lapangan sering tidak seideal aturan. Masyarakat kerap khawatir soal proses pencairan yang berbelit, mekanisme distribusi yang tidak jelas, hingga minimnya laporan penggunaan dana. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Studi di Indonesia menemukan bahwa banyak daerah masih bergantung penuh pada BNPB, sementara kapasitas daerah dalam mengelola BTT terbatas (Rivani, 2022). Mengambil contoh di negara tetangga seperti Filipina, kondisi serupa terjadi: meski dana bencana digelontorkan dalam jumlah besar, lebih dari seperempat anggaran justru tidak diserap, menyebabkan keterlambatan bantuan pada saat paling dibutuhkan (Oxfam Philippines, 2021).
Bali menghadapi tantangan serupa. Pemerintah memang sudah menjanjikan kompensasi bagi pedagang dan warga terdampak, tetapi banyak korban masih belum memahami prosedur klaim dan belum tahu apakah mereka masuk daftar penerima atau tidak. Kebingungan seperti ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat. Jika ditambah dengan keputusan pemerintah daerah yang dianggap kontroversial oleh warga, maka dalam situasi tersebut dapat memunculkan isu sosial baru yang memperkeruh suasana. Kondisi ini bisa menghambat fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir. Mengingat dalam konteks bencana, kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat, adil, dan lancar.
Di tengah problem klasik ini, Bali sebenarnya punya potensi tambahan yang bisa dimanfaatkan: Bali Tourist Levy. Sejak 2024, setiap wisatawan asing yang masuk ke Bali dikenakan pungutan sekitar Rp150 ribu, yang selama ini digunakan untuk menjaga lingkungan dan budaya (The Bali Sun, 2024). Mengingat banjir besar September 2025 telah menimbulkan kerugian signifikan, muncul gagasan agar sebagian dana levy ini bisa dialokasikan untuk memperkuat dana darurat bencana. Rasionalisasinya jelas: pariwisata adalah nadi ekonomi Bali, dan ketika bencana mengancam, wisatawan juga berkepentingan agar pulau ini cepat pulih.
Jika mekanisme ini dijalankan dengan baik, kontribusi dari Bali Tourist Levy bisa menjadi cadangan finansial yang sangat signifikan. Dengan jutaan wisatawan setiap tahun, potensi dana mencapai ratusan miliar rupiah. Sebagian dari jumlah ini dapat dialihkan untuk mendukung warga kecil yang paling terdampak bencana, seperti pedagang pasar, nelayan, atau pekerja sektor informal. Hal ini tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang peduli dan tangguh terhadap bencana.
Namun, wacana ini hanya bisa berhasil jika prinsip transparansi ditegakkan. Wisatawan asing yang membayar levy tentu ingin melihat dampak nyata dari kontribusinya. Masyarakat Bali juga berhak tahu ke mana dana itu disalurkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem pelaporan publik yang mudah diakses, misalnya berupa portal daring yang menampilkan jumlah levy yang terkumpul, persentase alokasi untuk lingkungan, budaya, dan dana darurat. Dengan cara ini, semua pihak baik masyarakat lokal maupun wisatawan bisa ikut mengawasi.
Selain memanfaatkan Bali Tourist Levy, pengelolaan dana darurat di Bali juga perlu diperkuat dengan melibatkan masyarakat. Struktur sosial Bali yang khas, lewat banjar dan desa adat, bisa menjadi jaringan distribusi sekaligus mekanisme pengawasan. Jika banjar ikut memverifikasi daftar penerima bantuan, maka risiko salah sasaran akan berkurang. Model partisipasi warga seperti ini pernah terbukti efektif pada bencana lain di Indonesia, misalnya saat gempa Yogyakarta 2006, ketika audit sosial berbasis komunitas membantu memastikan bantuan sampai ke tangan korban yang benar-benar membutuhkan (Soekanto & Mamuji, 2006).
Dari sini kita belajar bahwa pengelolaan dana darurat bukan hanya soal ada atau tidaknya uang, melainkan bagaimana uang itu digunakan. Bali sebenarnya sudah punya tiga sumber utama: BTT dari APBD, DSP dari BNPB, dan tambahan dari Bali Tourist Levy. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan ketiga sumber ini bisa digerakkan dengan cepat, digunakan tepat sasaran, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Referensi
- JakartaDaily. (2025). Indonesia’s Bali Governor Vows Compensation From Regional Budget After Floods Hit 200 Market Traders in Denpasar.
- Oxfam Philippines. (2021). Climate-vulnerable PH fails to fully spend disaster preparedness funds. Rappler/Oxfam.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). PP No.22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- Rivani, E. (2022). Mekanisme, jenis pendanaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah. Kajian.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Sonata, H. (2021). Disaster Management. Yogyakarta: Deepublish.
- The Bali Sun. (2024). Bali Tourist Levy Implementation for Environmental and Cultural Preservation.