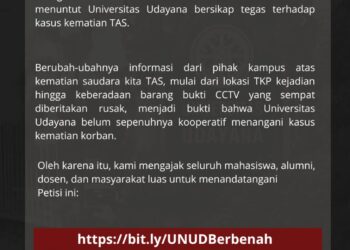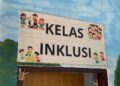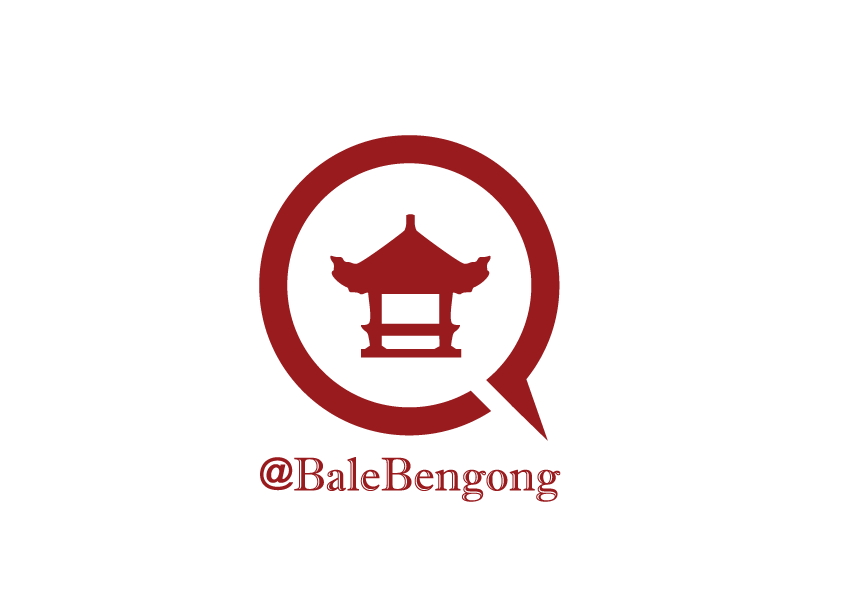Hari-hari berlalu, tetapi bencana banjir yang terjadi pada 10 September 2025 lalu masih meramaikan layar media sosial. Banjir bukan sesuatu yang asing di Bali, terutama di kawasan perkotaan padat seperti Kota Denpasar. Banjir kali ini berbeda karena bukan hanya menyisakan genangan air saja, tetapi menyisakan kerusakan, kerugian, trauma, hingga menelan korban jiwa.
Hujan deras menyapu sebagian besar wilayah Bali selama dua hari. Puncaknya dini hari pada Rabu, 10 September 2025, bertepatan dengan Pagerwesi. Siaran pers, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan intensitas hujan selama 8-9 September mencapai 245.5 mm/hari. Intensitas tersebut masuk kategori ekstrem dan berpotensi menyebabkan bencana besar.
Namun, hujan ekstrem bukan penyebab tunggal bencana di Bali beberapa waktu lalu. Muncul berbagai spekulasi bahwa tata ruang wilayah kota juga menjadi salah satu penyebab bencana.
Dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali, Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menyinggung krisis tutupan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung. DAS Ayung merupakan aliran sungai terbesar di Bali yang berhulu di Kintamani, Bangli dan mengalir melintasi Gianyar, Badung, Denpasar, hingga Selat Badung.
Kawasan DAS Ayung seluas 49.500 hektare. Dari luas tersebut, Hanif Faisol menyebutkan hanya 3 persen atau 1.500 hektare di antaranya yang masih memiliki tutupan hutan. “Secara ekologis, paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%,” ujar Hanif Faisol. Artinya 97% wilayah DAS Ayung sudah beralih fungsi, sehingga tak mampu menjalankan fungsinya sebagai daerah resapan air.
Pengaturan tata ruang kawasan di Bali
Pengaturan pembangunan di kawasan rawan bencana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Pemanfaatan ruang yang bertampalan (overlay) dengan kawasan khusus diatur dalam pasal 102 hingga pasal 114. Kawasan khusus yang dimaksud termasuk kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, dan kawasan sempadan.
Sementara itu, ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tinggi diatur dalam pasal 105 ayat (6). Secara garis besar, ketentuan tersebut mengatur pelarangan alih fungsi ruang di kawasan rawan bencana banjir, kecuali untuk kepentingan mitigasi.
Apabila, ruang di kawasan tersebut dimanfaatkan menjadi pemukiman, akomodasi pariwisata, maupun sebagai kawasan industri, perlu ada pemasangan sistem drainase, pembuatan sumur resapan, dan lubang resapan biopori. Selain itu, kawasan tersebut dilarang untuk fasilitas umum.
Di Denpasar, RTRW Kota Denpasar diatur melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021. Pasal 83 mengatur tentang pemanfaatan ruang di kawasan khusus, termasuk kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, dan kawasan sempadan. Isinya sama dengan RTRW Provinsi Bali.
Pengaturan sempadan sungai disesuaikan dengan kedalaman sungai. Pada sungai bertanggul, lebar sempadan sungai minimal 3 meter. Pada sungai tidak bertanggul, lebar sempadan sungai 10 meter untuk kedalaman sungai 3 meter, 15 meter untuk kedalaman sungai 3-20 meter, dan 30 meter untuk kedalaman sungai di atas 20 meter.
“Secara aturan, bangunan yang ada di sempadan sungai sebenarnya seharusnya itu nggak berlaku sebagai bangunan,” ujar Komang Ardinata dari Kota Masa Depan ketika dihubungi melalui telepon. Artinya, secara aturan, bangunan di sempadan sungai seharusnya tidak boleh ada dan tidak boleh dilegalkan. “Semestinya harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai sempadan untuk perlindungan,” imbuh Ardinata.
RTRW Provinsi Bali juga telah mengatur tentang pemanfaatan ruang di kawasan resapan air. Pemanfaatan ruang di kawasan resapan air dibatasi untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air hujan. Risiko hidrologi, yaitu banjir, akan muncul ketika kawasan resapan air semakin berkurang karena alih fungsi.
Dalam satu poster yang ditempelkan di BaleBio Sanur menunjukkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Denpasar selama 30 tahun terakhir. Kawasan pemukiman semakin berkembang ke kawasan pinggiran yang berpegaruh terhadap berkurangnya lahan terbuka dan egetasi. Dalam waktu 30 tahun, tutupan lahan di Kota Denpasar berkurang hingga 75,17% atau sekitar 5.000 hektar. Jika diibaratkan, 5.000 hektar setara dengan kota Jakarta Pusat.
Priyo Sancoyo, seorang arsitek pasca bencana mengungkapkan ada tiga hal yang memicu kerusakan parah pada banjir di Bali beberapa minggu yang lalu. “Penataan lingkungan, kemudian tata kelola kawasan resapan, terus kemudian kesadaran. Jadi, tiga hal itu menurut saya menjadi penyebab kerusakan banjirnya,” ujar Priyo.
Priyo mengibaratkan air seperti rasa mulas pada manusia yang ditahan. Ketika ditahan, rasa mulas itu akan beralih menjadi hal lain. “Air itu logikanya memang mau berpindah tempat mencari tempat yang lain untuk dia jalan,” ungkap Priyo ketika ditemui. Jika kawasan resapan air malah dibangun dan digantikan menjadi beton, air yang seharusnya meresap malah mengalir ke arah lain.
Berefleksi pada masa lalu dan daerah lain
Priyo bernostalgia mengingat arsitektur zaman dulu di Bali. Nenek moyang masyarakat Bali mewariskan konsep ruang yang beradaptasi pada alam, bukan alam yang beradaptasi pada pembangunan. “Sekarang alam menyesuaikan apa yang kita desain,” ujarnya.
Tata ruang Bali berpusat pada konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Asta Kosala Kosali merupakan konsep arsitektur tradisional Bali yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep ini mengatur tata cara pembangunan, rumah, pura, dan bangunan lainnya berdasarkan keseimbangan kosmologis, orientasi mata angin, dan ukuran tubuh manusia. Contoh sederhana dari Asta Kosala Kosali adalah bangunan bale daja, bale dangin, dan bale dauh yang mempertimbangkan arah mata angin. Sayangnya, konsep ini smai hilang dan disederhanakan, digantikan oleh konsep bangunan yang bergaya modern.
Masyarakat Bali juga memiliki kepercayaan turun-temurun yang bertujuan untuk melindungi alam. Ini disebut sebagai tabu budaya, larangan sosial atau norma adat yang tidak tertulis. Misalnya, bambu dihindari karena dipercaya membawa hal-hal negatif. Padahal, tujuannya adalah mencegah penebangan bambu atau alih fungsi karena bambu berfungsi menyimpan cadangan air. Ada juga aturan tidur dengan kepala mengarah ke letak gunung karena katanya pamali. Padahal, ini digunakan untuk mencegah sinar matahari langsung menyinari kepala ketika bangun tidur.
Berbeda dengan dulu, pembangunan di Bali saat ini, khususnya di Kota Denpasar berorientasi pada ekonomi, bukan sosial masyarakatnya. “Celakanya pembangunan yang kita desain tidak menyesuaikan kondisi alam,” ujar Priyo.
Selain tata ruang, Priyo juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tehadap alam sekitar dan mitigasi bencana. Kerusakan parah pada banjir Bali hingga menelan korba jiwa berlangsung pada dini hari, ketika masyarakat sedang tidur lelap. Priyo membayangkan seandainya rumah warga di bantaran sungai menghadap sungai, mungkin kerugian saat bencana dapat diminimalisir.
Di Yogyakarta, kawasan kumuh sekitar bantaran sungai ditata kembali dengan 3M, yaitu mundur, munggah, dan madep kali. Hal ini disampaikan Umi Akhsanti, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam sesi tematik Pekan Iklim Bali 2025. “Jadi, rumah itu mundur dari sungai 3 meter. Kemudian, kalau awalnya menghadap ke jalan, ini harus menghadap ke sungai supaya jalannya ada di tepi sungai, sehingga nanti kawasannya akan menjadi lebih bersih,” ujar Umi.
Umi menjelaskan bahwa pemerintah melakukan pendekatan ke masyarakat dengan menawarkan penataan kawasan di daerah bantaran sungai. Masyarakat yang sebelumnnya tinggal di bangunan yang mepet dengan sungai direlokasi ke bangunan baru yang mengedepankan 3M.
Yogyakarta juga dikenal dengan Kampung Kali Code yang ditata oleh seorang arsitek, Romo Mangun. Dalam penataan tersebut, Romo Mangun mencoba menata pemukiman di bantaran sungai dengan tidak memindahkan masyarakat yang tinggal selama bertahun-tahun di sana. Penataan dilakukan dengan pendekatan arsitektural yang juga melibatkan masyarakat sekitar. “Pelibatan multipihak dalam penataan kawasan juga sangat penting. Nah, perannya pemerintah adalah memastikan mendengar,” ujar Priyo.
Pernyataan Priyo selaras dengan Ardinata. Menurutnya, bangunan di bantaran sungai tidak bisa sekadar dibongkar. Harus ada komunikasi dan edukasi untuk orang-orang yang ada di sempadan dungai. “Pendekatan ya utamanya. Pendekatan yang partisipatif. Aku yakin permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa ada konflik antara pemerintah sama masyarakat,” ujar Ardinata.
Bencana besar yang melanda Bali menjadi wake up call atau alarm bahwa Bali sedang tida baik-baik aja. Ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat agar bencana yang sama tidak terulang lagi.