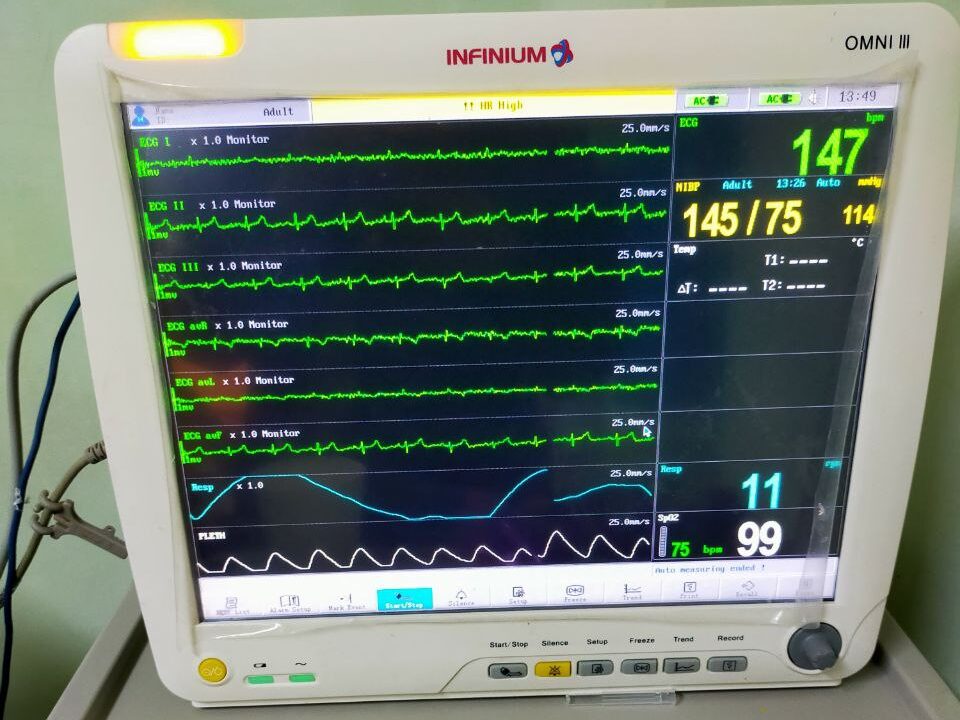
Hampir satu tahun berlalu semenjak ibu memperoleh serangan penyumbatan darah di otak atau yang kita kenali sebagai stroke. Hari itu minggu, sekitar jam 9 pagi, entah kekuatan apa yang mendorong, aneh tapi nyata, telepon genggamku jatuh sendiri dari genggaman yang sebenarnya cukup erat. Ponsel khusus untuk pasien-pasien tersebut retak dan padam.
Tak lama berselang, ponsel pribadi khusus untuk keluarga dan orang terdekat berbunyi. “Kak, sepertinya mama agak cadel. Sejak tadi malam mengeluh kepala terasa berat.” Perasaanku ngeri, tangan bergetar, segera aku menghubungi teman dokter yang tinggal dekat dengan ayah dan ibu. Hari yang diisi dengan segala ketidakberdayaan, tubuh di Bali dan sedang bertugas yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, pikiran bersama Ibu.
Sepanjang hari aku lewati dengan mengobati pasien-pasienku di RS dan menangis dalam hati karena tidak bisa bersama ibu dan ayah. Aku cukup beruntung, memiliki adik lelaki dan perempuan yang bisa fokus pada ayah dan ibu. Kami saling menopang. Aku dan adik nomor tiga bertugas memenuhi pembayaran, sedangkan adik nomor dua dan adik lelaki bertugas menjaga dan merawat. Ayah selalu menangis, saat bangun pagi, ia kerap menelepon dan menangis. “Ayah sedih, biasa bangun dan di samping ada Ibu. Sekarang ayah sendiri.” Aku mencoba menguatkan, ayah terus menangis.
Setelah hampir satu tahun, saat ibu sudah kembali berlatih berjalan dan berbicara. Aku mulai mampu mencerna segala yang terasa sungguh mengagetkan dan cepat tersebut. Pada suatu malam, sekitar satu bulan lalu. Sahabatku bertanya, “bagaimana aku memandang seorang ibu yang merantau demi keluarga dan meninggalkan anak bersama suami?” Sesaat setelah ia melontarkan pertanyaan tersebut, aku berdiam diri. Suasana agak hening, sesekali suara mobil berdesing di jalan raya. Dalam diam kami sepakat, itu bukan pertanyaan yang mudah.
Sahabatku ini adalah orang yang selalu menguatkan dan menghiburku saat aku menangis sepanjang malam ketika ibu dirawat inap. Ia bahkan mencari pendeta yang konon kabarnya memiliki doa ampuh untuk penyembuhan. Ia memanggil pendeta, dan menelepon ibu lewat video lalu mengajak Ibu berdoa. Meski saat itu, ia tengah bertugas di timur Indonesia. Ada orang-orang yang terus hadir dalam hidup kita, saat kita berada dalam berbagai pergolakan, dan sahabatku ini adalah salah satunya. Kata orang bijak, “segala kesulitan menunjukkan kita siapa yang mengasihi kita tanpa pamrih.”
Aku berdeham dan memutar cerita ke sana dan ke sini sampai akhirnya aku mencoba memberi pandanganku. “Beberapa hari yang lalu, aku menelepon video ayah dan ibu. Mereka duduk bersantai di teras rumah. Ayah mengadu tentang ibu yang malas berlatih menulis. Aku mencoba mengolok ibu sambil melucu. Ayah dan ibu tertawa sambil saling menggoda. Ayah mencubit pipi ibu.”
Sahabatku menjawab, “manis yah.”
“Mungkin ini terdengar egois dan kontra, tapi dari berbagai aspek, ada satu sisi di mana aku merasa bahagia ibu sakit. Aneh ya,” ucapku.
“Kok bisa?” ia bertanya dengan mimik wajah serius sembari menopang wajahnya dengan tangan yang ditaruh di atas meja makan.
“Ayah dan ibu sudah menikah lebih dari 30 tahun. Sepanjang mereka bersama, ibu selalu mengurus dan mengutamakan ayah dan kami. Ibu tidak pernah sakit. Ibu banyak menahan rasa, banyak menyimpan rasa takut, jika hidup suami dan anaknya akan menderita. Ibu juga terus belajar menjadi ibu, kadang benar, sering kali salah. Satu yang terus ia lakukan, menelan segala keinginannya sendirian. Sejak ia sakit, ayah mencintainya dengan cara baru. Ibu selalu dihujani cinta dan kasih setiap hari. Ayah membuka gorden untuknya, menyeduh teh tanpa gula, merebus ubi ungu sebagai kudapan sore untuknya. Ayah menemaninya belajar menulis. Dan bukan hanya itu, kami, anak-anaknya, bergantian menghubunginya, mengirimnya hadiah dan mengucapkan cinta. Ini agak aneh, Tapi kesakitan ibu membebaskannya, menjadikannya dirinya yang mungkin ia doakan sepanjang hidup pernikahannya. Ibu lebih banyak tertawa sekarang. Kami pun sembuh,” ucapku sambil menyeka air mata.
Sahabatku memandang jalanan, sambil mengunyah daging panggang. Sementara lagu-lagu berbahasa Korea di rumah makan tersebut bersenandung di langit-langit atap. Sesekali ia berdeham. “Memang segala sesuatu butuh waktu untuk dicerna,” ujarnya.
Kami berdua adalah dokter spesialis, keseharian kami penuh dengan jadwal yang mengharuskan kami di luar rumah. Kadang ada hari di mana ingin rasanya tinggal bersama orang yang kita kasihi saja. Namun, jalan hidup ini menuntut bahwa apa pun yang kami rasakan di dalam. Kami harus memberikan yang terbaik dari diri kami kepada pasien. Apakah mudah? Tentu sering kali jauh dari mudah.
“Lantas bagimu apakah aku perempuan yang tega jika aku merantau?” Ia bertanya kembali.
Aku tersenyum dan menarik nafas ku sekali. “Aku belum pernah menjadi ibu. Dan mungkin apa yang akan aku katakan sulit dimengerti. Namun, Milan Kundera pernah berkata, kita hanya memiliki hidup yang kali ini, yang ini saja. Maka, sangat mungkin kita salah dan akan selalu ada kesalahan karena toh kita hanya punya hidup yang ini saja. Sis, aku percaya padamu. Aku percaya apa pun yang kau lakukan semua karena kau mencintai keluargamu. Aku paham ini sulit, akan ada banyak hari di mana kau merenungkan ini dan mempertanyakannya. Namun, waktu akan menunjukkan apakah ini salah atau benar. Mungkin segala sesuatu adalah proses belajar. Belajar menjadi perempuan, belajar menjadi ibu, dan belajar terus menjadi manusia. Kau pasti sudah menimbang keberlangsungan kalian sehingga memilih jalan ini. Hanya kau yang tahu persis sakit dan senangnya. Tapi, aku bangga, aku bangga karena kau realistis dan berani. Apakah ini kesalahan atau kebaikan? biarlah masa depan yang akan menjawab. Sekalipun ini salah, ini akan jadi ruang bertumbuh bagimu, mungkin bagi pernikahanmu dan kau sebagai Ibu.”
Sama seperti hubungan Ayah dan Ibu, pernikahan mereka setara persis saat Ayah tahu bahwa hari-harinya adalah nihil tanpa ibu. Ia kerap menyesali kenapa dahulu tidak membantu ibu memasak telur dadar. Ia juga sering bilang bahwa kelak jika ibu sudah lancar berjalan, ayah akan lebih banyak membawa ibu pergi.
Sebagai seorang yang bekerja di Rumah Sakit dan melihat banyaknya kepergian dan kehilangan, memiliki kesempatan dicintai hingga menua bersama adalah pemandangan yang menguatkan. Pernah aku melihat sepasang kakek nenek dirawat bersama di ruang intensif, anak-anak mereka bahkan tidak hadir. Untung saja si kakek pensiunan BUMN. Si kakek akhirnya berpulang, cara nenek menatap tubuh mendiang suaminya adalah sebuah tatapan kehilangan yang mengerikan. Tatapan yang tak lagi mengandung air mata, namun kekosongan yang merongrong.
Pernah aku memiliki pasien yang begitu muda dan gemilang. Di masa mudanya, ia memperoleh kanker yang mematikan. Ia dipaksa pulang dari rantau perkuliahannya. Setiap minggu Ia melakukan kemoterapi. Tubuhnya hanya tulang dibalut kulit. Rongga mulutnya memerah kering. Lunglai di atas kasur dan mengerang kesakitan. Ayah dan ibunya terus mengiris buah naga dan alpukat, melunakkannya di atas sendok dan menaruh penuh kelembutan ke bibir putranya. Pada satu pagi, setelah meminum susu perlahan dan sering, putra mereka mampu menggenggam ponsel dan tersenyum. Saat aku memasuki ruangannya, si ibu berkata.
”Terima kasih dokter, putra saya suka susunya. Pagi ini dia bisa membuka ponsel dengan tangannya sendiri dan memanggil teman-teman kuliahnya.”
Setiap kata terima kasih keluar dari pasien-pasien, hidup menjadi signifikan. Bahkan saat menulis tentang bagaimana sakit dan kebimbangan kadang ada proses pelepasan dan perasaan semacam aneh. Tidak mengapa kita sakit, tidak mengapa kita bimbang dan salah, karena kita adalah manusia yang fana. Dan karena kita fana, kita akan pergi pun ditinggalkan. Sulit bagi kita mencerna ini, sulit bagi kita menjadi sempurna. Terutama pada perempuan, menjadi ibu, istri, bekerja dan menjadi diri sendiri, terlalu banyak yang harus kita topang dalam satu tubuh yang sangat mungkin menjadi ringkih. Dan untuk itu mari kita terus belajar, kadang kita salah pun bisa saja kita kali ini benar.
Saat teman bimbang atau saat aku melihat kehilangan, aku teringat pada surat Nick Cave saat ia kehilangan putranya: “It seems to me, that if we love, we grieve. That’s the pact. Grief and love forever intertwined. Grief is the terrible reminder of the depths of our love and, like love, grief is non-negotiable. There is a vastness to grief that overwhelms our minuscule selves. We are tiny, trembling clusters of atoms subsumed within grief’s awesome presence. It occupies the core of our being and extends.”
Saat aku menulis ini, aku tengah dalam perjalanan udara. Di antara yang sedang jatuh cinta di sisi kananku. Dan sepasang suami istri yang tengah bercakap di sisi kiri. Setelah sekian bulan, segala tangisan dan takut kehilangan, melankolis mengingat masa kecil bersama ibu. Belakangan aku melihat sisi lain dari kesakitan dan kebimbangan, bahwa kita hanya harus terus bertanya kepada pemilik hidup ini, setiap hari terus bertanya bagaimana kita mencoba menjalani hidup dengan bermakna dan di dalamnya pasti ada ruang error dan mari coba lagi.














