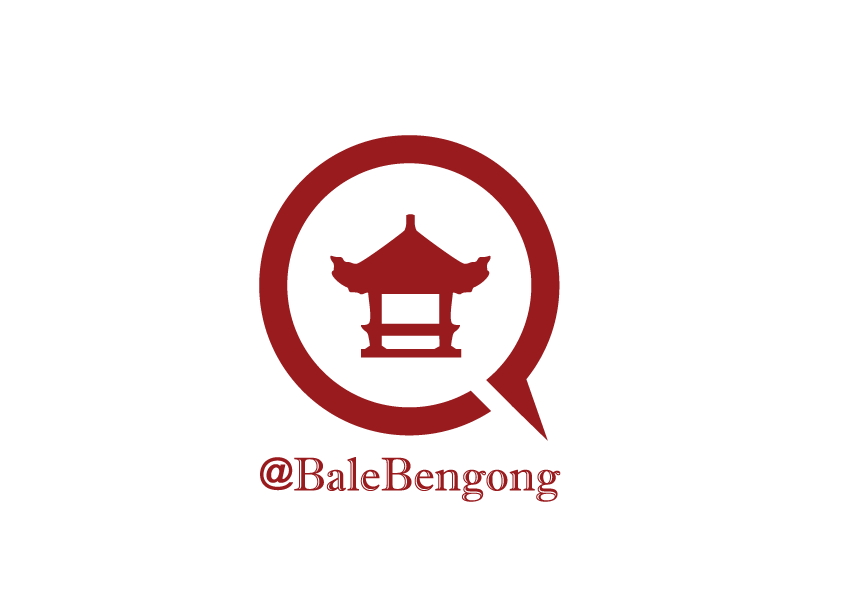Hingga hari ini, saat cuaca tidak menentu, beberapa warga Denpasar yang saya temui seringkali merasa was-was jika hujan turun. Mereka waspada dan tidak merasa tenang dengan lingkungan mereka sendiri, tempat yang seharusnya membuat mereka nyaman. Kawasan pinggiran sungai dan rumah-rumah yang sebelumnya terkena bencana banjir pada 10 September 2025 hanya dibersihkan. Sungai-sungai yang meluap hanya ditata agar tampak kembali elok dan bersih. Di beberapa tempat tampak sungai sudah dikeruk dan diperlebar, tapi masih banyak yang hanya dipoles semata dan masih beresiko untuk meluap jika banjir melanda.
Banjir besar oleh para tetua Bali yang saya ingin sering disebut dengan blabar. Blabar pada September 2025 lalu bisa jadi menjadi salah satu yang terbesar di Bali. Pasca banjir besar tersebut, beberapa respon publik pun mengemuka. Salah satunya adalah baru kali ini banjir besar melanda Bali. Bali sudah seperti Jakarta. Tapi semuanya kemudian bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama dari banjir besar tersebut? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan kita (mungkin saja) luput (terlewatkan) memperhatikannya? Mengapa hal tersebut menjadi berlarut-larut sampai kemudian kita tersentak dan baru tersadarkan tanah Bali sudah terendam banjir dahsyat.
Satu yang pasti, bencana banjir tidak hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi seperti tanggapan pejabat publik yang dangkal sekaligus mangkir dengan situasi struktural yang terjadi. Apa kondisi penyebab struktural tersebut? Ada faktor manusia dan kebijakan yang dibuatnya menyebabkan situasi Bali semakin memburuk sehingga (bencana) banjir hanya tinggal menunggu waktu saja.
Salah satunya yang sempat menjadi perdebatan publik di Bali adalah penanganan sampah. Timbulan sampah meningkat dari 800.000 ton di tahun 2019 menjadi lebih dari 1,2 juta ton di tahun 2024, sedangkan 52% tidak tertangani. Sekitar 33.000 ton sampah diperkirakan masuk ke perairan Bali setiap tahunnya. Belum lagi mayoritas sampah hanya berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan pola open dumping, tanpa pengolahan.
Tidak hanya soal sampah yang pada saat banjir banyak ditemui menyumbat drainase di sepanjang jalan selama banjir. Hal lainnya yang sama parahnya adalah hilangnya kawasan hutan, salah satunya hutan di kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ayung yang hanya tersisa ±1.500 hektare (3%). Data pada tahun 2019-2024 menunjukkan laju perubahan lahan di Bali mencapai kehilangan sebesar 6.522 hektar sawah atau rata-rata 1.087 hektar per tahun.
Lonjakan pembangunan pasca pandemi, terutama dari sektor digital nomad dan investasi properti asing, mendorong perubahan pesat di Bali. Data mencatat, investasi asing naik hingga 92% di Badung dan 81% di Denpasar. Namun, laju alih fungsi lahan ini bukan fenomena baru. Citra satelit periode 2010–2015 menunjukkan kawasan Sarbagita mengalami peningkatan area terbangun hingga 501%, menandakan tekanan pembangunan yang telah berlangsung sejak lama.

Masalah semakin parah karena jumlah RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang kian berkurang seiring berjalannya waktu. Menurut Undang-undang, setiap kota wajib memiliki RTH minimal 30%. Namun, Denpasar hanya memiliki RTH publik sekitar 405 hektar, atau hanya 3,2%. Hal ini juga menyulitkan dalam mengoperasikan dan merawat sistem drainase karena minimnya RTH dan alat pengendali limpasan seperti sumur resapan, sehingga menyebabkan sistem drainase mengalami penumpukan dan pendangkalan saat hujan deras. Belum lagi, banyak tepi sungai yang seharusnya berupa area terbuka dengan lebar 10 hingga 30 meter, kini telah digunakan untuk pembangunan.1
Sudah menjadi perbincangan umum bahwa berlebihan dan tidak terkendalinya pembangunan sektor pariwisata secara massif mengorbankan tata ruang dan air di Bali. Akibatnya adalah resapan air, ruang terbuka hijau, dan area persawahan berubah bentuk jadi bangunan keras. Pengendalian tata ruang mungkin salah satu yang menjadi kunci. Tapi kebijakan tersebut lebih sebagai pemanis daripada dilaksanakan dengan ketegasan di lapangan. Catatan Walhi Bali menyebutkan bahwa penerapan tata ruang Bali amat buruk. Berbagai rencana pembangunan acapkali melabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tentu saja yang marak adalah pembangunan akomodasi pariwisata yang mengalihfungsikan lahan sawah dan perkebunan menjadi bangunan.2
Sebagian besar pembangunan, baik itu perumahan dan akomodasi pariwisata sebenarnya terjadi di lahan persawahan, hutan, dan di sepanjang bantaran sungai. Beberapa wilayah seperti tepian Sungai Ayung sudah menjadi lokasi utama untuk vila dan investasi perumahan mewah. Hutan di Ubud dan sekitar Payangan juga sudah berubah secara signifikan. Wilayah pesisir seperti Uluwatu, Canggu, dan Seminyak menjadi contoh gamblang fasilitas wisata yang dibangun secara massif dan berlebihan. Tidak ada kontrol dan penegakan perencanaan tata ruang yang signifikan. 3
Kelompok (serakah) 1%
Beberapa kajian tentang bencana, khususnya banjir, berargumen bahwa bencana ini bukan hanya akibat dari fenomena alamiah namun terkait juga dengan tindakan dan ulah manusia. Inilah yang sering disebut dengan istilah antropogenik (anthropogenic) yang bisa dimaknai secara ringkas sebagai aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara terus-menerus yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu atau mempercepat terjadinya bencana. Aktivitas anthropogenic yang berkontribusi terhadap banjir antara lain perubahan bentang daratan atau alih guna lahan seperti urbanisasi, deforestasi, dan kegiatan pertanian-perkebunan skala besar.
Urbanisasi yang tidak terkontrol membuat betonisasi bangunan pemukiman di perkotaan terjadi secara berlebihan. Betonisasi di sepanjang daerah aliran sungai mereduksi luasan tanah untuk penyerapan air hingga beban sungai untuk membawa air ke laut menjadi bertambah. Eksplolitasi lahan berlebihan untuk industri pertanian atau perkebunan mengurangi kesuburan tanah hingga air tidak bisa terserap dengan baik. Selain itu, deforestasi di hulu sungai membuat kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang drastis. Dengan demikian, alih-alih suatu takdir, bencana juga berhubungan dengan perilaku manusia yang tidak benar dalam mengatur barang/kepentingan bersama (common goods).4
Konteks yang lebih luas dari pengaruh besar aktvitas manusia dalam mengatur bumi dan ekologinya ini sering disebut dengan istilah antroposen (anthropocene). Peran manusia yang kelewat sentral dan tanpa batas pada kenyataannya lebih bersifat menghancurkan ketimbang menghasilkan manfaat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhannya dan perkembangan-perkembangan hidupnya, manusia antroposen ini kemudian mengeksploitasi lebih dari 30-50 persen permukaan tanah, menghancurkan hutan hujan tropis, mengalihkan aliran sungai dan membangun bendungan-bendungan raksasa, dan mengkonsumsi lebih dari setengah keseluruhan air tawar yang bisa diakses.5
Adalah Vandana Shiva (2025) dengan tegas menolak istilah antroposen ini karena tidak semua manusia adalah predator. Manusia sebagai spesies tidak menyebabkan bencana iklim atau krisis kepunahan, melainkan praktik eksploitatif yang tidak terkendali dari kelompok 1% lah yang menyebabkannya. Krisis-krisis itu bukan dampak antropogenik dari tindakan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia, melainkan dampak kapitalogenik akibat ulah sembrono kelompok 1%. Shiva tidak menggunakan istilah antroposen karena baginya kita perlu melampaui antroposentrisme jika ingin membangun masa depan dengan semua kehidupan di bumi karena bumi tersebut untuk semua mahluk, bukan hanya manusia semata.
Darurat kepunahan, malapetaka dan kekacauan iklim serta krisis pangan, adalah gejala dan akibat dari kekerasan dan perang terhadap bumi dan warganya yang dipicu oleh keserakahan kelompok 1%. Kelompok inilah yang mengeruk, menutup, dan mencemari lingkungan hidup, menghancurkan kondisi kehidupan di bumi dengan merampas sumber daya yang menopang penghidupan masyarakat. Memahami bumi yang ‘mati’ sebagai ‘fosil’ dan dipadukan dengan perekonomian yang ekstraktif telah menciptakan keadaan darurat multidimensi yang mengancam masa depan kita.
Inilah yang disebut “perekonomian keserakahan” yang digerakkan oleh kelompok 1 % dengan berbagai jaringannya dari mulai aparat pemerintah, investasi, dan para broker dari kalangan masyarakat sendiri yang memanfaatkan keuntungan remah-remah dari kelompok eksploitatif yang lebih besar tersebut. Eksplotasi kelompok 1% ini berlangsung massif dan masyarakat dibujuk untuk melakukan penyangkalan bahwa keserakahan mereka berdampak besar yaitu krisis ekologi serius yang mengancam kehidupan beragam spesies dan anggota masyarakat yang rentan.
Keserakahan inilah yang sering disebut kolonialisme pembangunan yang lebih mengutamakan laba ketimbang alam dan manusia. Salah satu pandangan yang mendukungnya adalah dengan melakukan reduksi (penyederhanaan) krisis ekologis yang sebenarnya sangat kompleks dan saling berkaitan menjadi krisis yang berbeda-beda dan tidak bersambungan dengan satu dimensi gejala. Perspektif inilah yang kemudian mendasari solusi-solusi palsu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan kendali yang lebih besar atas bumi, sumber dayanya, dan kehidupan kita. Inilah yang sering disebut dengan kolonialisme hijau baru.
Promosi-promosi ramah lingkungan dan solusi parsial yang tidak menyentuh permasalahan mendasar terus digencarkan, padahal akar permasalahannya adalah yaitu hasrat eksploitatif dari kelompok 1 % ini. Inilah sebab-musabab utama dari kehancuran ekologi bumi yang didorong oleh model perekonomian ekstraktif dengan mendasarkan keyakinan bahwa “pembangunan sebagai pertumbuhan”. Situasi inilah yang sering disebutkan dengan globalisasi korporasi (Shiva, 2025: 1-2).
Gugatan Warga
Keyakinan “pembangunan (pariwisata) sebagai pertumbuhan” inilah yang menjebak Bali dalam solusi-solusi palsu mengatasi permasalahan alam yang semakin hari terasa semakin dekat untuk menghancurkan Bali (sedikit demi sedikit). Lalu, dimana peranan warga Bali yang berdaya dan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan jejaring kelompok 1% dari rezim pertumbuhan itu?
Pertanyaan lebih mendasarnya, apakah warga (citizenship) Bali hanya bisa diam dan nrimo (menerima) bencana tersebut. “Nah kudiang men” (mau bagaimana lagi) sering terdengar menjadi ungkapan warga yang pasrah dengan situasi yang sudah terjadi. Atau ungkapan apolitis “Taluh goreng ada hasil” (telur digoreng ada mendatangkan hasil) yang menyerang warga Bali untuk mencoba mengkritisi tingkah polah para pejabat publik dan politisi Bali yang mendadak bungkam merespon bencana banjir. Menurut mereka, yang apolitis ini, lebih baik diam dan menyerahkan nasib hidup kepada para elit dan pejabat publik. Tidak perlu ngendah (neko-neko atau berprilaku berlebihan) untuk bersuara menyapaikan aspirasi dan hanya fokus dengan kehidupan kita masing-masing dengan bekerja. Analoginya, daripada sibuk-sibuk mengkritisi dan bersuara menyampaikan aspirasi kita, lebih baik telur digoreng ada hasil untuk dimakan melanjutkan hidup.
Menjadi warga Bali sejatinya tidak hanya sekadar menjadi obyek politik untuk dijadikan alat dalam perebutan kekuasaan. Atau yang hanya bisa “dibeli” melalui politik uang pada saat kontestasi kekuasaan. Atau yang mudah dimobilisasi karena patron-client balas budi diurus pengeluaran Bansos (Bantuan Sosial). Atau hanya deretan daftar nama statistik yang menjadi sasaran “Serangan Fajar”, yang bisa dengan mudah nama itu “diuangkan” dengan ratusan ribu.
Warga dalam konstelasi politik dibuat (direncanakan) untuk tidak memiliki kedaulatan. Dibuat tidak bersuara dan memiliki aspirasi. Para elit dan pejabat publik yang justru menganggap dirinya paling tahu kebutuhan warga dan menjadikannya sebagai obyek pasif. Relasi warga dengan institusi negara inilah yang rentan dengan politisasi dan de-politisasi.
Citra warga Bali yang polos, nrimo penurut, mudah diatur, koh ngomong (malas berbicara) dan rekaan citra kekuasaan mungkin salah satu contoh reduksi emansipasi politik warga Bali untuk bersuara, menyampaikan aspirasi, mengkritik, bahkan melakukan aksi protes terhadap buruknya kinerja elit politik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Tidak terkecuali pada saat warga Bali ramai-ramai mengkritisi buruknya kapasitas pemerintah dalam penanganan musibah banjir.
Sebagai bentuk emansipasi warga Bali tersebut, Koalisi Pergerakan Untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali (PULIHKAN BALI) melakukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) dengan tuntutan: pertama, melakukan moratorium perizinan berusaha untuk investasi dan/atau proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan keselamatan ekosistem di wilayah Provinsi Bali; kedua, pada masa moratorium, pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) yang sesuai dengan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan audit pembangunan dan pedoman untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) yang memiliki daya tahan atas perubahan iklim (climate resilience); ketiga, melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan dan praktik yang berkontribusi pada terjadinya bencana terkait iklim, untuk mewujudkan pengelolaan tata ruang yang adil, pengembangan infrastruktur perkotaan yang ramah iklim dan responsif terhadap bencana, pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, partisipatif dan inklusif di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) Provinsi Bali; dan keempat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Keadilan Iklim yang mengatur sekurang-kurangnya perihal mitigasi, adaptasi dan kompensasi dari kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh krisis iklim.
Gugatan warga negara ini sangat penting untuk menandingi pandangan yang ingin dibangun bahwa banjir yang terjadi di Bali bukanlah karena salah urus kebijakan, tapi karena alam atau curah hujan yang tinggi. Genangan air yang merendam rumah warga-warga Bali hingga menyebabkan korban jiwa bukan semata karena intensitas curah hujan ekstrem, melainkan akibat kolusi dan kebijakan politik yang lebih berpihak pada pengembang, pengusaha, dan jejaring oligarki moda ekonomi pariwista. Sebagai kelompok 1% yang dinyatakan oleh Shiva, mereka inilah yang menghancurkan kondisi lingkungan Bali dengan janji pertumbuhan pariwisata. Pada titik yang lain mereka lupa bahwa alam dan bumi justru adalah pondasi yang menopang penghidupan masyarakat.
Permana (2025) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa warga yang sengsara karena rumahnya kebanjiran dan warga yang menyampaikan aspirasinya menghadapi musuh yang sama, yaitu elite politik yang mengabaikan kepentingan rakyat. Rakyat pantas mengawasi perilaku elite yang digaji dari pajak rakyat. Untuk itu, rakyat pantas marah bahkan melakukan demonstrasi di jalan menuntut pemerintahnya. Singkatnya, banjir adalah implikasi dari tata kelola dan akuntabilitas politik yang buruk. 6
Pemerintah Provinsi Bali semestinya mampu menjamin hak dan kebutuhan dasar warga yang paling rentan karena ada keseriusan dan rancangan kebijakan yang berpihak kepada kelompok ini. Hal ini bisa dilakukan jika pemerintah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengantisipasi dampak buruk dari perubahan iklim dan memperketat eksploitasi berlebihan terhadap ruang-ruang hijau dan penghidupan warga untuk kepentingan moda ekonomi pariwisata, yang sudah terlanjur menjadi panglima.
Demokrasi menjamin keadilan sosial dan pengambilan keputusan yang inklusif dalam persoalan publik misal dalam penentuan zonasi tata ruang dan peruntukan. Peruntukan tata ruang adalah faktor krusial dalam mengendalikan degradasi lingkungan, seperti, kepastian dan jaminan pemerintah mempertahankan zona hijau untuk konservasi di Bali dari keserakahan perizinan industri pariwisata.7
Sayangnya hal itu tidak terjadi. Pembangunan akomodasi pariwisata semakin massif dan bencana banjir menjadi seperti bayang-bayang yang terus menghantui warga yang rentan. Penanganan masalah sampah belum juga terlihat titik terang. Pada beberapa kesempatan, terlihat pemerintah melakukan penghentian beberapa proyek pariwisata yang sudah terlanjur terbangun. Tapi, seperti layaknya tingkah-polah para elit, sejatinya semuanya tidak menyentuh permasalahan mendasar yaitu keserakahan kebijakan yang dibuat oleh para elit eksekutif dan legislatif yang ingin mempariwisatakan ruang-ruang tersisa di Bali. Dan lagi, sayangnya warga Bali lebih banyak diam dan nrimo tanahya dihabisi perlahan-lahan. Tanpa kritik, perlawanan, dan gerakan sosial yang solid.
DAFTAR PUSTAKA
Permana, Y. S. (2025). The collusion trap: Business-political collusion and flood risk management in Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 122, May 2025, 105408. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2025.105408.
Shiva, V. (2025). Kodrat alam: gangguan metabolik perubahan iklim. Jakarta: Marjin Kiri.
1 Lihat siaran pers Koalisi Pergerakan Untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali (PULIHKAN BALI) yang mengajukan gugatan warga negara yang berdasar pada perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) melalui mekanisme gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) pada 12 November 2025. Lihat juuga: https://balebengong.id/koalisi-pulihkan-bali-ajukan-gugatan-warga-pada-pemerintah-pusat-dan-daerah-bali/ (diakses 17 November 2025).
2 Lihat: https://mongabay.co.id/2025/09/14/mengurai-penyebab-banjir-bandang-bali/ (diakses 16 November 2025).
3 Lihat: https://www.abc.net.au/indonesian/2025-09-19/apakah-pariwisata-berlebihan-jadi-penyebab-banjir-di-bali/105794976 (diakses 13 November 2025).
4 Lihat: Lihat: https://mongabay.co.id/2020/06/25/banjir-antropogenik-dan-demokrasi/ (diakses 10 September 2025).
5 Lihat: https://indoprogress.com/2022/01/asal-usul-antroposen-dan-efeknya-terhadap-hubungan-manusia-dan-alam/ (diakses 11 Oktober 2025).
6 Lihat: https://theconversation.com/mengapa-rakyat-pantas-marah-melihat-protes-sosial-dari-kacamata-persoalan-banjir-di-indonesia-264748
7 Lihat: https://mongabay.co.id/2020/06/25/banjir-antropogenik-dan-demokrasi/ (diakses 10 September 2025).
situs toto situs toto














![[Matan Ai] Bali dan Pembusukan Pembangunan](https://balebengong.id/wp-content/uploads/2025/01/KOLOM-MATAN-AI-oleh-I-Ngurah-Suryawan-by-Gus-Dark1-120x86.jpg)