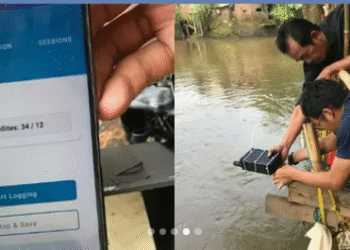Musim hujan kali ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Denpasar, Badung, dan Gianyar baru saja mengalami banjir terparah dalam satu dekade terakhir. Curah hujan tinggi dalam kurun waktu hampir 2 hari mengubah jalan-jalan utama menjadi sungai, rumah-rumah terendam, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Ini bukan lagi sekadar fenomena alam atau “nasib kota tropis.” Ini adalah tanda bahwa cara kita menata kota, mengelola ruang, dan merancang infrastruktur belum siap menghadapi tantangan zaman.
Banjir dan Tata Ruang: Memahami Akar Masalah
Banyak orang menyalahkan hujan deras ketika banjir datang. Padahal, masalah utamanya bukan hanya volume hujan, melainkan bagaimana kita mengelola lahan. Dalam teori hidrologi perkotaan, ada sebuah formula sederhana yang dikenal dengan metode rasional: Q=C×i×A, di mana (Q) adalah aliran puncak, (C) adalah koefisien limpasan, (i) adalah intensitas hujan, dan (A) adalah luas daerah tangkapan air. Rumus ini mengajarkan kita bahwa setiap kenaikan nilai (C)—yang terjadi ketika sawah atau ruang terbuka diubah menjadi permukaan kedap air—akan menaikkan aliran puncak secara langsung.
Sebelum lahan di kawasan hulu banyak dikonversi, koefisien limpasan mungkin hanya sekitar 0,3–0,4, yang berarti sebagian besar air hujan masih sempat meresap ke tanah. Namun, dengan bertambahnya permukaan kedap air akibat pembangunan perumahan, vila, jalan aspal, dan area komersial, nilai ini bisa melonjak menjadi 0,6–0,7. Konsekuensinya, volume air yang mengalir ke drainase kota meningkat dua kali lipat atau lebih, dengan waktu yang lebih singkat. Saluran drainase yang didesain beberapa dekade lalu tentu tidak lagi mampu menampung debit yang melonjak ini.
Ironisnya, Bali justru memiliki sistem pengelolaan air tradisional yang diakui UNESCO. Subak bukan sekadar sistem irigasi untuk sawah, tetapi juga sebuah mekanisme sosial-ekologis yang menahan, menyalurkan, dan membagi air secara adil. Ketika lahan sawah hilang dan jalur subak terputus, kita bukan hanya kehilangan ruang produksi pangan, tetapi juga kehilangan mekanisme pengendali banjir alami. Kita sering bangga pada pengakuan dunia terhadap subak, tetapi secara bersamaan mengabaikan fungsi ekologisnya di lapangan.
Data Terbaru: Alarm yang Tidak Boleh Diabaikan
Banjir parah tahun ini harus dibaca sebagai sinyal sistemik. Data dari BPBD menunjukkan lebih dari puluhan titik banjir di Denpasar, Badung, dan Gianyar dengan ketinggian air mencapai setengah meter di beberapa lokasi. Sekolah-sekolah diliburkan, lalu lintas macet total, dan ratusan keluarga harus mengungsi. Kerugian ekonomi harian akibat gangguan transportasi dan kerusakan properti diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dalam jangka panjang, banjir berulang juga menurunkan nilai properti, menggerus produktivitas, dan memicu kerentanan sosial.
Quick Wins ke Reformasi Tata Ruang
Sebagai peneliti sistem perkotaan, saya percaya masalah ini bisa dipecahkan, asalkan ada kemauan politik yang kuat dan koordinasi lintas sektor. Kita perlu memikirkan solusi berlapis, dari yang bisa dilakukan segera hingga reformasi struktural yang memerlukan waktu.
Berikut peta jalan (roadmap) yang bisa dijalankan dalam 12 bulan ke depan:
- 1 bulan: bersihkan drainase dan sungai secara serentak di seluruh Sarbagita. Libatkan pemerintah, desa adat, relawan, dan sektor swasta.
- 3 bulan: bangun kolam retensi sementara di lahan kosong strategis, pasang pompa di titik banjir kronis.
- 6 bulan: program sumur resapan massal di sekolah, kantor, dan perumahan, terutama di kawasan hulu Badung dan Gianyar.
- 12 bulan: rehabilitasi jalur subak yang tersisa, tetapkan zona lindung subak, dan masukkan ke revisi tata ruang kota.
Langkah-langkah ini bukan hanya teknis, tetapi juga simbol bahwa pemerintah merespons masalah dengan serius. Quick wins seperti ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memberi ruang bagi perencanaan jangka panjang.
Fokus Jangka Panjang Lewat Tata Ruang dan Regulasi
Kita perlu memastikan masalah ini tidak berulang setiap tahun dengan solusi permanen berbasis tata ruang dan regulasi yang kuat, melalui beberapa poin berikut :
Pertama, zona resapan harus ditetapkan dan dilindungi secara hukum. Ini berarti tidak boleh ada pembangunan masif di wilayah yang berfungsi menahan air hujan. Dengan perlindungan hukum, pemerintah bisa mencegah alih fungsi lahan kritis yang memperburuk banjir.
Kedua, setiap izin pembangunan sebaiknya mewajibkan minimal ruang terbuka hijau dan permukaan yang bisa meresap air. Jalan, halaman, dan area parkir tidak harus semuanya beton. Permeable pavement, biopori, dan taman kecil bisa membuat perbedaan besar pada jumlah air yang diserap.
Ketiga, pemerintah perlu mengadopsi prinsip sponge city, mendorong pembangunan infrastruktur hijau seperti taman resapan, biopori, kolam detensi, dan trotoar berpori. Kota yang bisa “menyerap” air hujan akan jauh lebih tahan terhadap banjir.
Keempat, pengembang harus diwajibkan melakukan perhitungan dampak hidrologi. Mereka perlu menyertakan data koefisien limpasan dan rencana pengelolaan air hujan dalam dokumen perencanaan. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi cara memastikan bahwa setiap proyek ikut menjaga keseimbangan hidrologi kota.
Kelima, perlu diterapkan biaya layanan drainase atau stormwater fee. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur hijau publik, seperti sumur resapan, kolam retensi, atau pelebaran saluran drainase. Kota-kota seperti Singapura sudah mempraktikkannya, dan hasilnya nyata: risiko banjir berkurang drastis.
Dan yang tidak kalah penting adalah menghidupkan kembali peran komunitas. Bali memiliki keunggulan sosial-budaya: jaringan desa adat dan subak. Mereka bisa menjadi mitra strategis dalam program konservasi hulu, pemeliharaan saluran, dan edukasi masyarakat. Partisipasi publik dalam pemetaan titik banjir dan pelaporan kondisi drainase juga bisa mempercepat respons pemerintah.
Preseden Dari Kota Lain
Kota-kota seperti Singapura, Tokyo, dan Kopenhagen telah berhasil menurunkan risiko banjir dengan kombinasi teknologi, tata ruang, dan keterlibatan masyarakat. Singapura, misalnya, menetapkan rasio ruang terbuka minimum di setiap pengembangan baru dan membangun jaringan kolam detensi yang juga berfungsi sebagai ruang publik. Kopenhagen mengubah lapangan kota menjadi waduk sementara ketika hujan ekstrem datang. Bali bisa mengambil pelajaran ini, disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi geografis kita.
Jangan Menunggu Banjir Berikutnya
Banjir bukan takdir. Ini hasil dari serangkaian keputusan tata ruang, pembangunan, dan kebijakan yang kita ambil. Jika kita tidak berubah, kerugian akan terus menumpuk, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Musim hujan tahun ini seharusnya menjadi wake-up call terbesar.
Kita perlu menjadikan banjir bukan sekadar berita viral sesaat, melainkan momentum untuk menata ulang kota kita. Dengan kombinasi aksi cepat, perencanaan berbasis data, dan penguatan regulasi, kita bisa mengubah musim hujan dari ancaman menjadi berkah. Bali selalu jadi contoh harmoni antara manusia dan alam. Mari kita buktikan bahwa harmoni itu bisa kita pulihkan sebelum genangan air menjadi simbol kegagalan kolektif kita.
Tulisan ini ditujukan sebagai ajakan berpikir dan bertindak, baik bagi pemerintah daerah, pengembang, maupun masyarakat umum. Bali berhak mendapatkan tata kota yang membuat musim hujan kembali membawa kesejukan, bukan bencana.
legianbet legianbet legianbet kampungbet


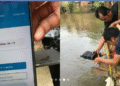


![[Matan Ai] Bali dan Pembusukan Pembangunan](https://balebengong.id/wp-content/uploads/2025/01/KOLOM-MATAN-AI-oleh-I-Ngurah-Suryawan-by-Gus-Dark1-120x86.jpg)