
Bali surga dunia, katanya.
Kaya akan pemandangan alam indah, gunung nan megah, pantai dan ombak untuk berselancar. Kaya budaya dengan segala filosofi mendalam di setiap tarian, pakaian tradisional, dan ritual keagamaan. Belum lagi wisata kuliner yang nikmat, enak, murah dan banyak.
Paket komplit? Belum.
Bali juga populer dengan gaya hidup modern. Hotel dan vila mewah siap memberi pelayanan papan atas. Fasilitas nightlife turut menjadi daya tarik turis untuk datang dan menghabiskan uang di sini. Bali menjadi magnet pengunjung dari berbagai latar belakang untuk menikmatinya, terutama turis mancanegara. Mereka diuntungkan oleh perbedaan nilai mata uangnya terhadap rupiah.
Bali memanjakan turis dengan pilihan wisata yang beragam, sesuai dengan gaya hidup yang diinginkan. Mewah? Ada. Menengah? Banyak. Bawah? Hmm, ada. Kualitas bukan lagi masalah. Siapapun yang punya (dan tidak) punya uang, bisa menghabiskan waktu dan bersenang-senang di Bali.
Tidak punya uang maksudnya bukanlah tidak punya uang sama sekali. Tentu mereka yang ingin berlibur perlu uang. Minimal untuk membayar tempat tinggal dan makan. Namun, yang menjadi definisi tidak punya uang adalah ketika gaya hidup yang diinginkan tidak sesuai dengan nominal uang yang dimiliki pada saat yang sama. Lalu, mereka menghalalkan segala cara untuk menjadi terlihat “punya uang” dan menikmati fasilitas yang ada.
Lalu masalahnya di mana? Itulah yang melahirkan tulisan ini, sengaja dibuat untuk mencari kawan diskusi.
Kita cukup tahu. Karakter Bali yang didominasi sektor pariwisata serta adanya faktor perbedaan nominal mata uang, tanpa disadari (atau mungkin sadar, tapi mengelak) menjadikan warganya mendewakan turis mancanegara. Kita biasa menyebutnya bule.
Kita menganggap bule adalah sosok yang ‘lebih’ dari kita. Lebih bagus, lebih keren, lebih berada, lebih terhormat, lebih kaya, dan lebih lain-lainnya. Payahnya, jiwa melayani yang menjadi karakter bangsa kita sedari dulu kala, membuat kita semakin menganggap bule adalah raja, dan kita, tentu saja, pelayan.
Sektor pariwisata adalah sektor yang tricky. Kita beranggapan bahwa tamu adalah raja. Itu saja sudah cukup menjelaskan bagaimana masyarakat kita menempatkan diri dalam rantai transaksinya. Dunia hospitality mau tak mau harus memberikan pelayanan terbaik untuk para tamu. Harapannya, turis akan senang dan menggunakan jasa yang mereka peroleh ketika kembali lagi suatu saat nanti. Maka, bisnis pun tetap berjalan dan ekonomi berputar secara berkelanjutan.
Kita terkesan rela melakukan apa saja untuk itu. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi para tamu, dan pastinya, untuk uang.

Rasisme
Tidak dipungkiri, dunia pariwisata di Bali adalah sektor yang menghasilkan uang paling cepat. Gaji boleh UMR, tapi untuk uang tip, para bule itu rupanya tidak segan memberikan tip besar dengan mata uang negara mereka. Bukan hanya dolar, tapi juga euro, poundsterling, swedish krona, swiss franc dan lainnya. Silakan dikalikan sendiri nominalnya dalam rupiah. Dalam satu hari, uang tip saja bisa lebih dari nilai gaji bulanan para pelaku pariwisata di lapangan.
Lho, kan bagus? Simbiosis mutualisme, bukan? Iya.
Jika kedua belah pihak melakukan hal sama, saling menghormati tata krama dan mau berpedoman pada desa, kala, patra. Namun, apa yang terjadi belakangan ini membuat kita harus berpikir dua kali. Sudah beberapa kali terbukti, betapa masyarakat kita menganggap bule adalah Tuhannya ekonomi pariwisata di Bali.
Saya sendiri pernah mengalaminya. Beberapa kawan yang sudah pernah saya ceritakan menganggap pengalaman saya ini adalah diskriminasi. Ada pula yang menyebut sebagai bagian dari rasisme. Namun, apapun penyebutannya, seharusnya hal seperti ini tidak terjadi di Bali. Di rumah yang mereka sebut sebagai surganya pariwisata dengan keramahan warga lokal.
Jadi, beberapa tahun lalu saya berkesempatan berkarya di salah satu lembaga internasional di Bali. Layaknya kehidupan profesional skala internasional, komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Plus, tim dan kawan sejawat di lembaga tersebut mayoritas bule. Sebagai satu dari warga negara Indonesia yang bekerja di sana, saya diberikan kepercayaan lebih untuk mengelola manajemen finansial.
Kejadiannya adalah ketika kami merayakan berakhirnya satu project yang kami kerjakan bersama. Kebetulan saya sebagai project coordinator. Saat itu, semua tim yang terdiri dari delapan bule dan saya sendiri sebagai WNI, berkunjung ke salah satu tempat makan fancy di daerah Seminyak. Candle light dinner by the beach, begitu kami namakan hari itu.
Dua hari sebelumnya, saya sudah terlebih dulu ke tempat itu. Memesan tempat menggunakan nama saya. Lebih tepatnya nama panggilan saya, Tya. Yang saya ingat ketika memesan tempat, saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Kami datang di lokasi secara bersamaan. Masuk pun bersamaan. Namun, kebiasaan saya adalah selalu berjalan paling belakang. Untuk mengamati, dan memastikan semua tidak ada yang tertinggal.
Kami masuk melalui pintu yang hanya muat untuk satu orang dewasa. Pegawai menanyakan nama sesuai pesanan. Tentu saja semua menyebut nama saya, Tya. Kemudian satu persatu semua bule yang berjalan di depan saya disambut dan dikalungi bunga selamat datang. Saya tersenyum senang, keberhasilan project ditutup dengan kebahagian semua anggota tim. Perayaan yang sesungguhnya, saya berucap dalam hati.
Menjadi aneh ketika kalung bunga hanya tersedia delapan, sementara saya memesan untuk sembilan orang. Karena saya yang paling belakang, saya tidak kebagian. Ahh tidak masalah, pikir saya waktu itu. Mungkin pihak restoran lalai. Toh, mereka sudah meminta maaf.
Tim saya (yang kebetulan cukup solid) melepas kalung bunga dan mengembalikannya ke karyawan terdekat. Mereka bahkan memberikan masukan kepada pihak restoran untuk lebih sigap dalam persiapan dan lebih memperhatikan setiap detail pesanan.
Singkat cerita, perayaan selesai. Perut kenyang, semua senang. Tibalah untuk pembayaran. Saya memanggil salah satu karyawan terdekat dan meminta bill. Lucunya, karyawan datang dan menyerahkan bill senilai jutaan itu ke salah satu bule laki-laki yang ada di meja. Tentu saja bule ini menolak dengan halus dan mengatakan, “Oh no, not me. Tya will pay for all of these. She is the boss”.
Well, sebenarnya bukan saya. Kebetulan saya yang bertanggung jawab dengan finansial kantor, dan kegiatan hari ini ditanggung oleh anggaran dari kantor.
Kemudian karyawan restoran tersebut berpindah dan mendekat ke saya. Sebelumnya, dia memandangi saya dari atas sampai bawah, seakan-akan memastikan bahwa saya adalah orang yang tepat untuk membayar pengeluaran hari itu. Mendadak nada bicara dan bahasa tubuhnya berubah. Menjadi ketus dan tanpa memandang mata saya dia bertanya dalam bahasa Indonesia, “Coba lihat, kartu kreditnya apa, ya?”.
Saya mendelik, sambil tersenyum kecut.
Kawan-kawan bule saya yang bisa berbahasa Indonesia pun cukup terkejut dengan perubahan gestur dan intonasi dari karyawan tersebut. Seakan tidak percaya, salah satu kawan saya bertanya kepadanya, memastikan dalam bahasa Indonesia, “Apakah kamu sengaja mengubah nada bicaramu kepada Tya? Kamu tidak sopan dan kamu bahkan tidak memandang matanya ketika meminta pembayaran”.
Saya cukup sabar untuk tidak menggebrak meja. Hanya menarik napas panjang dan mengeluarkan kartu untuk pembayaran. “Saya gak punya kartu kredit, adanya debit. Apakah masih bisa diterima buat bayar? Kalau tidak, mungkin saya harus mencari ATM terdekat dan membayarnya dengan uang tunai.”
Karyawan tersebut langsung mengambil kartu dan meminta saya menunggu. Tidak ada kata maaf. Seperti tanpa rasa bersalah ia melenggang pergi begitu saja. Kawan-kawan saya menjadi mulai serius. Mempertanyakan bagaimana mungkin orang Bali bisa melakukan hal begitu kepada orangnya sendiri.
Bahkan sebagai bule, mereka tidak pernah mendapatkan perlakuan begitu selama di Bali. Mereka bilang saya punya alasan tepat untuk marah. Pertama karena kalung bunga yang tidak tepat hitung. Kedua, cara karyawannya memperlakukan saya seakan-akan tidak percaya ada warga lokal yang membayar bill senilai jutaan untuk kawan-kawan bulenya.
Saya cukup beruntung dibela. Mungkin mereka keki juga, takut makanannya gak jadi dibayarin. Hahaha. Saya bisa tertawa ketika menceritakan hal ini sekarang, tapi saya masih ingat bagaimana saya merasa kesal, marah, tersinggung dan juga sedih ketika itu terjadi.
Waktu itu, saya tidak percaya hal tersebut bisa terjadi di Bali. Di tempat tinggalku sendiri, dan dilakukan oleh orang Bali terhadap sesamanya. Padahal selama ini Bali dikenal mempunyai pedoman tat twam asi. Lalu, kenapa kehangatan di dunia pariwisata hanya diberikan kepada bule saja?

Lahan Basah
Sekarang saya mulai bisa berpikir jernih dan lebih berlogika. Sekali lagi, pariwisata di Bali erat kaitannya dengan lahan basah dan menghasilkan uang cepat. Hal yang selama ini hanya kita dapatkan dari mereka yang mempunyai nominal mata uang lebih tinggi dari rupiah.
Tanpa sadar (atau mungkin sadar, tapi mengelak), hal tersebut membuat kita mendewakan bule tanpa berpikir dengan akal sehat tentang nilai kemanusiaan. Kita mengkotakkan pikiran dan pelayanan kita terhadap warna kulit. Sepertinya diskriminasi dan rasis memang terjadi di sini.
Pola pikir bule-oriented itu menciptakan hal serupa seperti efek domino. Banyak bule merasa superior dibanding warna lokal. Merasa lebih, karena selama ini dilebih-lebihkan. Merasa raja, karena selama ini diperlakukan seperti raja. Sedihnya, tidak sedikit bule yang merasa bisa melakukan apa saja karena mereka punya uang.
Memang tidak bisa disamaratakan. Tidak semua orang lokal seperti itu, dan tidak semua bule demikian. Namun, pengalaman-pengalaman ini menjadi pembelajaran bahwa kejadian seperti ini bisa saja terjadi lagi dan lagi. Apabila pola pikir kita masih tetap sama, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di lain waktu.
Jika pengalaman saya di atas adalah mengenai perlakuan tidak adil oleh warga Bali sendiri, di bawah ini adalah beberapa pengalaman dengan perlakuan semena-mena dari pihak bule.
Saya membaca tulisan Rini Siallagan di BaleBengong (Baca: Sesungguhnya, Tak Semua Pasien WNA sesuai citranya). Pengalaman beliau sebagai dokter cukup pelik menghadapi beberapa pasien bule. Seorang kawan lain, yang berprofesi sebagai dokter gigi di salah satu klinik swasta di daerah Seminyak juga pernah menceritakan pengalaman serupa.
Suatu hari, ia kedatangan pasien dari salah satu negara di Eropa Barat. Tipikal penampilannya sudah seperti warga lokal yang tinggal dekat dengan pantai. Celana pendek, kaos oblong tanpa lengan, sandal jepit dan rambut serampangan. Seperti memperlakukan pada setiap pasien pada umumnya, resepsionis pun menyapa pasien tersebut dan menanyakan keperluannya. Rupanya ia ingin mencabut gigi geraham paling belakang, yang kemungkinan diperlukan tindakan operasi.
Resepsionis kemudian memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi. Pasien masih cukup kooperatif sampai akhirnya ia mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia mengambil formulir pendaftaran dan mengisinya dengan duduk lesehan di lantai. Sambil menggumam, ia mulai menanyakan siapa dokter gigi yang akan menanganinya, karena ia sudah tidak tahan akan rasa sakitnya. Di saat yang sama, kawan saya yang dokter gigi keluar dan menemui pasien. Ia tampak bingung karena pasien duduk di lantai dan berbicara dengan nada tinggi.
Pasien ini kemudian mulai menanyakan berapa harga yang harus ia bayar. Pertanyaan wajar sebenarnya. Hanya saja ia kemukakan dengan intonasi yang tidak biasa. Sebagai dokter gigi, kawan saya cukup profesional dan menjawab, “Kami perlu melakukan observasi dulu untuk mengetahui tindakan yang harus kami lakukan untuk gigi gerahammu. Apakah hanya untuk mencabut atau perlu tindakan operasi. Sampai kami bisa melakukan hal tersebut, kami tidak bisa menyebutkan nominal yang pasti.”
Ia juga menanyakan apakah pasien memiliki asuransi yang bisa menjamin tindakan medis.
Sayangnya, pertanyaan ini tidak dijawab. Bahkan pasien bule bersikeras tidak perlu observasi karena ia sudah mempunyai hasil rontgen. Dia memaksa dokter untuk segera mencabut giginya saat itu juga. “Apakah kami bisa melihat hasil rontgennya?” kawan saya perlu bertanya. Namun, pasien bule kembali bernada tinggi, memaksa segera ditangani, tetapi tidak menunjukkan apa yang diminta.
Kawan saya kemudian menyebutkan kisaran harga untuk penanganan cabut gigi geraham. Saat itulah pasien bule meledak, “Apakah kamu ingin merampok saya? Tidak mungkin setinggi itu. Lagian, saya sudah punya hasil rontgennya. Saya bisa mendapatkan harga lebih murah di negara saya. Dengan pelayanan dokter gigi yang lebih baik dari Anda! Di negara terbaik di seluruh dunia! Sudahlah, saya hanya mau gigi saya dicabut sekarang juga. Ayo kita mulai saja.”
Kawan saya memastikan kehendak pasien bule dan meminta ia menandatangani pernyataan sebagai wajib bayar, dengan mencantumkan kisaran nominal yang mungkin timbul untuk tindakan yang diperlukan. Sayangnya, pasien bule tidak mau menandatanganinya dan kembali berteriak bahwa klinik tersebut sedang mencoba merampoknya.
Bukan hanya itu. Dia kembali menyebutkan bahwa negaranya adalah negara yang memiliki fasilitas kesehatan jauh lebih baik dari Bali, dengan dokter gigi yang lebih hebat daripada yang ada di sini.
Dokter gigi dan tim resepsionis mencoba menenangkan pasien bule ini dengan kembali menanyakan hasil rontgen. Namun, ia tidak menggubris. Ia mulai memaki, menggunakan kata-kata kasar yang tidak seharusnya diucapkan kepada orang yang ia perlukan bantuannya.
Merasa tersinggung, kawan saya mengucapkan satu kalimat yang mengakhiri semua tingkah laku pasien bule ini. “Jika memang negaramu mempunyai pelayanan seperti yang kamu ucapkan, dan bisa memberikan layanan sesuai dengan budget yang kamu miliki, silakan kembali ke negaramu sekarang juga. Nikmati semua fasilitas itu dengan baik.”
Pasien bule kembali memaki. Dia menunjukkan jari tengah, mengeluarkan ponsel genggamnya dan mulai mengambil gambar beberapa sudut di klinik itu. Ia berteriak dan mengatakan akan menyebarkan nama klinik itu di media sosial dengan tuduhan perampokan dan menolak memberikan pelayanan.
Sembari mengucapkan maaf, tim dokter gigi dan resepsionis mempersilakan pasien untuk pergi.
Bisa kita bayangkan, betapa luar biasa terkuras secara emosional menangani pasien yang seperti itu. Belum lagi pihak klinik harus melakukan klarifikasi pada semua tanggapan di media sosial dan juga keluhan yang mungkin datang di kemudian hari.

Solusi Kuno
Berbicara mengenai sektor pariwisata, tidak bisa terlepas dari krisis akibat masa pandemi COVID-19. Setahun terakhir menjadi momen menyedihkan bagi dunia pariwisata. Bali yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor ini mengalami fase habis-habisan. Jangankan mengembangkan bisnis, berada pada posisi bertahan di masa krisis ini saja sudah menjadi prestasi luar biasa. Banyak yang menyerah kemudian gulung tikar.
Jumlah pengangguran? Jangan ditanya. Bisa dipastikan 81 persen penduduk Bali yang bekerja di sektor ini kehilangan pekerjaan akibat bisnis yang merugi (data Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali, Agustus 2020).
Banyak hal yang membuat pariwisata di Bali kehilangan napas lalu mati akibat pandemi ini. Pariwisata Bali berpangku tangan pada turis internasional. Sementara turis domestik bukanlah pasar utama. Jadi, tak bisa dipungkiri bahwa alasan adalah karena kehilangan bule-bule yang berkunjung ke Bali.
Tanpa bermaksud mendegradasikan sektor ini, Bali tampaknya tidak bisa kembali bangkit apabila tidak segera mencari alternatif pengembangan perekonomian. Kita tidak bisa selamanya bergantung sepenuhnya pada satu sektor yang ringkih. Pariwisata akan tetap menjadi primadona di Bali, tapi kita harus siap dengan segala konsekuensi. Termasuk seperti pada masa sekarang ini, ketika dunia dilanda pandemi.
Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa berdiri?
Jawabannya bukanlah sesuatu yang populer, atau bahkan mungkin terkesan kuno: pertanian. Bukan tanpa alasan, sektor pertanian di Bali sebenarnya sudah eksis sejak dulu kala. Bahkan jauh sebelum pariwisata berkembang. Namun, pertanian di Bali tidak semenarik pariwisata yang bisa mendatangkan fresh money dalam waktu cepat dengan lebih sedikit usaha. Sektor pertanian membutuhkan proses dan konsistensi terutama terkait perawatan hingga tiba masa menghasilkan. Petani adalah mereka yang bekerja keras dan memilih berpeluh deras untuk tetap bisa di desa daripada memilih jalan mudah untuk sektor pariwisata di kota.
Pandemi ini membuat lebih dari setengah penduduk Bali yang bekerja di perhotelan mengalami pemutusan hubungan kerja. Mereka tidak mempunyai pilihan selain harus kembali ke desa dan mengembangkan apa yang mereka punya di sana. Bagi yang mempunyai lahan, mereka kembali mengolahnya menjadi lahan produktif. Memulai menanam kembali dengan apa yang bisa menghasilkan, minimal untuk kebutuhan makan sehari-hari semacam sayur mayur dan umbi-umbian. Bagi yang tidak mempunyai lahan, mereka kini mulai berjualan. Bisnis kuliner menjadi pilihan favorit untuk bertahan di masa pandemi ini.
Sayangnya tulisan ini terbatas dan hanya berfokus pada mereka yang kembali bertani akibat krisis dan pandemi. Hal ini menarik, karena berdasarkan penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana, dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19 hanya terasa eksesif di daerah perkotaan, tapi sedikit sekali dirasakan di pedesaan yang notabene dominan sektor pertanian.
Contohnya untuk makan saja. Di daerah perkotaan, kita terbiasa bertransaksi menggunakan uang. Jika tidak ada uang, maka kita tidak bisa membeli makanan. Kehidupan di kota menjadi terasa berat dan susah untuk dipertahankan dalam keadaan lapar.
Lain halnya di desa. Uang bukanlah masalah utama, karena mereka mempunyai kebun dan menanam tanaman umur pendek yang bisa dimasak untuk makan sehari-hari. Uang hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, atau karena bahan baku utamanya sudah tersedia secara alami. Kehidupan ekonomi desa tetap berjalan normal.

Fakta Mengejutkan
Kebetulan pekerjaan profesional saya berinteraksi langsung dengan petani di Bali. Desember tahun lalu, tim kami melakukan riset evaluasi mengenai program gender budgeting dalam rantai nilai kakao. Program ini memberikan rekomendasi kebijakan finansial kepada Pemerintah Daerah terkait sektor pertanian berkelanjutan dan hubungannya dengan program pemberdayaan petani perempuan dan keterlibatan generasi muda di sektor pertanian.
Evaluasi tersebut mengumpulkan data dari 609 keluarga petani kakao di Kabupaten Jembrana, Bali bagian barat. Apa yang kami temukan di lapangan tampak mengejutkan karena bertolak belakang dengan hipotesis awal yang dirancang oleh tim peneliti.
Premis pertama bahwa petani kakao mengalami penurunan pendapatan akibat pasar global yang juga terdampak resesi ekonomi akibat pandemi, memang terbukti. Namun, penurunan pendapatan ini hanya terjadi pada pangsa ekspor dan pasar domestik untuk produk olahan hilir seperti biji kakao dan produk turunannya.
Premis kedua yang menyatakan petani kakao mengalami isu finansial akibat krisis ini yang rupanya ditentang oleh kondisi di lapangan. Faktanya, sumber pendapatan petani justru bertambah. Maraknya korban PHK dari kota yang kembali desa, membuat aktivitas pembukaan lahan pertanian meningkat. Pembukaan lahan ini membuka celah intensifikasi pertanian yang membutuhkan pengadaan bibit kakao untuk ditanam.
Dengan kata lain, di sektor hulu, permintaan akan bibit kakao justru meningkat tajam dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi petani kakao di Jembrana.
Salah satu petani perempuan program Kakao Lestari dari desa Penyaringan, I Made Budhi Ayu Anggraeni mengatakan bahwa hingga Desember 2020, ia dan suaminya sudah menjual bibit kakao lebih dari 18.000 bibit. Permintaan paling tinggi dalam satu minggu adalah sebanyak 5.000 bibit. Permintaan ini datang tidak hanya dari petani di Kabupaten Jembrana, tapi juga dari Kabupaten Singaraja dan Kabupaten Tabanan.
Made Ernawati, petani perempuan dari Subak Abian Amerta Taman Sari menimpali bahwa ia bersama subak abian setempat sudah melakukan penyebaran bibit sekitar 21.000 sebanyak 3 kali. Ditambah lagi saat ini mereka sedang melakukan pembibitan lagi sekitar 14.500 bibit.
Jika satu buah bibit kakao diberondol dengan harga Rp 10.000-Rp 15.000 per bibit tergantung dengan kualitasnya, silakan melakukan perhitungan berapa jumlah peningkatan pendapatan petani di masa pandemi ini.
“Harapannya tahun depan (2021) bibitnya sudah bisa disambung dan ditanam. Saya belum terlalu mengetahui kakao, tapi saya bersyukur dikelilingi petani-petani hebat yang tidak pelit ilmu untuk berbagi dan mengajari kami,” ujar Ernawati dengan optimis.
Kami sebagai pendamping petani pun turut berbahagia. Bukan dalam artian kami senang akan adanya pandemi ini. Namun, semacam blessing in disguise. Jumlah petani muda yang menjadi tantangan terbesar dalam sektor pertanian Indonesia turut meningkat. Kita cukup realistis bahwa generasi muda enggan terlibat di sektor pertanian karena dianggap kurang menjanjikan. Terutama jika disandingkan dengan pariwisata di Bali. Hampir 90 persen pemuda-pemudi desa akan memilih pergi ke kota ketimbang menjadi petani.
Namun, semenjak pandemi ini, pemuda-pemudi yang mengalami PHK dari perhotelan dan memutuskan kembali ke desa menjadi angka yang potensial untuk peningkatan keterlibatan anak muda di sektor pertanian. Di Subak Abian Amerta Taman Sari sendiri, dalam satu bulan terakhir telah terdaftar 13 petani muda baru.
Kecil memang, tapi ini adalah angka spektakuler ketika berbicara keterlibatan anak muda di sektor pertanian dalam jangka waktu yang singkat!
Mereka adalah anak-anak muda yang menjadi korban ringkihnya sektor pariwisata di Bali, yang memutuskan kembali ke desa dan mencari cara untuk tetap mampu berdikari. Siapa nyana, justru sektor inilah yang menyelamatkan kantong mereka di saat pandemi.
“Kalau tau potensi kakao seperti ini, sejak dulu saya garap. Gak usah dah kembali ke kota, jadi petani aja sudah bisa dapat jutaan,” kata Astiti Bakti, petani kakao perempuan dari Subak Abian Taman Sari menimpali temannya.
Memang, apapun yang kita lakukan mempunyai kesenangan dan risikonya masing-masing. Sektor pariwisata yang bergelimangan tip dengan mata uang bule dari mancanegara, dan juga sektor pertanian yang slow but sure dengan risiko-risiko yang ada. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan.
Namun, jika kita mencoba refleksi diri ke dalam sebelum ke luar, sebenarnya kita bisa sadar bahwa apa yang kita butuhkan sudah kita miliki sedari dulu kala. Hanya saja hal tersebut terbiaskan oleh sesuatu yang baru, yang datang dan mencoba membuat kita meninggalkan kekayaan yang kita miliki, untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan kita sendiri gagap untuk menggarapnya.
Paragraf ini akan merangkum tulisannya ini agar berakhir sesuai dengan judulnya. Bahwa sesungguhnya di mana pun, kapan pun dan dalam situasi yang bagaimanapun hendaknya kita berpikir, berkata dan berbuat sesuai lingkungan kita berada. Hal ini bersifat umum dan universal. Kenali apa yang kita miliki. Kuatkan akar agar tak mudah tergiring. Selebihnya kita optimalkan potensi sesuai dengan jati diri.
Jadi, siapapun kita, mau jadi bule maupun petani, kita semua sedang berjuang menghadapi pandemi ini. Semoga kita selalu sehat, berbuat sesuatu yang bermanfaat dan senantiasa berbahagia dengan pilihan kita masing-masing. Amin. [b]






















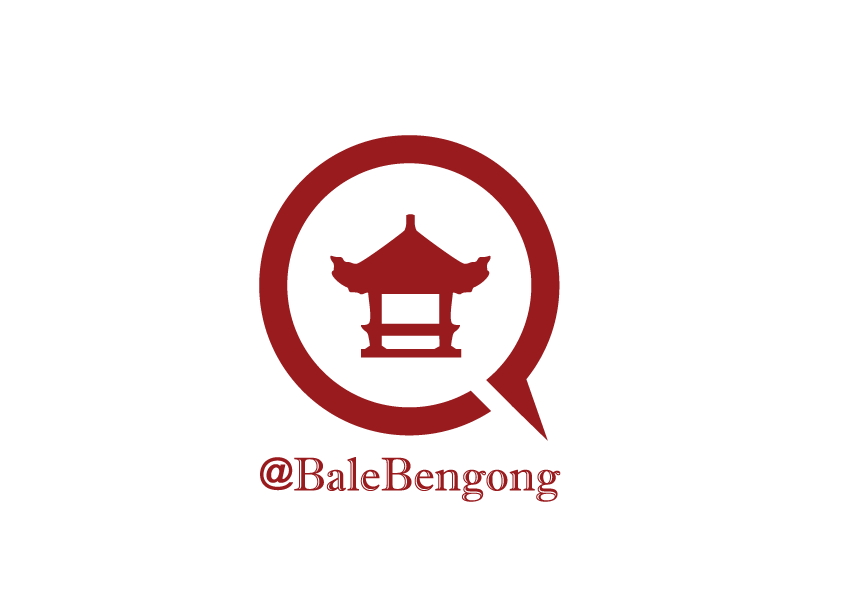
mental INLANDER warisan kolonial masih banyak di wisata2 indonesia
bukan bali doang.
kapan bangsa ini bisa maju kl mental jongos begini?
anggapan kl asing duitnya lbh banyak dr lokal udh ketinggalan jaman !!!