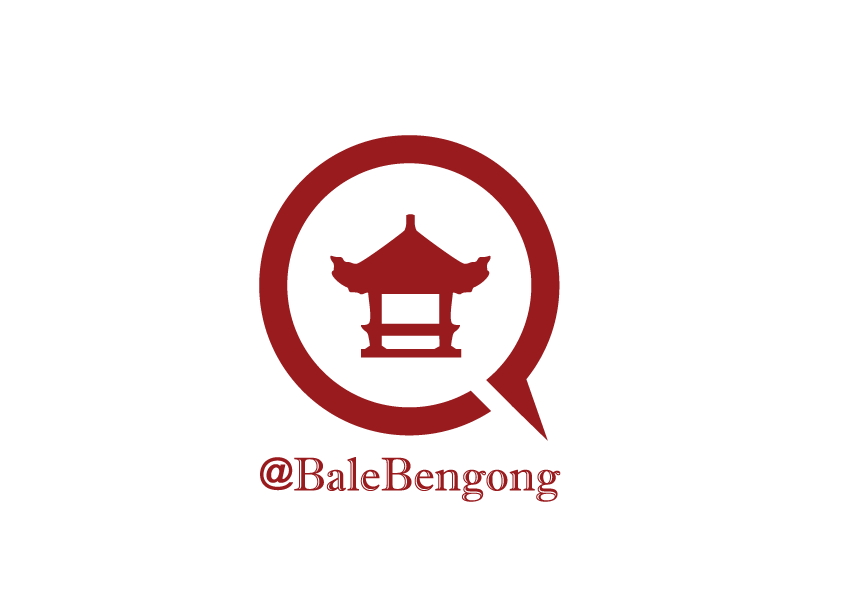“Kami melayani mereka yang berlibur dari hidup, sementara kami tak pernah berhenti bekerja di dalamnya dan tak pernah menikmatinya.”

Bali yang dipuja bak arsip suci harmoni seperti lukisan Walter Spies, sebenarnya hidup dalam kegentingan. Yadnya sakral terus berlangsung dalam ritme, canang dan dupa menyala hingga aromanya pun tercium hingga luar pulau. Kosmos pelan-pelan menata dirinya kembali menyulam makna pada tubuh sosial yang belum sepenuhnya tercerabut dari kosmologi leluhur.
Dari sisi lain, ritus baru juga muncul bernama kapitalisme global menuntut tumbal yang tak kalah nyata. Jam kerja panjang, upah timpang, dan ruang hidup yang kian menyempit.
Tak mengenal purnama-tilem upah yang serendah senyuman pura-pura, dan ruang hidup yang kian sempit seperti lorong harapan. Mereka yang menggerakkan mesin pariwisata jarang mencicipi kemakmuran yang mereka ciptakan, yang menghirup wangi dupa lebih sering adalah mereka yang tak pernah membeli bunga di pasar subuh.
Jarum jam smartwatch milik seorang tamu tergeletak malas di atas meja nakas biovarnish kayu jati menunjukan pukul 09.00 pagi. Sebut saja Wayan, 25 tahun. Tangannya cekatan melucuti sprei king size bed di sebuah private pool villa Uluwatu, semacam kuli modern industri pariwisata, dengan kolam pribadi yang airnya lebih biru daripada laut sebenarnya.
Harga sewa vila ini permalam, jutaan, dan entah berapa kali lipat UKM Badung dan harga harapan yang patah. Setara dengan lima kali gaji yang ia terima setiap bulan, itu pun jika ia beruntung mendapat service charge penuh. Sehari-hari Wayan merapikan bantal, membersihkan sisa gelas sampanye, dan memastikan bathtub marmer mengkilap layaknya candi yang siap dikunjungi.
Selesai itu, Wayan menumpangkan letihnya pada kemacetan menuju kos di Jimbaran kamar 3×3 meter, kamar mandi berbagi, sisa ruang menampung nasib yang dipres hingga pipih.
Sementara di Denpasar, asap dupa baru saja padam di pelinggih kosnya. Di sana, Gede, 23 tahun, merapikan seragam waiter yang ia setrika sendiri, sambil menimbang sisa dompet. Satu jam lagi, ia harus menyelinap melalui Seminyak epicentrum yang agaknya bercita-cita menjadi Versailles tropis untuk mulai shift sore di restoran bintang lima.
Malam itu, Gede akan tersenyum setebal meja marmer, menangkupkan tangan, dan merekomendasikan sebotol wine seharga lima juta rupiah kepada tamu asing sebuah angka yang 1,4 kali lipat melampaui gaji UMK yang ia terima sebulan penuh.
Setiap kali Gede menyebut vintage dan aftertaste, seolah ia sendiri pernah mencicipinya padahal, yang pernah ia minum hanyalah kopi sachet yang direbus di kompor kos, rasanya pahit, tapi jujur. Jujur melihat pahitnya kesenjangan sosial.
Wayan dan Gede adalah kuli surga yang bekerja demi memastikan surga tetap instagrammable. Memastikan citra kemewahan pulau ini tetap terjaga, sekaligus korban dari sistem yang sama.
Pukul sepuluh malam di gerbang sebuah beach club elite di Canggu, Komang, 35 tahun, berdiri tegap. Lengkap dengan seragam keamanan yang menutupi resah. Ia menata antrian influencer yang ingin menyingkirkan debu spiritual lewat minimum spend Rp 2 juta dengan musik Dejdak-Jeduk (DJ) dan kembang api tiap malam. Nominal yang hampir 70% gajinya UMK yang dibawa pulang sebulan, tapi tak ada diskon bagi penjaga pintu.
Selama delapan jam sifnya, Komang adalah wajah “kedamaian”, “keamanan” yang dijual pariwisata Bali. Namun, kedamaian itu hanya untuk mereka yang mampu membelinya.
Sementara pikirannya menyimpan kecemasan, dan bergulat tiap hari. Dari urusan rumah cicilan motor, biaya sekolah anak, jauh sebelum gajian berikutnya tiba. Dan harapan yang menipis seperti dupa menjelang pagi.
Cerita tadi adalah beberapa dari ratusan ribu potret paradoks Bali. Ia adalah penjaga literal dari “surga wisata” yang ironisnya mengecualikan kesejahteraan dirinya, keseimbangan yang tak pernah benar-benar imbang.
Dua Bali yang Berjalan Beriringan.
Bali resmi: Surga dunia, harmoni, pariwisata ramah.
Bali riil: Pekerja kontrak berpindah hunian, terancam PHK saat paceklik turis, sulit memiliki rumah, hidup di antara janji keberlanjutan dan kenyataan perebutan ruang.
Distorsi dua ritus ini dapat diamati di ruang publik yang terus bermetamorfosa, perlahan menjadi catwalk bagi kapitalisme yang berparfum dupa.
Tempat yang dulu halaman rumah, sawah tempat kita melayangan, dititipkan leluhur kini menjelma menjadi co-working space, restoran berkonsep conscious eating, beach club, tempat boxing, golf dan boutique villa berpesan please respect the culture walaupun mereka sendiri mencabut akarnya. Sampai-sampai kehilangan bahasa Bali dan mencoba bersosialisasi dengan bahasa Inggris alih-alih bahasa penghuni.
Cita rasa lokal pun berubah menjadi komoditas estetika, dipoles sebagai “authentic experience” bagi mereka yang mampu membelinya.
Warga yang tak mampu menanggung kenaikan harga tanah dan biaya hidup perlahan tersingkir ke pinggiran Denpasar, Mengwi, Gianyar hingga Tabanan, terperangkap dalam lingkaran sewa, kredit, dan mobilitas paksa yang tak kunjung usai. Maka tak heran kita melihat tingkat depresi di bali tinggi (Liputan6com, 2025).
Keramaian yang dulu dibangun dari mantra dan kidung kini digantikan dentum DJ Berawa (Detikbali, 2024). Sementara suara gamelan semakin tersingkir ke sudut playlist, agar tidak mengganggu kesenangan tamu. Kalah bukan karena inferior, tapi karena tidak punya manajer.
Ironi itu menyentuh batas absurditas ketika identitas sakral dijadikan merek dagang, pura menjadi latar swafoto; upacara menjadi konten “cultural immersion”; sesajen terselip di antara gelas cocktail beraroma pandan yang dipesan melalui POS system berlangganan.
Bagi wisatawan, semuanya tampak wajar di Instagram, Tiktok, Facebook, spiritualitas memang seharusnya estetik. Sering tak terlihat adalah ketegangan yang terus menggerus ruang spiritual masyarakat lokal.
Sementara omon-omon di brosur pariwisata menggumamkan mantra keseimbangan. Di balik narasi romantis itu, kita temukan angka yang lebih jujur.
Gaji yang tersengal mengejar harga cabai, jam kerja panjang tanpa payung, ketidakpastian perlindungan memadai; dan akses kesehatan yang masih timpang. Satu keluarga menghitung sisa gaji sebelum tanggal tua datang.
Lanskap sosial semacam ini, agama dan adat menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, sistem adat tetap menjadi penyangga sosial; namun di sisi lain, ia perlahan digiring untuk memainkan peran simbolik dalam industri yang lebih besar, menegaskan citra eksotis dan harmonis yang dijual kepada dunia.
Tak sedikit upacara yang terpaksa menyesuaikan nafsu pariwisata prosesi diundur agar tak mengganggu lalu lintas menuju villa cluster yang ditempati para digital nomad; pemedek menepi ketika rombongan turis melintas di tengah prosesi, mencari sudut terbaik untuk merekam konten. Ruang sakral dan ruang komersial kini saling tindih bukan karena harmoni, tetapi karena kompetisi ruang yang tak seimbang.
Di layar global, Bali dilukis sebagai sanctuary bagi yang ingin menemukan diri. Tempat menyembuhkan trauma, detox ketidakbahagiaan, menyatukan napas.
Namun bagi warganya, yang mereka temukan justru trauma baru. Beban ekonomi semakin berat, ketergantungan pada pariwisata kian akut, sementara lahan-lahan produktif menyusut direklasifikasi menjadi properti investasi yang mengaku spiritually aligned. Sialnya mereka yang menciptakan keindahan itu justru menjadi penonton dan sekaligus pekerja tanpa akses yang setara terhadap ruang yang sama.
Surga berubah menjadi paket langganan, diperjualbelikan dalam flexible check-in.
Turisme bukan hanya pertukaran jasa, tetapi pertukaran simbol. Nilai-nilai spiritual menjadi ikon, estetika lokal menjadi komoditas, dan bahasa ajeg Bali menjadi aksesori branding. Bali yang dahulu merupakan struktur sosial berbasis desa adat, kini dirasuki logika pasar yang melampaui kemampuan regulasi lokal.
Alih fungsi tanah berlangsung bukan semata karena permintaan, tetapi karena struktur insentif yang memihak modal migran baik domestik maupun asing. Kini, di kawasan seperti Canggu, Uluwatu, Seminyak, harga tanah melonjak ke Rp 2–5 miliar/are (9–10 juta/m²) bahkan lebih, menurut agen properti dan pasar sekunder lokal. Penduduk lokal yang menjual tanahnya akhirnya menyewa kembali tempat tinggal di kampung sendiri. Surga itu kini bertamu, bukan bertuan.
Dengan dalih inovasi dan perkembangan, desa adat perlahan terdorong untuk menegosiasikan identitasnya sendiri mempertahankan nilai komunal sekaligus beradaptasi pada mesin pariwisata yang tak mengenal henti bertransformasi menjadi predator alam.
Yang paling penting dan memukau bukan pemandangannya, tapi bagaimana “harmoni” menjadi iklan, bukan realitas. Ritual pembersihan jiwa yang dibeli para wisatawan, para pekerja membersihkan jejak ekses yang ditinggalkan setelahnya dengan tubuh yang semakin letih, tanpa jaminan imbal balik.
Modal tumbuh,
tenaga menyusut,
tapi senyum tetap wajib, soalnya ada review score.
Bagi sebagian, ini adalah hukum pasar.
Bagi sebagian lain, ini adalah adharma berbalut sunset vibes.
Bagi yang lain, ini bukan sekadar perdebatan moral, itulah kenyataan sehari-hari. Ritus hidup yang tak menunggu blessing untuk terus berjalan.
Mereka memanggul koper, mengangkat tray, menjaga pintu, menukar waktu mudanya untuk memastikan bahwa orang lain merasa lebih hidup atau setidaknya merasa pantas membuat konten.
Jika Bali adalah surga, maka surga itu bersyarat.
Aksesnya berdasarkan dompet,
pemandangannya berdasarkan reservasi,
ritualnya berdasarkan konten.
Seperti semua surga, menyisakan pertanyaan yang menggantung di udara asin pantai.
Bisakah sebuah pulau menjaga rohnya tetap utuh,
ketika tubuhnya disewakan per malam?