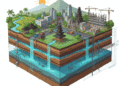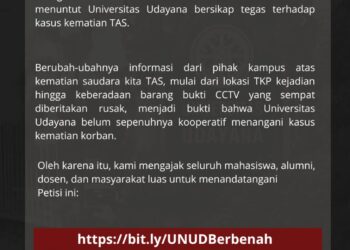Saya di kelas nol besar Taman Kanak-Kanak saat itu. Ketika saya tidak mengenakan seragam yang seharusnya dikenakan. Saya lupa hari apa. Yang pasti seragam tersebut sudah dipakai pada hari sebelumnya. Bapak memarahi saya dengan serius.
Meskipun saya lupa hari apa, namun saya masih ingat ucapan bapak, “Makanya, kalau pulang sekolah langsung ganti baju, jangan langsung bermain. Coba kau macam Arman dan Yoman (anak tetangga sebelah), mereka pulang sekolah langsung ganti seragam. Jadi masih bisa dipakai lagi hari ini….”
Saya tidak ingat kenapa saya menangis saat itu. Apakah karena rasa malu yang besar sebab mengenakan seragam berbeda dengan kawan-kawan. Atau rasa sakit karena bapak dengan terang-terangan memuji anak tetangga di hadapan saya di kala saya tengah lara memendam rasa minder yang membuncah.
Namun satu hal yang saya ingat, posisi kami masih di atas motor, di depan sekolah. Bapak membelakangi saya dan terus meracau, air mata saya serupa hujan. Saya perlahan turun dari motor dengan mata yang kabur.
Saya tidak sadar bahwa saya turun dari sisi yang salah di mana knalpot berada. Knalpot tentu saja masih membara karena mesin sepeda motor baru saja berhenti. Betis kanan saya menjadi santapan pagi bagi kecerobohan saya, meninggalkan bekas lepuhan yang hingga saat ini masih nyata.
Jejak kasar tentang bagaimana gigihnya saya melewati masa lampau sebab ini hanya salah satu cerita dari sekian kisah tentang kebiasaan membandingkan yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat kita.
Saya anak sulung dan cucu pertama dari keluarga Ibu. Dalam keluarga mana pun, sulung adalah panutan. Terlepas dari jenis kelaminnya, kuncup atau batang, maksud saya perempuan ataukah laki-laki, anak pertama selalu memiliki bebannya sendiri, tanggung jawab yang ia pikul sejak berada dalam rahim ibu.
Apakah manusia dapat meminta agar ia tidak dilahirkan sebagai orang yang pertama dalam sebuah keluarga? Tentu saja tidak. Karena hanya lagu yang bisa direquest di radio. #eh
Maka, apabila setelah anak pertama lahir dilanjutkan dengan anak kedua, ketiga dan seterusnya, tetaplah menjadi yang pertama dan sempurna. Sebab dia menjadi suri tauladan sejak masih bocah meskpun tidak ada pedoman khususnya. Tuntutan yang menempamu.
Itu bakat, alamiah. Kalau tak ada bakat, yah kamu sial.
Saya memiliki seorang adik laki-laki. Ia anak kedua dari kami yang jumlahnya seperti grup vokal. Kwartet. Ia menjadi idaman orang tua. Laki-laki sulung dalam keluarga. Didukung dengan perhatian dan kasih sayang selama dalam kandungan, ASI tanpa henti selama dua tahun dan gizi melimpah pada masa pertumbuhan.
Semua orang mengelu-elukan karena lumayan tampan. Lalu yang paling fatal, ia bukan cuma pintar tapi juga cerdas. Semua pelajaran mudah bagi dia. Segala jenis permainan akan ia menangkan, mulus maupun licik.
Saya pernah membuktikan ia curang pada permainan wayang, dan ia mengadu pada ibu bahwa saya menuduhnya. Toh ia memiliki cerita sendiri yang membuat ibu akan berbalik menyerang saya. Ingat, kamu sulung. Ngalah kenapa?
Kondisi itu jauh dibandingkan saya yang senang berkhayal dan membaca sajak di pojok kelas. Saya memang pernah melakukannya di depan kelas dan di panggung pada perayaan ulang tahun sekolah, namun hanya foto sebagai bukti. Pujian tak pernah datang karena yang dibahas adalah kegugupan saya bukan keberanian saya berada di hadapan sejuta umat sebagai siswi kelas II SD.
Adik saya tetaplah yang terbaik karena mewarisi daftar nilai hampir sempurna di setiap akhir caturwulan, yang sampai sekarang bisa dijadikan bahan cek dan ricek jika membutuhkan bukti.
Di setiap hari penerimaan rapor, saya memiliki kesadaran penuh untuk kembali ke rumah dalam kondisi siap siaga. Siap untuk didudukkan oleh bapak, ditatar dan menjadi tolok ukur bagi adik-adik sekalian. Tentu saja di hadapan ibu yang setia menjadi backing vocal tunggal alias sang pencatat kelalaian sepanjang sejarah.
Bayangkan, betapa tebalnya kulit saya hingga saat ini, karena pidato bapak dan catatan-catatan ibu tersebut sama sekali tidak berbekas di kepala. Bijaknya, saya mengambil semua pengalaman masa kecil itu sebagai salah satu fondasi kuat untuk menjadi tidak tahu diri dan tidak tahu malu selama itu resiko untuk maju. Halah. Pastinya masih dalam taraf sopan santun dan akhlak yang baik.
Adegan di atas biasanya sedikit didramatisir dengan cubitan di paha atau kata-kata busuk yang mampu menghalau udara. Ah ada lagi, siapa yang menduduki peringkat tertinggi dalam caturwulan ini akan mendapatkan hadiah dari bapak. Sungguh mengagumkan. Jelas bukan saya.
Hasil dari dua jam ritual membandingkan tersebut, adik-adik saya akan mulai meremehkan saya. Kakak perempuan sulungnya tidak sekeren kakak perempuan teman-temannya yang bisa ini, bisa itu. Tidak pantaslah untuk diteladani. Kakak perempuan saya biasa pergi bermain sampai petang, masuk hutan keluar hutan, mengambil buah mangga di kebun orang tanpa izin, memakannya tanpa dicuci dulu, sungguh menggelikan. Malas belajar, susah dimintai tolong mengerjakan PR berhitung dan suka bangun terlambat. Yang terburuklah pokoknya.
Beranjak ke lingkungan sekitar rumah atau lingkungan gaul orang-orang tua kita. Bayangan anak para pejabat, dari pejabat rumah ibadah sampai pejabat sekolah dan pejabat pemerintahan pasti akan dibahas satu per satu. Apalagi kalau anak sekian pejabat tersebut kebetulan sekali ada di sekolah yang sama dengan kita.
Sekalipun kamu memiliki kemampuan tetapi yang akan menjadi nilai dan kualitas atas dirimu adalah karena kamu anak ibu dan bapakmu bukan karena memang kamu mampu. Itu bisa menjadi kutukan. Bagaimana bisa secepatnya menemukan jati diri, lha wong kita dilatih untuk tidak menjadi diri sendiri sejak dini.
Tak jarang kata-kata pembanding tersebut seperti peluru mematikan, mematikan motivasi dan semangat untuk berkembang dan bereksplorasi sesuai kemampuan.
Apa orang tua pernah memikirkan terlebih dahulu bahasa-bahasa yang mereka gunakan untuk mendukung anak-anaknya? Apa pernah mereka berusaha untuk merefleksi diri sendiri dan mencari kesempatan membenahi dan membina pikiran maupun mulut mereka sendiri? Bocah nakal tak akan paham sindiran di usianya yang masih lebih bersukacita bermain dan berkelahi.
Atau, pernahkah memperhatikan tingkah laku mereka sendiri yang sebenarnya adalah refleksi nyata bagi anak-anak mereka? Mungkin di masa sekarang, telah banyak orang tua mulai sadar, cukup pengetahuan dan perlahan-lahan mengubah kebiasaan. Bagi orang tua yang peduli pada pertumbuhan anaknya, tidak bagi mereka yang menyerahkan takdir anak-anaknya pada semesta.
Maka pepatah “buah jatuh tidak jauh dari pohon” yang legendaris itu, bukanlah omong kosong belaka. Orang tua hendaklah sadar bahwa mereka adalah pion utama yang menentukan hajat nasib anak-anaknya di masa depan. Orang tua adalah awal dari sebuah kehidupan. Rumah adalah tempat segalanya bermula. Bukan rumah sakit. Numpang lahir di rumah sakit, iya. Karena orang tua adalah tonggak sejarah, pedoman arah.
Berhentilah membandingkan anak anda dengan anak orang lain. Terkadang keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh anak-anak bergantung pada ajaran dan anjuran orang tua baik melalui kata-kata maupun tindakan refleks yang nyata terlihat, secara sengaja maupun tidak sengaja.
Saya belum jadi orang tua. Belum tahu kapan. Saya juga belum punya anak, yah karena belum jadi orang tua. Tetapi omongan saya seolah-olah sudah punya pengalaman berkeluarga yah. Yah iyalah, saya anak dari keluarga saya. Anak perempuan sulung, jika anda menyimak dengan baik paragraf ketiga tulisan ini.
Jadi saya merasa saya memiliki kapasitas untuk berbicara tentang kebiasaan ini, karena dampaknya luar biasa. Konkretnya, saya betul-betul baru memiliki kepercayaan diri absolut saat usia saya sudah menginjak seperempat abad. Mau tahu kenapa? Karena yang sudah kalian telusuri dari awal tadi. Itu nyata!
Yang mungkin belum kita ketahui, kebiasaan membandingkan ini dapat bersarang lama dan berkembang melar sesuai pribadi seseorang. Pada mereka yang teguh hati, hal-hal semacam perbandingan akan memacu penemuan jati diri. Namun pada mereka yang hanya pandai bersolek, tuntutan perbandingan memicu diri untuk selalu terlihat sempurna di hadapan orang lain.
Yang sebaliknya, memperlihatkan semangat berkompetisi tiada akhir, kompetisi yang tidak membangun diri sama sekali. Mereka justru menciptakan cermin dalam hidup orang lain dan menjadi bayangan yang buruk. Contoh klasik, para follower pengikut tren? Yang lebih galau besok harus pakai baju apa dan lipstik warna apa atau dasi dan kemeja warna senada atau tabrak lari aja biar terkesan cetar?
Hm, agar lebih berasa, setelah baca tulisan ini, mari kita perhatikan anak-anak kita, keponakan kita, dan anak tetangga kita. Mereka dapat menjadi variabel paling jelas saat ini.
Generasi keluarga anda dan saya, ditentukan oleh apa yang kita ucapkan hari ini. [b]