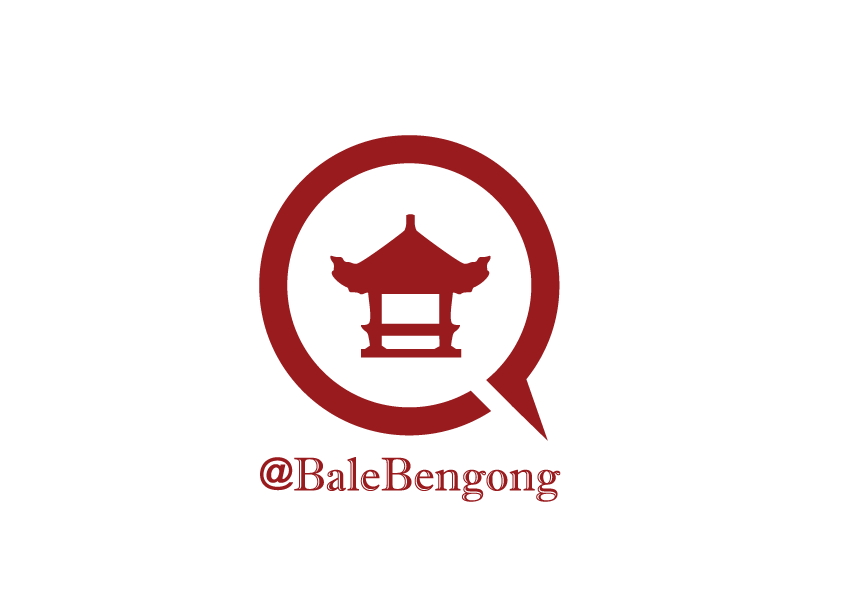Banjir yang melanda Kota Denpasar dan sekitarnya pada 10 September 2025 bukan hanya meninggalkan jejak genangan air dan kerusakan infrastruktur. Dampak yang sering terlupakan, namun tidak kalah serius, adalah ancaman kesehatan masyarakat setelah banjir. Lingkungan yang lembab, tumpukan sampah di sungai hingga rumah, serta air yang terkontaminasi menciptakan kondisi ideal bagi timbulnya berbagai penyakit menular. Sehingga mengapa kewaspadaan harus tetap dijaga, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar warga lebih siap menghadapi risiko kesehatan yang sering kali datang diam-diam setelah bencana.
Salah satu penyakit yang kerap muncul pasca banjir adalah penyakit kulit. Air banjir yang bercampur dengan lumpur, limbah rumah tangga, hingga kotoran hewan, bisa menimbulkan iritasi dan infeksi pada kulit. Banyak warga yang harus beraktivitas di air banjir, misalnya menyelamatkan barang, membersihkan rumahnya, atau hanya melintasi genangan banjir, sering kali tidak memiliki perlindungan memadai seperti sepatu bot atau sarung tangan. Akibatnya, kulit menjadi rentan terhadap penyakit seperti dermatitis, gatal-gatal, dan infeksi jamur. Menurut laporan penelitian oleh Afandi dkk. (2024), prevalensi penyakit kulit dapat meningkat hingga 30% di wilayah terdampak banjir jika tidak ada upaya pencegahan.
Selain kulit, masalah pencernaan juga menjadi ancaman serius. Air bersih pasca banjir sering kali sulit didapatkan, sehingga risiko kontaminasi pada makanan dan minuman meningkat tajam. Penyakit diare, muntaber, hingga hepatitis A dapat menyebar dengan cepat. Data dari WHO (2013) menunjukkan bahwa lebih dari 40% kasus diare di wilayah pasca banjir disebabkan oleh konsumsi air yang tidak layak. Di Bali, yang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, risiko ini semakin besar. Apalagi jika banjir merendam septic tank atau saluran limbah di rumah, kontaminasi kotoran manusia bisa masuk ke sumber air bersih warga seperti sumur bor ataupun sumur gali.
Tidak kalah penting, demam berdarah (DB) juga menjadi ancaman. Setelah banjir, genangan air sering tertinggal di halaman rumah, selokan, dan wadah terbuka. Kondisi ini merupakan tempat ideal bagi nyamuk berkembang biak. Laporan Kementerian Kesehatan RI (2022) mencatat bahwa kasus DBD sering mengalami peningkatan tajam setelah musim hujan atau peristiwa banjir besar. Oleh karena itu, meski genangan air banjir telah surut, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi munculnya sarang nyamuk baru.
Dari sisi kesehatan pernapasan, banjir juga membawa dampak tidak langsung. Rumah yang terendam dan lembap sering kali menjadi sarang jamur, debu, dan bakteri. Setelah banjir, aktivitas membersihkan rumah dan tempat tinggal kerap bisa memicu masalah pernapasan seperti ISPA, asma, atau alergi. Banjir mungkin saja dapat meningkatkan risiko penyakit terutama pada anak-anak dan lansia. Bagi masyarakat perkotaan seperti Denpasar yang padat, penyebaran penyakit ini bisa berlangsung cepat jika tidak diantisipasi.
Menghadapi semua potensi penyakit ini, kuncinya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tidak perlu langkah rumit, cukup memastikan selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, gunakan air bersih untuk minum dan memasak, jangan lupa memakai alas kaki ketika membersihkan sisa banjir. Jika memungkinkan, warga bisa menggunakan cairan pembersih tambahan seperti cairan pembersih desinfektan untuk membersihkan lantai atau perabot yang terendam. Pada saat yang sama, penyelenggara daerah juga berperan penting dalam memastikan distribusi air bersih, layanan kesehatan, dan penyemprotan disinfektan di titik-titik rawan.
Selain itu yang kadang dilupakan pasca bencana yakni aspek psikologis. Bencana banjir tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga tekanan mental. Rasa cemas, sulit tidur, atau stres bisa melemahkan daya tahan tubuh, sehingga risiko terserang penyakit semakin besar. Kekhawatiran ini sangat mudah ditemukan dari keresahan dan ketakutan masyarakat ketika muncul hujan kembali beberapa waktu lalu baik lewat unggahan media sosial ataupun suara-suara dari tempat pengungsian.Studi oleh Reacher et al. (2004) di Inggris menemukan bahwa korban banjir yang mengalami stres berat lebih rentan terkena penyakit pencernaan dan infeksi saluran pernapasan dibandingkan mereka yang lebih stabil secara emosional. Artinya, menjaga kesehatan mental juga sama pentingnya dengan menjaga fisik. Di Bali, dukungan sosial melalui komunitas banjar, jalinan kekerabatan ataupun pendampingan trauma pasca bencana dari instansi kesehatan maupun relawasan bisa menjadi kekuatan untuk saling menguatkan pasca banjir.
Pada akhirnya, pemulihan pasca bencana bukan hanya persoalan perbaikan kerusakan infrastruktur atau tata kota, tetapi juga soal kesehatan masyarakat. Denpasar sebagai kota besar dengan dinamika urban yang tinggi harus belajar dari peristiwa ini. Edukasi masyarakat, distribusi pelayanan kesehatan darurat, dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit pasca banjir perlu dijadikan bagian dari sistem penanggulangan bencana.
Referensi
- Afandi, dkk. (2024). Analisis Kerentanan Kesehatan Penduduk Pasca Bencana. Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan.Volume 6 Nomor 2, 2024
- WHO. (2013). Floods: Climate Change and Health. World Health Organization.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes.
- Mortality and morbidity risks associated with floods: A systematic review and meta-analysis (Environmental Research, 2024)
- Reacher, M., et al. (2004). “Health Impacts of Flooding in Lewes: A Comparison of Reported Gastrointestinal and Other Illness and Mental Health in Flooded and Non-Flooded Households.” Communicable Disease and Public Health, 7(1), 39–46.







![[Matan Ai] Bali dan Pembusukan Pembangunan](https://balebengong.id/wp-content/uploads/2025/01/KOLOM-MATAN-AI-oleh-I-Ngurah-Suryawan-by-Gus-Dark1-120x86.jpg)