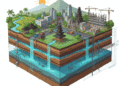“Ketika kampus menjauh dari denyut kehidupan masyarakat, ilmu kehilangan maknanya. Di Bali, menara gagasan berdiri megah, tapi tangga menuju akar rumput belum pernah benar-benar dibangun.”
Bali bukan hanya pulau seribu pura. Dalam dua dekade terakhir, ia juga menjelma menjadi pulau dengan ratusan guru besar, sebuah capaian yang secara akademik patut dibanggakan.
Universitas Udayana (Unud) kini memiliki lebih dari 243 profesor tetap, sekitar 14 persen dari total dosennya, melampaui rata-rata nasional. Universitas Warmadewa (Unwar) mencatat 23 guru besar, dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki 93 orang guru besar aktif. Jika digabung, Bali menampung lebih dari 360 guru besar, sebuah angka yang menegaskan potensi intelektual luar biasa di pulau kecil ini.
Namun di balik limpahan gelar akademik itu, muncul ironi yang tak bisa diabaikan: semakin banyak guru besar, semakin jarang terdengar suara mereka di ruang publik. Isu-isu genting seperti kemacetan, pariwisata massal, degradasi lingkungan, hingga krisis air jarang diiringi pandangan terbuka dari kalangan akademisi. Kita memiliki banyak profesor, tetapi sedikit pemikir yang berani turun ke gelanggang gagasan.
Kuantitas guru besar seharusnya menjadi modal besar bagi pembangunan daerah. Setiap pengukuhan profesor selalu diiringi pidato ilmiah tentang kearifan lokal, keberlanjutan, atau kebijakan publik. Namun setelah seremoni usai, gagasan – gagasan itu seolah menguap. Ilmu berhenti di podium, tidak menetes ke kebijakan.
Paradoks ini menunjukkan bahwa ilmu di Bali tumbuh tinggi, tetapi tidak berakar kuat dalam pengambilan keputusan publik. Kampus sibuk menulis jurnal demi akreditasi, sementara pemerintah sibuk mengejar proyek pembangunan dan citra politik. Keduanya berjalan sejajar tetapi jarang bersinggungan. Akibatnya, hasil riset akademik hanya berakhir di rak laporan, bukan menjadi dasar arah kebijakan. Fenomena ini bukan sekadar soal individu, tapi soal ekosistem berpikir yang kehilangan keberanian intelektual.
Di banyak kampus, budaya kritis kerap dianggap mengganggu harmoni kelembagaan. Guru besar yang bersuara keras berisiko dicap tidak “bijak”, sementara yang diam justru aman secara birokratis. Kampus akhirnya menjadi ruang steril, penuh aturan tapi miskin keberanian moral. Di sisi lain, pemerintah daerah memandang kampus hanya sebagai pelengkap teknis. Akademisi dilibatkan sekadar untuk memberi legitimasi atau tanda “sudah konsultasi dengan ahli”, bukan benar-benar sebagai mitra konseptual. Banyak hasil penelitian yang tak pernah dijadikan pijakan kebijakan, karena yang dicari bukan kebenaran ilmiah, tapi pembenaran administratif.
Di sinilah missing link paling krusial dalam pembangunan Bali hari ini: kampus kehilangan keberanian berpikir, sementara pemerintah kehilangan sumber pengetahuan. Dengan jumlah guru besar yang tinggi, seharusnya ada korelasi antara banyaknya pengetahuan dan kualitas kebijakan publik. Idealnya, setiap keputusan tentang tata ruang, transportasi, atau pariwisata berbasis pada riset dan kajian akademik.
Namun kenyataan berkata lain: relasi antara kampus dan pemerintah bersifat reaktif, bukan kolaboratif. Kampus baru diajak bicara setelah kebijakan diputuskan. Ilmu datang terlambat, dan kritik dianggap gangguan. Akibatnya, Bali bergerak dengan dua kaki yang tak seirama, kaki birokrasi yang cepat tapi pendek pandangan, dan kaki intelektual yang lambat atau bahkan lumpuh.
Namun situasi ini tidak harus menjadi takdir. Bali memiliki peluang besar untuk membangun model kemitraan baru antara kampus dan pemerintah, di mana universitas berperan sebagai think tank daerah, pusat produksi ide dan riset kebijakan yang langsung terhubung dengan kebutuhan publik.
Namun perubahan ini menuntut pergeseran paradigma di dua sisi: Di kampus, keberanian intelektual harus dihargai setara dengan publikasi ilmiah. Di pemerintahan, kebijakan harus berpijak pada data dan analisis, bukan sekadar intuisi politik. Dengan begitu, pengetahuan tak lagi berhenti di ruang seminar, tapi menetes ke jalan-jalan kota, ke sawah yang kekeringan, dan ke kebijakan publik yang menyentuh kehidupan nyata masyarakat. Kampus berhenti menjadi eksklusif, dan pemerintah berhenti memandang ilmu sebagai formalitas.
Sebuah analogi sederhana: kita telah membangun menara gading yang megah, tetapi lupa membangun tangga untuk turun ke akar rumput. Di puncak menara itu, ilmu memang tampak berkilau, tapi di bawahnya masyarakat berjalan dalam kegelapan.
Bali tidak kekurangan orang pintar. Yang hilang adalah sistem yang menghubungkan kecerdasan dengan keberanian, antara pengetahuan dengan keputusan. Kita memiliki ratusan guru besar, tapi sedikit public intellectual, sosok yang menjembatani dunia ide dengan dunia nyata.
Sudah saatnya kampus turun dari menara gadingnya, dan pemerintah membuka ruang dialog sejajar. Karena pembangunan sejatinya tidak lahir dari proyek, melainkan dari pemikiran. Dan pemikiran tidak akan bermakna tanpa keberanian untuk bersuara.
Jika jembatan antara ilmu dan kekuasaan tidak segera dibangun, Bali akan tetap menjadi pulau dengan banyak profesor, tapi sedikit arah. Dan di atas segala kemegahan akademiknya, keheningan intelektual itulah yang paling menyedihkan.
toto slot toto slot toto slot cerutu4d situs toto situs toto cerutu4d cerutu4d cerutu4d slot resmi cerutu4d