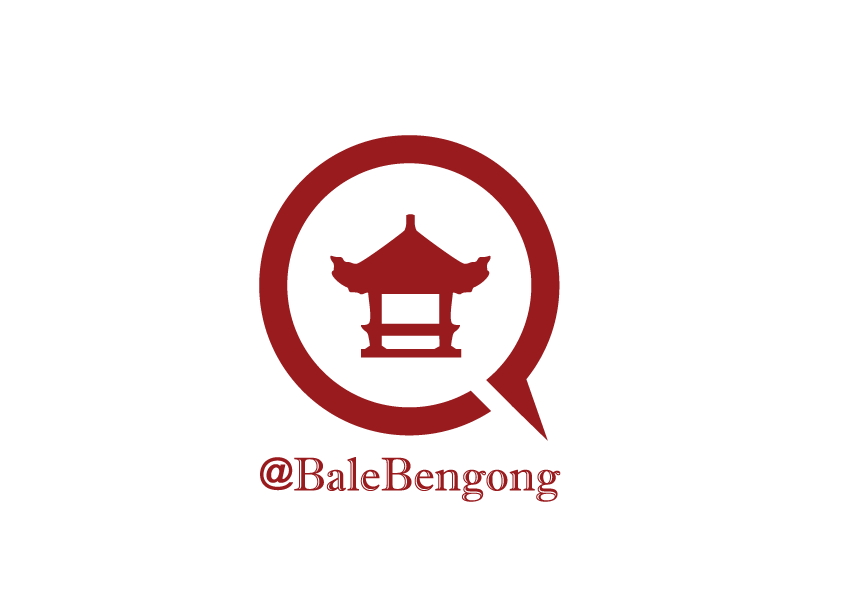Tanggal 29 Januari, ditetapkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, sebagai Hari Arak Bali. Hari Arak ini disambut gembira oleh beberapa kalangan. Para akademisi dan budayawan memujinya sebagai langkah untuk melestarikan kebudayaan Bali. Walaupun sesungguhnya tidak terlalu jelas apa yang hendak dilestarikan.
Arak adalah bagian dari ritual keagamaan di Bali. Selain itu, ia adalah bagian dari gaya hidup lelaki Bali. Arak sangat maskulin. Ketika saya masih kecil, hampir tidak pernah saya melihat perempuan menikmati Arak atau tuak.
Sebagai keturunan orang yang berprofesi sebagai penjual Arak dan tuak, saya berefleksi: mengapa penguasa Bali ini perlu menetapkan hari arak untuk Bali? Ini untuk apa?
Sebagian besar penguasa Bali dalam benaknya selalu ingin menjual Bali. Yang pertama-tama dilakukan adalah bagaimana mengemas Bali sebagai barang dagangan. Semua dibungkus dengan keeleganan semantik — seperti “Pariwisata Kebudayaan.” Yang tidak jelas disini apakah pariwisatanya yang harus berbudaya; ataukah kebudayaan yang dipariwisatakan.
Para penguasa Bali jelas harus menjadi gedibal-gedibal dari para priyayi penguasa Jakarta. Mereka melayani para tuannya di Jakarta dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah dengan memodifikasi apa saja yang Bali menjadi seturut selera dan kemauan Jakarta.
Dalam hal pariwisata, sangat jelas bahwa kebudayaan adalah abdi pariwisata. Dan, kebudayaan adalah semua aspek hidup orang Bali. Termasuk bagaimana mereka melakukan ritual, bagaimana mereka bermasyarakat, bagaimana mereka menjadi dirinya sendiri.
Kemana pun saya pergi, selalu ada pertanyaan apakah saya bisa menari? Apakah saya bisa menabuh gamelan? Seringkali saya jawab dengan nada marah, “What the fuck are you thinking about a Balinese?”
Orang Bali jelas tidak boleh menjadi intelektual, tidak boleh menjadi akademisi, tidak boleh menjadi pemikir kritis. Mereka yang menjadi orang–orang dengan karakter itu harus keluar dari Bali. Mereka harus melakukannya dari luar Bali. Mereka yang di Bali harus tetap domesticated dan neutered semata-mata sebagai insan abdi pariwisata.
Dan merekalah yang paling berbusa-busa mulutnya berbicara bagaimana pariwisata kebudayaan itu harus dilakukan — dengan mengutip jargon-jargon tradisi, yang para pekak dan dadong saya pasti akan bengong kalau ditanyai artinya. Yang paling menyedihkan dari Bali adalah hilangnya tradisi intelektual itu. Semakin banyak jargon digali dan ditemukan hanya menjustifikasi pariwisata. Hilang sudah sikap yang dirumuskan oleh Ida Pedanda Made Sidemen dengan, “tong ngelah karang sawah, karang awake tandurin” (kalau tidak punya tanah sawah, tanah badan (dan pikiran) inilah yang harus ditanami). Saya menafsirkan ini sebagai usaha untuk menanami jiwa dengan pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaan yang membuahkan kebaikan untuk diri sendiri dan masyarakat.
Ironi inilah yang saya tangkap dari keputusan Koster (lewat peraturan gubernurnya itu) untuk menjadi hari arak. Hari yang sebenarnya tidak perlu tapi penting untuk kekuasaan sang Gubernur sendiri.
Sejak berkuasanya Koster berusaha menjadi politisi populis. Dia dengan pintar menggunakan jargon indigenous people untuk mentransformasikan Majelis Desa Adat. Dibawah kepemimpinannya dibuat Perda tentang Desa Adat. Dia seolah-olah memberikan apa yang diinginkan orang Bali; meneriakkan apa yang ingin didengar oleh orang Bali; memuaskan apa yang ingin dinikmati oleh orang Bali.
Populisme Koster, delivered. Maksud saya, populisme ini memberikan hasil sangat baik untuk para priyayi Jakarta. Suara PDIP menjadi 54,3% di Bali. Dan Jokowi menang dengan mayoritas mutlak 92% di Bali. Delivered.
Koster juga merangkul semua seniman dan budayawan. Pandemi juga memberikan keuntungan ditengah-tengah cekikan ekonomi yang menimpa golongan ini. Seperrti di banyak tempat di negeri ini, di kala Pandemi, “semua seniman, budayawan, intelektual, dan kaum kritis lainnya dipelihara oleh negara; dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan penguasa.” Inipun, delivered.
Disinilah dalam pandangan saya letak Arak dalam politik semantik sang Gubernur Bali ini. Seperti Tuak, Arak adalah minuman biasa yang sangat humble di kalangan masyarakat Bali. Dulu ia berfungsi sebagai alat sosial. Orang minum di kalangan, kadang dengan “megecel” ayam aduan atau mekekawin. Itulah yang saya alami pada masa kecil saya.
Di masa Koster, Arak dipolitisasi dengan identitas kebalian. Ia dijadikan elegan. Ia diapropriasi menjadi bagian dari pariwisata kebudayaan atau abdi pariwisata. Sekaligus, pada saat bersamaan, Arak dirampas dari konsumennya yang paling setia yaitu rakyat kebanyakan.
Langkah Koster ini tidak berbeda dengan penguasa wilayah lain, yaitu Sulawesi Utara yang menjadikan Cap Tikus sebagai minuman fancy dan mahal. Atau NTT yang menjadikan Sofi sebagai setara whiskey yang dijual ratusan ribu per botol. Rakyat kebanyakan? Minumlah air. Itu lebih sehat, kata para elit itu.
Beberapa waktu saya berdiskusi sangat dalam dengan seorang kawan tentang mengapa anak-anak jalanan yang banyak di Jawa tahun 80-90an menghilang dari jalanan? Argumen dia sederhana. Ini karena menguatnya jaminan sosial dari negara terhadap penduduk-penduduk miskin. Banyak keluarga memang tetap miskin tapi mereka tidak rentan sehingga anak-anak mereka tidak terlempar ke jalan.
Argumen dia itu saya beri counter-factual dengan kasus Bali. Di Bali, sangat mudah kita jumpai anak-anak mengemis. Sangat mudah. Mengapa dia bisa demikian?
Kami tidak bisa menemukan jawaban langsung. Dia menyebut satu studi tentang Sumba. Di sana, pada wakto Orde Baru, pemerintah mendorong penguatan klan-klan sosial. Upacara-upacara menjadi jauh lebih megah — demikian pula pengeluaran ekonominya. Perumitan ritual, tradisi, dan kebudayaan ini ongkos ekonominya sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan tingginya human trafficking dan orang-orang mencari kerja kasar keluar daerah sekalipun menghadapi iklim yang sangat abusive.
Penjelasan ini mengembalikan pertanyaan saya kepada Bali. Inikah yang menyebabkan banyaknya anak-anak Bali terlempar ke jalanan? Kemarin saya terbengong-bengong ketika diberitahu ada penjor seharga 15 juta. Dan berapa juta diperlukan membangun ogoh-ogoh yang hanya keluar semalam itu?
Kejelian dari para politisi ini adalah seolah-olah mereka mengangkat identitas dan kebudayaan masyarakat mereka. Dan masyarakat pun menerimanya dengan gembira dan bahagia. Yang tidak mereka sadari adalah mereka harus menanggung ongkosnya. Merekalah yang menanggung bebannya. Dan politisi serta penguasa itulah yang meraup hasilnya, melapor ke Jakarta: Siap, boss! Kita berhasil …
Kalau Anda ingin melihat bagaimana populisme itu bekerja, perhatikan baik-baik hal–hal seperti ini. Kadangkala, apa yang Anda rasakan baik itu sesungguhnya sebuah jerat dan sekali Anda masuk ke dalamnya, sangat sulit bagi Anda untuk keluar.
Permainan Koster lewat hari Arak ini adalah contoh yang paling baik bagaimana populisme itu bekerja dan membakar lehermu. Bukan karena arak api. Tapi karena beaya sosial, ekonomi, dan politik yang harus kamu tanggung. Dan ini tidak berlaku untuk Bali saja. Ia berkembang di tempat lain. Juga di politik nasional.