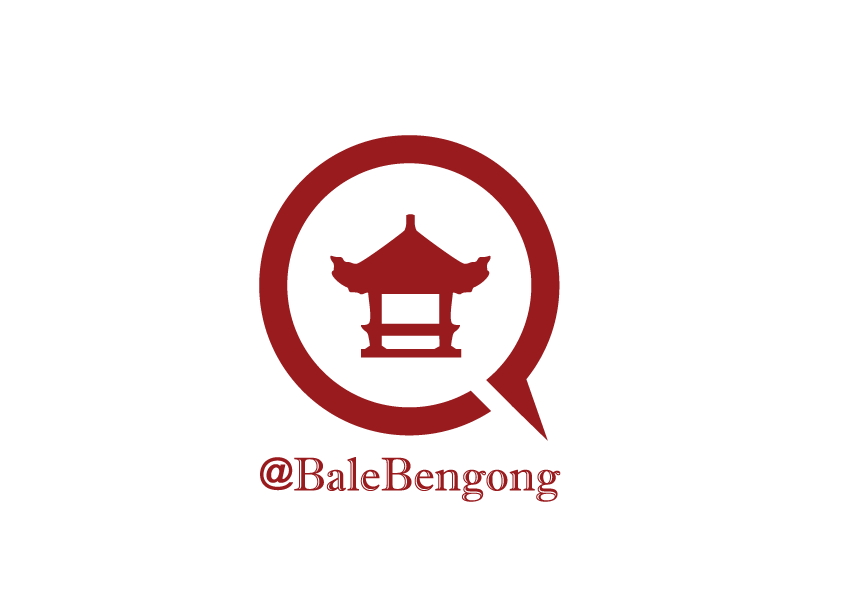I Ngurah Suryawan

Sumber: @frontpemudarevolusioner (https://www.instagram.com/p/DQCCUH1iWUl/?img_index=1)
Bunga dan Tembok
oleh – Wiji Thukul
Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak
Kau kehendaki tumbuh
Engkau lebih suka membangun
Rumah dan merampas tanah seumpama bunga
Kami adalah bunga yang tak
Kau kehendaki adanya
Engkau lebih suka membangun
Jalan raya dan pagar besi
Seumpama bunga
Kami adalah bunga yang
Dirontokkan di bumi kami sendiri
Jika kami bunga
Engkau adalah tembok
Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!
Dalam keyakinan kami
Di manapun-tirani harus tumbang!
Solo, 1987-1988
Mengenang berpulangnya Timothy Anugerah Saputra (22 tahun), mahasiswa FISIP Universitas Udayana (Unud), saya teringat puisi “Bunga dan Tembok” karya Widji Thukul (1987-1988). Puisi ini selalu terngiang sekaligus saya rasakan pada saat zaman mahasiswa di Unud tahun 1990 – 2000-an. Kata-kata yang membawa saya mengartikan pentingnya idealisme mahasiswa dalam arti seluas-luasnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berpikir merdeka dan menyerap berbagai pengetahuan untuk memperluas wawasan dan cara berpikir. Menyerap, menelaah, mengolah, dan mengartikulasikan dalam bahasa sendiri dan pilihan (karakteristik) ekspresi masing-masing adalah salah satu masa pembelajaran paling berharga yang saya rasakan dalam kehidupan ini.
Cara memperoleh pengetahuan ini berjalan beriringan dengan praksis dalam menunjukkan eksistensi diri di organisasi kemahasiswaan, yang di Unud kini pilihannya bagi saya cukup mewah. Pilihan boleh mewah tapi saya tidak mengetahui lebih dalam kiprah dan eksistensi mereka, terutama keberaniannya dalam memperjuangkan idealisme mahasiswa yang melawan otoritarianisme di lingkungan kampus maupun karena intervensi kebebasan akademik dari pihak luar kampus.
Puisi menyentuh “Bunga dan Tembok”, bagi saya jauh lebih mendalam untuk “memerdekakan” mahasiswa dari cara mereka memaknai diri menjadi mahasiswa dan cara berpikir mereka dalam merespon (menanggapi) berbagai situasi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Bagi saya, “Tembok” itu adalah personifikasi dari “kekuasaan”, baik itu kekuasaan di dalam dan luar kampus, maupun di internal organisasi kemahasiswaan. Yang tidak kalah pentingnya, “Tembok” tersebut adalah sesat berpikir mahasiswa yang dengan kekuasaannya menindas sesama manusia, atau mem-bully dan berperilaku rasis. Begitulah pelik dan fluid (cair-nya) kekuasaan yang bisa menjangkiti kita.
Tembok kekuasaan tersebut ada di sekitar kita dan tidak ada yang bisa steril darinya. Tidak terkecuali di dunia pendidikan dan akumulasi pengetahuan. Implikasi paling serius dari kekuasaan yang merasuk halus tanpa disadari ini adalah “membunuh” imajinasi dan “menyeragamkan” cara berpikir yang dianggap benar dan berkuasa. Tidak mudah untuk memperjuangkan pemikiran alternatif atau yang berlawanan dari arus utama dan kekuasaan. Itulah mengapa kekuasaan yang paling produktif sekaligus kuat mencengkram adalah yang merambah halus. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan yang “membunuh” anak-anak muda untuk berpikir kritis dan melawan praktik mikro kekuasaan di lingkungan (internal kampus) mereka.
Tapi semakin kekuasaan mencengkram, semakin laten sekaligus tersemai konsolidasi perlawanan terhadapnya. Seperti petikan puisi Wiji Thukul bahwa generasi yang tidak dikehendaki oleh kekuasaan akan membangun jejaringnya, mencari jalan untuk melawan, dan sudah tentu mengeskpresikan eksistensi mereka. Mereka ini, yang terhempas oleh kekuasaan yang represif dan “dikalahkan” oleh sistem yang korup dan diskrimiantif, perlahan namun pasti menyebarkan gagasan, silang pengetahuan, dan ide-ide gerakan untuk melawan penindasan.
Seperti kata Wiji Thukul lagi:
“…Tapi di tubuh tembok itu
Telah kami sebar biji-biji
Suatu saat kami akan tumbuh bersama
Dengan keyakinan: engkau harus hancur!”
Generasi di masa kebusukan kapitalisme
Gugurnya Timothy menghentak kita akan situasi pendidikan tinggi yang sejatinya tidak baik-baik saja. Hiruk-pikuk universitas saling berlomba meraih penghargaan terbaik dan menjadi kampus internasional, namun justru satu hal penting yang tertinggal: relasi (lingkungan akademik) yang humanis dalam pendidikan. Investigasi sedang berlangsung tentang latar belakang dan motif terjatuhnya Timothy dari Lantai 4 Gedung FISIP Unud. Kita menunggu hasilnya. Tapi terlepas dari apapun hasilnya, perundungan pasca meninggalnya Timothy sangat menyesakkan sekaligus sangat memprihatinkan. Ada persoalan sangat penting yang “hilang” dalam dunia pendidikan tinggi kita: martabat kemanusiaan peserta didik.
Pihak Unud kelabakan dan mengklarifikasi berbagai hal. Dari soal simpang siur CCTV dan lantai lokasi kejadian membuat kita juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dari saling bertolak-belakangnya fakta yang diungkapkan oleh pihak universitas dan kepolisian. Unud juga buru-buru mengklaim bahwa tragedi Timothy bukan disebabkan karena perundungan. Pada sisi yang lain, perundungan pasca tragedi mengundang kontroversi lemahnya hukuman terhadap para pelaku perundungan. Kita wajib melindungi pelaku perundungan agar tidak terjadi perundungan baru. Tapi kita juga tidak serta-merta menafikkan ada sesuatu hal mendasar yang telah terjadi secara struktural dan nilai dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi (Unud).
Secara struktural sudah tentu adalah persoalan kekuasaan dan kritik terhadapnya yang selalu akan terus membayangi Unud. Persoalannya adalah apakah orang-orang dalam struktur kekuasaan tersebut berani bersuara atau bungkam (cari aman) seribu bahasa demi kedudukan dan posisi (jabatan) mereka. Tapi ada hal lain yang saya perhatikan adalah berkaitan dengan konteks yang lebih luas yaitu keberanian untuk mempertanyakan bahkan menggugat situasi yang oleh banyak orang dianggap biasa atau baik-baik saja.
Satu obituari tentang Timothy yang menggugah menuliskan bahwa generasi sekarang lahir di masa kebusukan kapitalisme. Satu masa yang mengganggap keadilan sosial adalah sumir dan manusia adalah “modal” yang bisa dieksploitasi. Pada masa kebusukan kapitalisme ini, nilai-nilai kemanusiaan hanya dianggap sebagai ornemen pemanis untuk berjalan muluskan akumulasi kapital di berbagai sendi kehidupan manusia. Salah satu yang paling massif dan menggurita adalah dalam bidang pendidikan tinggi.
Pada situasi inilah Timothy bersama dengan generasi muda lainnya yang sepemikiran dengannya sedang mencari gagasan revolusioner yang mampu membuka jalan keluar dari kebuntuan kapitalisme. Seperti kutipan menghentak Timothy yang sering kita lihat di sosial media, “Militerisme itu sebuah tumor. Tetapi, penyakitnya sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme.” 1
Tidak banyak tentu anak-anak muda di universitas menempuh jalan mempertanyakan dunia mereka di kampus dan juga keseharian yang dialami oleh rakyat jelata. Inisiatif mempertanyakan situasi yang terjadi saat ini menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sungguh bernilai artinya di republik ini. Biasanya yang menyibukkan generasi mahasiswa dan tenaga kerja adalah hal ikhwal bersaing menjadi tenaga kerja yang produktif dan kompetitif di sirkuit kapitalisme, saat bekerja sepenuh hati dan tidak bertanya macam-macam (baca: tidak berpikir) menjadi nilai luhur tertinggi.

Melawan Budaya Bisu
Masa kebusukan kapitalisme semakin parah saat budaya bisu di kalangan akademisi, birokrat kampus, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat menjadi kronis. Semuanya bungkam. Ruang pendidikan di universitas menjadi hal yang sangat penting untuk menggambarkan apakah proses pendidikan menghasilkan “manusia yang merdeka” atau “manusia yang bisu” tidak bisa bersuara karena dibungkam oleh lingkungan yang menindasnya.
Bahasa, daya manusia untuk mengartikan dunia, mengartikan relasi sosial, mendirikan logos, membangun pengetahuan, hanya datang dari atas(an). Semuanya menjadi satu saluran, tidak beragam. Semuanya terpusat. Yang ada sebelum peradaban/pengetahuan datang hanya bunyi tanpa arti, tanpa daya membangun apa pun. Kebebasan untuk mengartikan dunia direnggut. Bagi Fraire (2005; 2018), pemangkasan kebebasan inilah yang menjadi salah satu ciri pendidikan yang menindas.
Kebisuan di tengah-tengah kebisingan kata milik kepentingan di luar pengalaman realitas komunitas dan diri sendiri: inilah kebisuan hakiki. Dan kebisuan hakiki ini mematahkan hak dan daya untuk mendefinisikan dunia, mematahkan hak dan daya untuk membangun pengetahuan yang bukan sekadar informasi dalam arti fungsional atau instrumental. Sistem pendidikan di Indonesia hingga kini masih menjadi matarantai pembisuan dengan sistem pendidikan yang amburadul (Tiwon, 2021: 184).
Pemerintah berulang kali menggulirkan strategi strategi baru untuk perbaikan pendidikan, dengan merujuk kepada cita-cita percerdasan kehidupan berbangsa sebagai tujuannya. Berbagai jargon seperti direproduksi seperti “Kampus Merdeka” dan kini “Kampus Berdampak”. Jika kita lebih mendalam, logika berpikirnya adalah menjadikan pendidikan sekadar cara untuk mencapai target ekonomistik. Salah satu contohnya semisal “berdaya saing” (atau “kompetitif”) untuk menggambarkan manusia yang berubah menjadi “sumberdaya” (resources) untuk didayagunakan demi memantapkan pembangunan nasional. Target tersebut memang dibungkus dengan rangkaian panjang frasa muluk seperti “memajukan kebudayaan nasional”, membentuk “ahlak mulia”, “bermoral”, “beretika”, “berbudaya”, dan “beradab”. Sejatinya inilah cara pandang yang menjadikan pendidikan sangat instrumentalis yaitu sebagai mesin pencetak sumberdaya yang bermanfaat untuk pola pembangunan yang bersandar pada rezim “pasar bebas”, rejim yang sungguh tidak membebaskan (Tiwon, 2021: 185).
Tragedi Timothy mendidik kita untuk merefleksikan secara lebih mendalam berjalannya proses pendidikan di perguruan tinggi berisiko berhenti dalam jebakan hanya menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pertumbuhan ekonomi semata. Hal yang jauh lebih penting yaitu pengembangan martabat manusia disingkirkan. Pada titik inilah sebenarnya pendidikan humaniora sejatinya secara spesifik mengarahkan kita kepada usaha-usaha pengembangan manusia ke arah sasaran-sasaran yang lebih substansial, halus penuh apresiasi dan empati pada hidup manusia itu sendiri daripada ke arah hidup material yang praktis.
Ironisnya, dalam dunia yang dipenuhi dengan jargon-jargon pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus memacu dirinya, konflik internal dalam dunia pendidikan berjalan tidak seimbang. Kepentingan untuk melayani pasar, kekuasaan, dan globalisasi cenderung menunda bahkan mengabaikan pentingnya pendidikan yang membimbing manusia berkembang ke arah hidup yang lebih bermartabat secara utuh.
Pada masa kebusukan kapitalisme ini, menggugat proses pendidikan dianggap mubazir karena lebih penting untuk memacu diri memikirkan bagaimana agar pendidikan bisa melayani pasar kapital. Hakekat pendidikan mendasar yang menyentuh revolusi kesadaran historis manusia akan hakekat hidupnya menjadi terabaikan, bahkan terdengarpun menjadi sangat sumir. Eksistensi manusia terbentang antara masa lampau dan masa depan. Dengan demikian pendidikan itu arahnya tidak hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pada usaha pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya.
Pada akhirnya kita mesti bertanya pada diri kita masing-masing. Sebegitu panjangnya kita memperoleh pendidikan, bahkan dengan gelar berderet-deret dan penghargaan. Lalu, mengapa kita harus bisu menyaksikan penindasan dan ketidakadilan di sekitar kita?
DAFTAR PUSTAKA
Freire, P. (2018). Pedagogy of the oppressed. USA: Bloomsbury publishing
Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed. USA: Continuum.
Tiwon, S. (2021). “Sekolah Memecah Budaya Bisu” dalam Toto Rahardjo, Sekolah Biasa Saja. Yogyakarta: Insist.
1 Lihat: https://revolusioner.org/kamerad-timothy-hidup-singkat-cita-citanya-abadi/ (diakses 28 Oktober 2025).
situs gacor cerutu4d toto togel toto togel