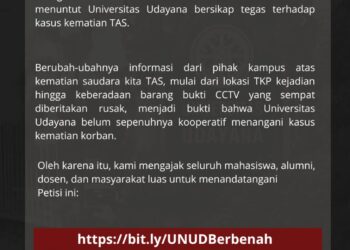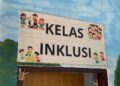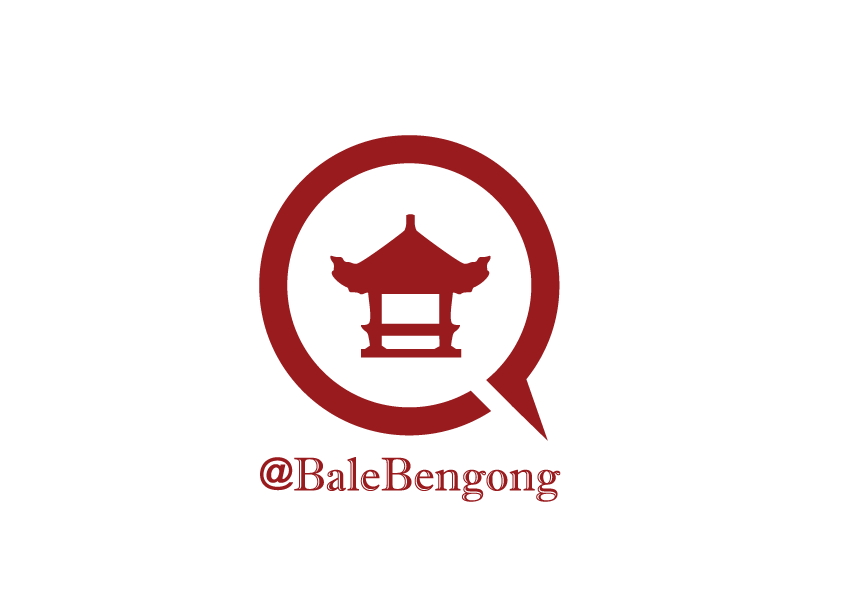Oleh Komang Ari, Juniantari, Osila — Semarapura


Foto: Potret Patung Kanda Pat Sari (Kiri) dan Monumen Ida Dewa Agung Jambe (Kanan) yang terletak di jantung Kota Semarapura
Siapa yang pernah jalan-jalan ke Klungkung? Dari Denpasar, setidaknya kita perlu melintas sejauh 31 kilometer atau nyaris satu jam untuk sampai di gumi serombotan ini. Terdiri atas empat kecamatan yang mencakup wilayah daratan dan lautan, Klungkung dikenal kaya akan potensi lokal, mulai dari kekayaan bahari hingga kebudayaan yang khas. “Ber jeg aeng liune!” Demikian kira-kira untuk mewakili isi hati orang Klungkung. Lantas, seperti apa potret lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di kabupaten yang dihuni lebih dari dua ratus ribu jiwa ini?
Di balik ‘ketog semprong’ ke kapal pesiar
Kapal pesiar menjadi salah satu pekerjaan di sektor pariwisata yang masih digandrungi anak muda Klungkung. Dilansir dari data milik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2024, Bali menyumbang 8.143 Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Klungkung menyumbang 627 jiwa dari total 9.360 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdaftar yang berasal dari Bali. Angka ini menempatkan Bali di posisi ketujuh secara nasional sebagai provinsi pengirim pekerja migran terbanyak, dari total populasi usia kerja Bali yang mencapai 2.665.420.
Di serpihan Kota Semarapura, Desa Gelgel yang menjadi sentra pengerajin kain tradisional menjadi salah satu daerah terbanyak asal PMI yang bekerja ke kapal pesiar. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Kantor Perbekel Desa Gelgel, ada 146 PMI dari wilayah ini bekerja ke kapal pesiar. Lagi-lagi mungkin akan terlintas pertanyaan, ‘mengapa kapal pesiar masih menjadi tujuan bekerja favorit bagi banyak anak muda di Klungkung?’.

Penuturan Agus Wedayana (25), pemuda asal Gelgel, ia memantapkan diri bekerja ke kapal pesiar untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Selain itu, persiapan waktu studinya pun tergolong singkat. Hal ini dinilai menjadi keuntungan tersendiri bagi anak muda yang ingin segera bekerja. “Ya, kalau di sektor pariwisata kan cepat sama nggak perlu lama-lama 1 sampai 2 tahun (sudah bisa berangkat ke kapal pesiar),” ucapnya.
Pria yang karib disapa Bobo ini mengungkap, bekerja di kapal pesiar adalah jawaban ideal untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Dalam sebulan, upah pokok yang diterima Bobo sebagai waiters assistant atau asisten pramusaji berkisar antara 100 Dolar AS setiap bulannya dengan rincian bekerja selama delapan jam per hari, atau paling banter 12 jam (tentunya dengan konsekuensi perusahaan membayar lebih).
Meski dengan catatan, gaji pokok yang diterima awak kapal pesiar berbeda-beda, tergantung posisi dan perusahaan tempat mereka bekerja. Syukur jika mujur, jumlah tipping yang diterimanya mampu menjadi penghasilan tambahan. Hal ini biasanya digunakan Bobo untuk membiayainya kebutuhan sehari-hari, hingga sekadar nongkrong saat kapal bersandar. “Kalau lagi keluar beli Wi-Fi, terus beli makan nggak pernah pakai uang gaji, selalu dari tipping,” kata dia. Dengan demikian, ia bisa menyimpan keseluruhan gaji untuk keperluan lain, termasuk untuk kebutuhan keluarga di rumah.
Hal ini dibenarkan oleh Penggagas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Glory Klungkung, I Nengah Budiarta. Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa banyak anak muda tertarik bekerja di kapal pesiar. Pertama, tidak dibutuhkan latar belakang pendidikan khusus; lulusan SMA/K atau sederajat dapat langsung melamar setelah menjalani pelatihan. Kedua, anak muda umumnya belum terikat kewajiban adat, sehingga usia ini menjadi momen yang tepat untuk mencari pengalaman di luar negeri. Selain itu, bekerja di kapal pesiar memungkinkan mereka secara otomatis berkeliling dunia. Terakhir, upah yang ditawarkan jauh lebih layak dibandingkan pekerjaan lain yang tersedia di daerah.
Senada dengan itu, I Komang Ary Wirawan seorang pria paruh baya asal Banjar Tangkas, Gelgel, juga punya alasan serupa; berangkat ke kapal pesiar demi memperbaiki perekonomian keluarga. Namun, ia tidak menampik ada sejumlah tantangan yang dirasakan selama bekerja di kapal pesiar.
“Fisik dan mental to harus kuat, raga ba merasakan, yen sing karena dukungan orang tua, dukungan kurenan, pidan be mulih. karena kurenane ngoraang, nah jalanin gen, bersyukurlah karena ada dukungan orang tua masih. Kebanyakan anak ane suud megae di kapal karena sing ada dukungan,” beber Ary.
(Fisik dan mental itu harus kuat, saya sudah merasakan. Kalau bukan karena dukungan orang tua dan istri, saya sudah pulang, karena istri saya bilang ‘ya jalanin aja’. Bersyukur karena ada dukungan orang tua juga. Kebanyakan orang yang berhenti bekerja di kapal pesiar karena tidak ada dukungan).

Menyusuri lautan sejak 2009, membuat Ary paham betul bahwa bekerja ke luar negeri, di kapal pesiar tak lantas menawarkannya kenyamanan. Ada konsekuensi yang harus dibayar di balik kesan ‘wah’ yang menggeliat di permukaan, entah itu tekanan kerja, berjarak dengan keluarga, atau semata merelakan waktu tidur. Baginya, menjadi awak kapal adalah pilihan terakhir untuk lari dari pekerjaan tidak tetap (daily worker) dengan gempuran upah yang jauh dari kata memadai. Kendati demikian, Ary sebenarnya berkeinginan untuk bekerja di kampung halamannya. Bukan tanpa alasan bagi pria yang akrab dengan dolar ini melontarkan hal itu, baginya kesempatan bekerja di dekat keluarga jauh lebih berharga. “Yen maan limang juta gen, tapi sing misi kos artine paek-paek dini. Keluarga tepuk,” ungkapnya.
(Kalau dapat gaji Rp5 juta saja, tapi tidak ngekos, artinya biar dekat dengan keluarga).
Selain itu, bekerja di kapal pesiar, juga dinilai rentan akan risiko pemulangan. Jika terindikasi sakit, misalnya, pemulangan dapat menghampiri pekerja. Bahkan, sambung Ary, selama di kapal pesiar tak ada waktu untuk cuti.
“Jam kerja mekelo, istirahat akejep maan. Tergantung bos, kadang maan libur, kadang sing. Kadang libur 2 jam, to sebenehne sing libur, istirahat. Yen ditu dua jam nak libur kone adane. Makane jani liunan anake ke darat. Yen di konten to ane luung-luung dogen,” tuturnya.
(Jam kerjanya lama, istirahatnya cuma sebentar. Tergantung bos, kadang dapat libur, kadang nggak. Kadang dapat libur 2 jam. Itu sebenarnya bukan libur, (tapi) cuma istirahat. Kalau di sana dua jam itu dihitung libur. Makanya sekarang lebih banyak yang ke darat. Kalau konten di media sosial itu yang diperlihatkan yang bagus-bagus aja).
Bobo dan Ari merupakan lukisan hidup untuk menggambarkan kisah serta keluh kesah nak Bali yang bekerja di luar negeri. Mengisyaratkan alarm, ada persoalan mendesak yang harus direspons semua pihak; lapangan pekerjaan, kelayakan upah, peran pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lagi catatan.
Mengenal kain tradisional di Desa Adat Gelgel
Mari beranjak sejenak dari kisah Ary, Bobo, dan kapal pesiar. Sebagai kabupaten yang lekat dengan nilai-nilai historis peradaban Bali, Klungkung sejatinya tidak hanya kaya akan warisan budaya tetapi juga menghadapi dinamika sosio-ekonomi yang kompleks. Terutama dalam konteks Bali sebagai destinasi pariwisata global yang kaya akan potensi kebudayaan. Di desa kelahiran Ary dan Bobo, ada beberapa industri kain tradisional yang masih berkembang.

Keberadaan kain tenun tradisional, dalam hal ini adalah songket, tak lepas dari kaitannya dengan sejarah pusat kerajaan di Gelgel pada masanya. I Gede Eka Sumaya Putra, seorang Jero Mangku (pemuka agama) di Desa Adat Gelgel, menceritakan pada masa Kerajaan Gelgel pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Saat itu masa kepemimpinan Ida Dalem Bekung dan Dalem Sagening, para penenun di Gelgel itu adalah para penenun yang membuat produk kain songket untuk keperluan para bangsawan puri dan upacara yadnya.
Menurut Jero Mangku Eka, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) baru ada tahun 90-an. Sebelumnya yang ada hanya tenun tradisional, perajin memproses kain dengan cara duduk dan bagian alat tenun melingkari badan penenun. Cagcag, namanya. Konon nama ini diambil dari bunyi belidanya.
“Bangkiang bajang-bajang nak Gelgel ipidan rengkiang karena ditarik sama tenun cagcag,” kenangnya.
(Pinggang gadis asal Gelgel dulu langsing karena ditarik tenun cagcag).

Jero Mangku Eka menuturkan, dulu belida penenun di Gelgel sangat halus, tujuannya agar benang tidak tersangkut. Ini menandakan, para perajin kain tradisional di Gelgel sangat aktif menggunakan alat tempurnya (alat tenun).
“Kemudian kenapa saya bilang tenun itu sudah ada dari zaman kerajaan, karena ketika zaman perang Puputan Klungkung para istri menggunakan belida sebagai senjata, bukan bambu runcing. Alat tenun itu yang digunakan sebagai senjata melawan Belanda, sehingga ada mitos belida dipakai memukul celuluk,” ujarnya sembari tertawa.
Saking fasihnya dengan aktivitas menenun di era 80-an, ia mengaku bisa menebak siapa perajinnya hanya dari irama alat tenunnya. “Asal sube kene munyi tenunne, artine i anu nenun (kalau sudah begini suara tenunnya, artinya si ini yang menenun). Suaranya keluar dari kerorogan bambu. Bunyi sentuhan antara belida yang dilempar ke samping setiap jam 8 malam itu,” katanya.
Tenun tradisional sudah ada sebelum ATBM. Tanda tenun cagcag semuanya menggunakan alat tradisional. Dulu kelemahannya alat tenun tradisional ini sangat terbatas. Dalam tenun cagcag ada istilah nyuntik benang. Sebuah tahapan untuk membuat desain motif di benang.
Uniknya, dalam satu suntikan hanya untuk satu ukuran kamen saja. Setelah benangnya habis, artinya proses tenunnya sudah selesai. Kalau dibandingkan dengan ATBM hasil kainnya bisa lebih panjang. Tapi kualitas hasil tenun cagcag jauh lebih bagus dari ATBM.
Jero Mangku Eka bernostalgia dengan karya tenun Gelgel. Jika dulu dari melihat saja sudah diketahui kalau itu songket Gelgel karena dilihat dari keunikan desainnya. Desain songket Gelgel menurutnya juga mendapat pengaruh China. Secara motif desain itu diambil dari patra (sebuah pakem desain China). Ia memberikan percontohan lain motif songket Gelgel mendapatkan pengaruh China terlihat dari penggunaan benang emas.
Selain dari alat dan proses pembuatannya, karakter kain tradisional Gelgel ini juga terlihat dari motifnya. Sehingga pengembangan kreativitas motif dari tukang suntik benang (desainer motif kain) sangat mempengaruhi. Sayangnya, tukang suntik benang tradisional di Gelgel hingga kini tersisa dua orang saja. Tim mencoba untuk menemui kedua tukang suntik benang yang ada di Desa Gelgel, tapi kami mendapatkan kabar tukang suntik benang tenun yang lebih tua sudah meninggal. Sehingga sampai saat kami mencari data tukang suntik benang tenun di Gelgel kini tersisa satu orang saja.

Ia adalah I Gusti Putu Merti, seorang penenun di Dian’s Songket dari Desa Gelgel. Sejak kecil, Gusti Merti sudah berdampingan dengan aktivitas menenun. Terlebih orang tuanya adalah penenun. Ia mengakui desa kelahirannya memang merupakan sentra tenun. Tak perlu jauh belajar tenun, dengan mengamati dan menggunakan langsung alat tenun tradisional milik orangtuanya Gusti Merti mampu membuat kain selendang sejak kelas 3 SD.
Sebagai seorang pembuat desain motif di benang, Gusti Merti harus mampu menuangkan motif-motif gambar yang sudah ada di kain. Menurutnya itu sudah lebih mudah. Sebab, para pelanggannya kini lebih sering memesan motif kain hanya dengan memberikan salinan dalam kertas, yang tak banyak penyuntik benang bisa menuangkannya menjadi motif.
“Seperti ini (sembari menunjukkan kertas fotokopian motif) ada orderan dalam bentuk fotokopian. Bisa sih kita tuangkan ke dalam kain. Tapi ya memang tidak akan 100% mirip,” jelas Gusti Merti.
Menurut Gusti Merti, yang menjadi pembeda kain tradisional Klungkung dengan daerah lainnya adalah dari jenis bahan yang digunakan. Misalnya seperti di Sidemen, Karangasem kebanyakan menggunakan bahan katun dan rayon. Tapi di Klungkung sebagian besar menggunakan sutra alam.
“Kalau segi motif saya sering menggunakan gambar kedis (burung), naga, keker itu sudah bisa dibuat di mana pun. Kadang-kadang motif ini sudah banyak yang niru, kita buat motif baru, dengan memadukan antara motif satu dengan yang lainnya”.
Tantangan sebagai seorang suntik benang, menurut Gusti Merti terletak saat penyusunan benang yang banyak karena rentan putus. Terlebih lagi saat benangnya kusut dan ukurannya kurang sehingga harus menambahkan benang lagi. Jika ia membuat beberapa susunan benang lagi atau menggunakan benang sisa dan tipis itu justru akan lebih menyusahkan.
Kini ia sendiri sangat khawatir siapa yang akan meneruskan profesi tenun tanda pengenal Desa Gelgel ini. Setelah generasi Gusti Merti, ia belum menemukan generasi selanjutnya. Baik itu menjadi penenun ataupun tukang suntik benang (desainer motif kain tradisional).
“Setelah ini tidak ada generasi lagi, karena susah mencari regenerasi. Anak muda tidak ada yang mau meneruskan. Padahal kalau mau ke sini, saya mau mengajari secara gratis. Banyak anak muda duluan bilang (menenun) itu susah,” cerita Gusti Merti saat ditemui di Dian’s Songket.
Padahal, Gusti Merti melalui Dian’s Songket selalu saja ada pesanan yang harus dibuat. Terkadang ia merasa kewalahan. Terlebih saat menjelang hari raya dan banyak upacara seperti saat ini sampai September, Gusti Merti sudah mendapatkan pesanan penuh.
“Banyak yang order ada dari salon, DPR-DPR juga,” tambahnya.
Gusti Merti masih menaruh harapan agar ada generasi penerusnya di bidang menenun. Terlebih lagi ada regenerasi yang menekuni motif yang sudah ada di Gelgel agar tidak punah. Sebab ia kini merasakan nasib tradisi menenun di Desa Gelgel sudah mulai langka.
Perjuangan lain yang turut disumbangkan untuk menghidupkan kembali eksistensi pembuatan kain tradisional Gelgel juga dilakukan oleh pengelola Dian’s Songket, I Putu Agus Aksara. Sebagai anak muda Gelgel, Agus juga memiliki keinginan sama seperti pemuda lain di desanya untuk bekerja merantau ke luar desa. Namun terhalang izin dari orang tuanya, kini Agus justru menghidupkan kembali api menenun di Desa Gelgel yang sudah mulai temaram.
“Motivasi tiang karena usahanya sudah jalan, jadi tiang tinggal mempertahankan dan mengembangkan,” tutur Agus menyampaikan motivasinya meneruskan pekerjaan yang justru ditinggalkan teman sebayanya.
Sama seperti Gusti Merti, saking fasihnya melihat proses menenun setiap hari dari ibunya, Agus Aksara kepikiran untuk melanjutkan menjadi bisnis rumahan milik ibunya. Ibunya memulai bisnis sejak 2010, awalnya peran Agus hanya membantu. Namun, ia melihat peluang bisnis yang stabil di bidang kain tradisional, akhirnya tahun 2014 mulai fokus di mengembangkan Dian’s Songket.
“Selain memang nggak ada pekerjaan dulu, tiang dapat kerja di hotel, cuma harus memilih salah satu. Dulu di bagian front office. Dulu lebih banyak hasilnya di hotel cuma lambat laun lebih enak di sini, tiang buang yang di hotel. Kalau bukan tiang yang melanjutkan mungkin sudah mati usahanya,” tuntasnya.
Ia melihat saat itu para penenun yang turut bekerja dalam usaha ibunya masih banyak tapi umur 50-an tahun. Kalau sekarang rata-rata usianya 30-an tahun.
“Sekarang tiang challenge untuk regenerasi, memang susah sekali kalau dibandingkan Sidemen atau daerah lain,” Agus merenungkan tantangan bisnis tenun di Klungkung.
Ia menduga kesulitan regenerasi ini karena ada perbedaan mindset anak muda terhadap penghasilan menjadi penenun yang dianggap kecil. Bagi Agus, penghasilan menenun bisa di atas pekerjaan lain karena sistem kerjanya borongan. Ia mencontohkan penghasilan penenun di tempat usahanya paling kecil gajinya Rp3 juta dalam sekali pembuatan produk. Sedangkan tukang pembuat motif (suntik benang) mendapatkan gaji bulanan yang berbeda dan ada gaji harian lain.
Setali tiga uang dengan yang dirasakan pemilik Pertenunan Astiti I Nyoman Sudira di Gelgel. Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah berusia 73 tahun ini, sektor kain tradisional cenderung stabil mengingat kebutuhan pasar untuk produk ini selalu ada. “Kalau ATBM ini bagus sebenarnya penghasilannya, anggap bekerja 8 jam mereka dapat 5 meter ongkosnya Rp125 ribu per 8 jam. Marginnya tambah lagi 10-25 persen. Rata-rata kalau di pasar dapat jualan Rp1 juta per hari, per meternya kami hitung Rp130 ribu,” beber dia.
Fleksibilitas pekerjaan ini juga disoroti Nyoman Sudira. Menjadi seorang penenun bisa dikerjakan dari rumah atau bisa kolektif di lokasi industri. Dulu menenun di rumah masing-masing karena setiap rumah sudah memiliki alat tenun. Sekarang lebih banyak kolektif/berkelompok karena alat tenun sudah mulai langka di rumah. Bagi penenun yang sudah memiliki alat tenun di rumahnya, mereka akan menenun di rumahnya masing-masing. Namun, tetap mengerjakan orderan dari Dian’s Songket atau Pertenunan Astiti yang membuat pertenunan masih dilakoni ibu-ibu rumah tangga.
Stereotip pekerja kain tradisional
PMI yang bekerja ke kapal pesiar dengan krisis regenerasi kain tradisional di Desa Gelgel dianggap tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Hal ini terjadi lantaran masih ada stereotip di bidang pekerjaan; bahwa menenun adalah semata-mata ranah perempuan.
“Tidak ada hubunganya, kan yang banyak berangkat ke kapal itu laki-laki, sedangkan yang penenun kan perempuanya, jadi ya tidak ada hubungannya itu, berkurangnya penenun kalau menurut saya karena penjualan yang susah, dan bahan yang mulai mahal dan langka apalagi benang emas itu susah, mahal dan terbatas, meskipun belakangan ini sudah mulai ada yang mau membangkitkan budaya ini,” ucap Perbekel Desa Gelgel, I Wayan Sudiantara.
Namun demikian, pihaknya mengaku tengah berupaya melestarikan industri kain tradisional ini di Desa Gelgel. “Ya sedang kami upayakan, semoga ada dukungan dari semua pihak, kami ingin membuat sebuah workshop terkait tenun ini, jalan-jalan ke tempat workshop untuk melihat proses pembuatan tenun dari proses membuat motif, sampai menjadi produk songket,” tuturnya.
Meski sektor ini didominasi oleh pekerja perempuan, nyatanya banyak posisi penting juga diisi oleh laki-laki. Berdasarkan data teranyar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Klungkung, dari 15 unit usaha pertenunan yang tercatat, 9 di antaranya dikelola oleh laki-laki.
Salah satunya pemilik Pertenunan Astiti, I Nyoman Sudira, ia bekerja sebagai pengelola pertenunan sekaliber menanggungjawabi desain untuk setiap motif kain yang diproduksi. Selain dirinya, Sudira juga mempekerjakan beberapa pekerja laki-laki di pertenunan miliknya. Menurut Sudira, industri lokalan ini memiliki ‘PR’ untuk terus meregenerasi penerusnya kelak. Ia menambahkan, anak muda perlu difasilitasi dengan pendekatan yang sesuai untuk berminat pada kain tradisional.
“Saya kira begini, kita banyak cara untuk menarik mereka, pertama anak-anak sekolah diberikan stimulus mereka kita bayar. Biasanya anak-anak muda yang sudah menikah dia tidak dapat pekerjaan akan mau kesini sebab pekerjaan menenun tidak perlu tenaga yang besar, dan tempat kerjanya teduh tidak seperti di sawah. Kalau ATBM itu nggak sampai satu minggu udah bisa,” terangnya.


Foto: Pengelola Pertenunan Astiti, I Nyoman Sudira (kiri) bersama Putu Diana, anak muda yang bekerja sebagai tukang telos.
Ia tak menampik jika regulasi untuk mempertahankan keberadaan kain tradisional saat ini tengah giat diwacanakan. Namun, di sisi lain, pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran. Sehingga lazimnya yang mengikuti workshop pembuatan kain tradisional bisa dihitung jari.
“Sebenarnya pemerintah sudah luar biasa ya, sudah sering melakukan pelatihan nenun tapi yang dilatih orang-orang itu saja. Saya pernah mengusulkan supaya pendekatannya mulai dari tingkat SD. Orang Jepang pernah kesini, mereka sampai heran mengapa tidak ada sekolahnya (tenun). Di Jepang, sedikit yang bisa (nenun), tapi ada sekolahnya. Makanya di Jepang kan ada alat-alat tenun modern,” tambah dia.
Sementara itu, Tjokorda Istri Agung Wiradnyani selaku Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung mengakui peminat anak muda untuk meneruskan bidang pekerjaan menenun sangat kecil. Hal ini terbukti dari setiap programnya memberikan pelatihan di bidang menenun yang hadir paling banyak dari kalangan ibu rumah tangga. Bahkan nihil dari kalangan anak muda di bawah umur 25 tahun. Ia menilai paling tidak ada tiga anggapan yang muncul membuat stereotip pekerjaan menenun di kalangan anak muda. Pertama, pekerjaan ini tidak bergengsi, karena pekerjaan menenun dikerjakan di rumah.
“Jadi kan kerjanya dari rumah saja, nggak dapat keluar rumah. Istilah Balinya, sing maan mepayas gitu loh, artinya menenun di rumah dianggap tidak bergengsi,” tambah Tjok Wiradnyani.
Kedua, prosesnya juga cukup panjang, untuk menyelesaikan satu kain bisa berhari-hari. Anggapan ketiga dari penghasilannya yang belum menjanjikan. Untuk stereotip ketiga ini sebenarnya bisa dibantu atau di-support sama dinas. Dalam artian bisa diperbaiki misalnya secara penghasilan atau secara harga ada standar pengupahan, harap Tjok Wiradnyani.
Diskoperindag Klungkung melihat keberlanjutan masa depan hilirisasi kain tradisional Klungkung sangat stabil, karena memiliki pasar yang luas. Ia mencontohkan misalnya pada pemakaian kain itu sudah tidak menjadi hal yang premium. Boleh dikatakan kain tradisional sudah menjadi kebutuhan. Selain itu, hilirisasi kain tradisional sudah masuk ke dalam sistem. Sebab beberapa kebijakan mendukung pemanfaatan penduduk lokal, seperti menggunakan pakaian kerja berbahan endek dan batik tidak hanya ASN saja tapi seluruh lembaga yang ada di Klungkung.
“Saya pikir industri tenun di Klungkung bisa berkelanjutan, justru sampai kewalahan, karena banyak dikejar desainer dari luar sebab kualitasnya yang bagus,” katanya.
Selama dihimpun Diskoperindag, pendistribusian produk kain tradisional di Klungkung dipasarkan oleh seller. Ada juga yang mengambil langsung ke penenun atau industrinya, selain juga pasti dijual di pasar.
Perubahan dan adaptasi di kewajiban adat
Kehidupan masyarakat Bali umumnya tidak terlepas dari tatanan desa adat. Bendesa Adat Gelgel, Putu Arimbawa, mengakui adanya kekhawatiran terhadap menurunnya partisipasi anak muda dalam kegiatan adat, seiring dengan semakin banyaknya yang bekerja ke luar desa, termasuk ke kapal pesiar. Namun, di lain sisi, ia menilai rasa kepemilikan akan adat bagi PMI yang bekerja ke luar negeri justru meningkat. Arimbawa berasumsi, hal tersebut dapat terjadi karena mereka (para PMI) rindu akan kampung halamannya.
“Katakanlah di kapal pesiar, dari penuturan beberapa yang berangkat itu kan ada semacam pertunjukan kesenian Bali juga mereka tampilkan (di saat-saat tertentu). Dan itu diapresiasi di luar sehingga kecintaan mereka terhadap budaya Bali sebenarnya lebih kuat ketika mereka berada di luar negeri,” kata dia.
Berbeda dengan anak muda, warga yang telah menikah umumnya memiliki lebih banyak kewajiban adat, seperti ngayah (berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan) dan menyama braya (gotong royong). Bagi mereka yang tidak bisa hadir karena alasan pekerjaan, biasanya dikenai sistem melaga, yakni denda yang dibayarkan sebagai bentuk pengganti atas ketidakhadiran dalam kegiatan adat. Sistem ini dinilai menjadi solusi bagi warga yang merantau atau bekerja di luar desa. Ary menuturkan, dirinya dikenai sistem ini karena telah berkeluarga.
“Mayah per nem bulan Rp175 ribu. Ketika libur, tetap keluar menyama braya,” ujar dia.
(Bayar per enam bulan sekali Rp175 ribu. Ketika libur, tetap ke luar untuk mengikuti kegiatan adat).
Sementara itu, di bidang kesenian, Desa Adat Gelgel kini mendorong terbentuknya sekaa gong (kelompok pemusik tradisional) perempuan. Gagasan ini muncul karena banyak pemuda yang bekerja di kapal pesiar, sehingga jumlah laki-laki di desa menjadi terbatas. Menurut Arimbawa, langkah ini menjadi bukti bahwa berbagai perubahan dan adaptasi perlahan mulai terjadi di lingkungan desa adat seiring dengan banyaknya anak muda yang bekerja ke luar desa.
Dukungan Pertenunan Klungkung: Sudah Lesu, Dipangkas Pula
| Tahun | Jumlah Penenun di Klungkung | |
| Laki-laki | Perempuan | |
| 2015 | 24 | 1294 |
| 2016 | 0 | 60 |
| 2017 | 0 | 20 |
| 2018 | 0 | 58 |
| 2022 | 114 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
Saat itu (21 April 2025) tim mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung. Tak sengaja berbarengan dengan seorang perangkat desa dari salah satu desa di Kecamatan Dawan yang sedang mendaftarkan warga mudanya ke Disnaker Klungkung untuk ikut pelatihan menjadi calon PMI.
Program memberangkatkan KK miskin oleh Bupati Klungkung sudah tidak asing lagi bagi desa-desa di Klungkung. Program inovasi memberangkatkan anak dari KK miskin ke kapal pesiar ini sudah berjalan sejak 2019. Hal inilah yang turut memotivasi Disnaker mendorong hingga memfasilitasi anak muda Klungkung berangkat ke kapal pesiar. Tidak hanya pelatihan, tapi juga upaya pendanaan untuk keberangkatan.
“Anak-anak di sini difasilitasi, semua sudah kami biayai, ada beberapa dokumen ke kapal pesiar ini kita biayai. Yang tidak bisa kami biayai adalah paspor, medical check up dan visa. Jadi saat anak-anak Klungkung yang merupakan KK miskin lolos berangkat ke kapal pesiar akan dibantu LPD desa adat saat keberangkatannya,” kata Edy Santosa, Kabid Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi Disnaker Klungkung.
Menurut Edy, dari data yang dihimpun Disnaker Klungkung saat ini peminat yang mau berangkat ke kapal pesiar banyak sekali karena iming-iming gaji besar. Hal ini dibuktikan dari banyaknya warga Klungkung yang mengakses ID ke kapal pesiar.
Banyaknya minat anak muda Klungkung ini direspon dengan dukungan penuh oleh pemerintah. Melalui Disnaker, pemerintah menjangkau anak muda dengan bersurat ke desa-desa. Desa turut memfasilitasi dengan mengantar warganya mendaftarkan ke Disnaker yang ingin berangkat ke kapal pesiar.
Semua yang mendaftar akan diterima dulu di Disnaker. Kemudian datanya akan dibawa ke Dinas Sosial. Sebab hanya pemilik ID KKS yang terdaftar di Dinsos yang diseleksi. Meski sudah membuat surat keterangan miskin dari desa, itu tidak berlaku karena syarat mutlaknya memiliki ID KKS.
“Kuota pelatihannya tahun ini menurun menjadi 14 orang karena efisiensi anggaran. Sebelumnya dari 2019 ada 20 orang per tahun yang dibiayai untuk berangkat ke kapal pesiar,” tambah Edy.
Di tengah gempuran fasilitas pemerintah untuk mendukung keberangkatan ke kapal pesiar, lantas bagaimana dukungan di sektor pekerjaan lokal? Meski memiliki sejarah panjang di Klungkung, tapi dukungan sektor pertenunan jomplang.
Dalam waktu yang berbeda, kami menemui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung untuk mengetahui situasi dukungan untuk UMKM di Klungkung. Wayan Asin Yuliani, staf Bidang Perindustrian menyebutkan profesi menenun memang digeluti oleh para ibu rumah tangga yang sudah terbiasa menenun. Biasanya Diskoperindag memberikan pelatihan berkala dengan para penenun di Klungkung. Pelatihannya bertahap dan bersifat mendalami. Seperti yang baru beberapa waktu lalu berlangsung yaitu pelatihan mebed. Peserta cukup antusias yang mendaftar sekitar 20-an orang.
Pelatihan mebed ini merupakan agenda pertama yang baru berjalan di tahun ini. Setelah agenda pelatihan sebelumnya gagal akibat efisiensi anggaran. Tahun lalu, pihaknya mengajukan mengadakan pelatihan pewarnaan alami untuk dilaksanakan tahun ini. Tapi sayangnya, agenda pelatihan pewarnaan alami dibatalkan karena dipangkasnya anggaran kegiatan.
“Harusnya Maret 2025 ini dilaksanakan pelatihan cara pewarnaan alami dengan belajar metode dari Pejukutan, Nusa Penida. Pelatihan ini adalah usul permintaan dari ibu-ibu penenun yang sering ikut pelatihan, mereka sangat antusias untuk ikut. Tapi tidak bisa kami lakukan karena dikurangi semua anggarannya,” ungkap Yuli.
Menurut Yuli, pihaknya juga sangat terbatas untuk melakukan dukungan terhadap UMKM di Klungkung. Seperti di bidang pertenunan ini. Sebab Diskoperindag mempunyai wewenang sebatas pembinaan dan membantu memfasilitasi para penenun. Lebih banyak memfasilitasi dalam bentuk pameran. Jika ada yang memerlukan izin untuk sertifikat aplikasi kementerian perindustrian pihaknya juga bisa memfasilitasi.
“Cuma kita belum bisa memberian bantuan alat atau permodalan. Dari kita enggak ada penganggaran untuk pembantuan permodalan karena itu bisa jadi besar dananya (yang dianggarkan),” jelas Yuli.
Di tengah minimnya dukungan dan krisis regenerasi pertenunan di Klungkung, tapi ia masih membaca ada peluang anak muda terlibat dalam pertenunan. Dari sisi pemanfaatan kain anak muda bisa menjadi desainernya. Sehingga anak muda tidak harus menjadi penenun.
Satu sisi, menurut Tjok Wiradnyani, agar pertenunan Klungkung dapat lestari harusnya ada sinergi dengan Dinas Pendidikan. Misalnya ada program pertenunan masuk dalam kurikulum pembelajaran.
“Kita berharap sih di SMK itu pertenunan bisa menjadi pemantiknya. Sekarang kan belum ada kelas fashion di Klungkung. Kalau memang bisa dibuka mungkin anak-anak yang belum tahu soal tenun bisa berminat. Setidaknya ada jurusannya dulu, pasti ada aja yang mencoba,” optimisnya.
Ia melihat anak muda saat ini banyak yang antusias di bidang fashion. Tak jarang ia melihat anak muda rela kursus di luar untuk belajar seperti MUA. Menurut Tjok Wiradnyani, itu bisa difasilitasi dan pertenunan bisa menjadi bagian dari pembelajaran itu.
“Sekarang kan justru yang paling banyak dibuka jurusan Pariwisata, Akuntansi, IT, Perkantoran. Makanya Dinas Pendidikan perlu bisa ikut mendukung ini,” harapnya.
Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022
| No. | Pekerjaan | Jiwa | Persen (%) |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 63.344 | 28, 91 |
| 2 | Pelajar/Mahasiswa | 27.039 | 12, 34 |
| 3 | Pertanian/Peternakan/Perikanan | 33.242 | 15, 17 |
| 4 | Perdagangan | 9.026 | 4, 12 |
| 5 | Industri | 327 | 0, 15 |
| 6 | Perangkat Desa | 426 | 0, 19 |
| 7 | Konstruksi | 269 | 0, 12 |
| 8 | PNS/TNI/POLRI | 5.490 | 2, 51 |
| 9 | Swasta/BUMN/BUMD | 33.600 | 15, 33 |
| 10 | Wiraswasta | 15.965 | 7, 29 |
| 11 | Dosen/Guru | 1.471 | 0, 67 |
| 12 | Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker | 577 | 0, 26 |
| 13 | Lainnya | 28.336 | 12, 93 |
| Total | 219.112 | 100 | |
Benarkah Tidak Ada Lapangan Pekerjaan di Klungkung?
Kabupaten Klungkung menampilkan gambaran ketenagakerjaan yang penuh teka-teki. Di satu sisi, data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif rendah, tercatat 1,29% pada estimasi terbaru 2024, jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali (1,58% per Februari 2025) dan nasional (4,76% per Februari 2025). Data BPS juga menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Klungkung yang cukup tinggi, yakni 79,88% pada 2023, menandakan mayoritas penduduk usia produktif aktif secara ekonomi.
Namun, angka statistik ini seolah berbanding terbalik dengan realitas yang dirasakan sebagian masyarakat, terutama generasi muda. Keluhan “sulit mencari kerja” atau “tidak ada lapangan pekerjaan yang layak” masih sering terdengar. Lantas, benarkah tidak ada lapangan pekerjaan di Klungkung?
Wawancara dengan berbagai narasumber di Klungkung mengungkap kompleksitas di balik angka-angka tersebut. Agus Aksara, pengelola Dian’s Songket, menuturkan bahwa meskipun lowongan pekerjaan ada, seringkali tidak sesuai dengan minat dan kualifikasi anak muda.
“Banyak teman saya lebih memilih menganggur atau cari kerja di luar Klungkung karena gaji dan peluang karir dianggap lebih baik. Ada juga yang enggan mengambil pekerjaan yang dianggap ‘kotor’ atau proses rekrutmennya lama dan tidak pasti,” ungkapnya.
Proses yang panjang ini menjadi salah satu faktor yang menurunkan minat anak muda untuk terlibat aktif.
Hal serupa diungkapkan I Nyoman Sudira. Ia kesulitan mencari generasi muda yang mau menekuni kerajinan tradisional. “Anak muda sekarang maunya kerja yang cepat dapat uang, instan. Padahal menenun ini butuh ketekunan dan prosesnya lama. Orientasi mereka berbeda,” keluhnya. Meskipun usahanya mampu menyerap tenaga kerja, minimnya minat membuat regenerasi perajin menjadi tantangan besar.
I Wayan Sudiantara selaku Perbekel Gegel, membenarkan adanya lapangan pekerjaan di sektor informal dan pertanian. Namun, ia menyoroti perubahan orientasi anak muda. “Kalau mau kerja kasar atau di sawah, sebenarnya ada saja. Tapi anak muda sekarang gengsinya tinggi, maunya kerja kantoran. Ada juga yang punya orientasi ‘kalau ingin kaya cepat’, ya akhirnya memilih merantau atau kerja di kapal pesiar meski resikonya besar,” ujarnya.
Ia juga mengamini bahwa proses mendapatkan pekerjaan yang dianggap ideal oleh anak muda seringkali tidak mudah dan memakan waktu. Data dari berbagai portal lowongan kerja daring menunjukkan adanya penawaran kerja di Klungkung, didominasi sektor pariwisata dan perhotelan, terutama di Nusa Penida, serta sektor jasa lainnya. Posisi yang ditawarkan beragam, mulai dari staf operasional hingga manajerial.
Namun, aspek kelayakan menjadi sorotan. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klungkung 2025 memang telah disepakati sebesar Rp 2.996.561, tetapi beberapa tawaran gaji di lapangan, terutama untuk posisi entry-level atau di sektor tertentu, dilaporkan masih di bawah standar tersebut atau dianggap tidak sebanding dengan biaya hidup dan ekspektasi pencari kerja.
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Klungkung, melalui tim sosialisasinya, telah menjalankan berbagai program seperti pelatihan kerja, fasilitasi bursa kerja, dan sosialisasi program pemerintah. Namun, tantangan seperti akurasi data ketenagakerjaan, khususnya terkait PMI, dan jangkauan program masih perlu dioptimalkan.
Di sisi lain, para pekerja lansia di Klungkung tetap aktif bekerja, mayoritas karena dorongan ekonomi. “Kalau tidak kerja, mau makan apa? Selama masih kuat, ya kerja saja,” ujar Anak Agung Istri Oka Kartini, seorang penenun lansia di Pertenunan Astiti. Mereka umumnya bekerja di sektor informal seperti pertanian atau berdagang kecil, dengan pendapatan tidak menentu dan tanpa jaminan sosial yang memadai.

Fenomena di Klungkung menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan tidak sesederhana angka statistik pengangguran. Persepsi “tidak ada lapangan pekerjaan” lebih mencerminkan kurangnya pekerjaan yang dianggap “layak” dari segi upah dan kondisi, tidak sesuainya pekerjaan yang tersedia dengan aspirasi dan kualifikasi (khususnya anak muda), serta tantangan dalam proses rekrutmen dan akses informasi.
Mengatasi paradoks ini memerlukan upaya komprehensif yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan yang ada, penyelarasan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri, serta pengelolaan ekspektasi dan fasilitasi yang lebih baik bagi para pencari kerja di Klungkung.
Melihat kegelisahan krisisnya lapangan pekerjaan untuk anak muda di Kabupaten Klungkung, Tjok Wiradnyani berbagi peluang kerja lokal yang eksisting. Peluang pertama memang tak lepas dari sentra pertenunan. Meski regerasinya semakin kritis tapi profesi pertenunan tersebar di beberapa desa di Klungkung. Peluang kerja selanjutnya yang sudah cukup naik daun adalah profesi pelukis wayang Kamasan. Tersentralisasi di Kamasan dan upaya pelestarian profesi ini sudah masuk dalam kurikulum bangku pendidikan.
Peluang kerja ketiga, Klungkung memiliki warisan kemampuan di bidang pembuatan Gong atau gamelan Bali. Saat ini masih terpusat di Kecamatan Banjarangkan. Selanjutnya, peluang di bidang pertanian dan kelautan. Ada banyak peluang pekerjaan yang didukung oleh alam pesisir Klungkung. Seperti pemindangan, pembuatan garam dan pembuatan gula yang tersebar di Kecamatan Dawan. Satu hal lagi yaitu mulai tumbuhnya kemampuan pengrajin emas di Desa Tegak, Klungkung.
Jadi gimana semeton, ber jeg liu sajan ternyata gae-nya kan?