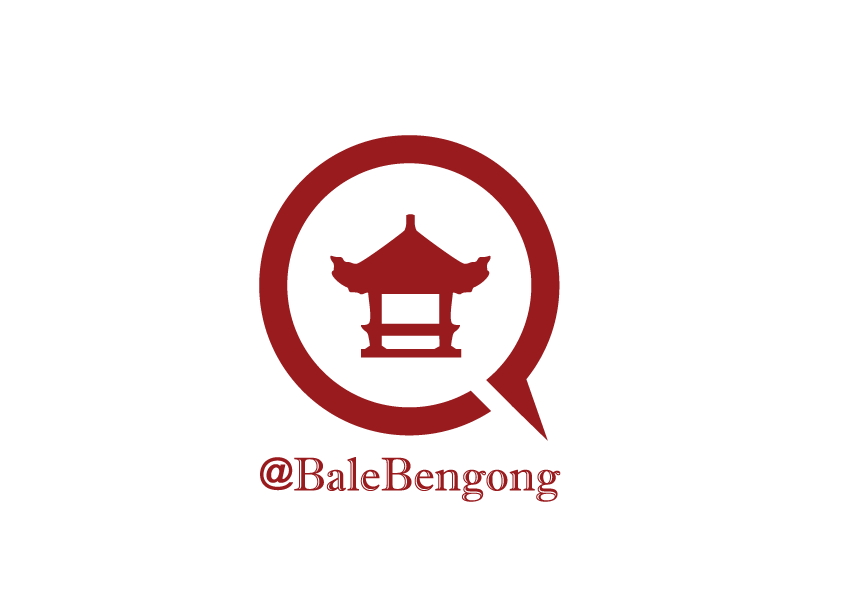Kantor kecil BaleBengong disulap menjadi bioskop. Satu per satu pengunjung berdatangan, memenuhi sisi-sisi yang kosong. Sore menjelang malam pada Jumat, 31 Oktober 2025 diselenggarakan nonton bareng film ROOTS.
Film baru diputar sekitar pukul 18.00. Penonton mulai mengambil posisi santai, ditemani bermacam sajian hidangan. Debur ombak membuka film selama beberapa detik, diikuti bayangan dua orang laki-laki, satu menggunakan pakaian adat Bali, satu lagi mengenakan topi.
Narator baru berbicara pada menit pertama sembari gambar menunjukkan lanskap Pulau Bali. Narator memulai cerita dengan memperkenalkan Walter Spies, seorang pria yang lahir di Moskow dan meninggal di laut lepas Sumatera. Dari penuturan narator, Spies memulai perjalanannya dari Eropa ke daerah tropis pada tahun 1923 untuk mencari dunia baru dan inspirasi artistik.
Sesungguhnya, nama Walter Spies sangat asing bagi saya. Tak pernah rasanya nama tersebut berdampingan dengan nama-nama orang Eropa di buku sejarah. Nama ini pertama kali saya dengar ketika film Roots diputar di beberapa tempat. Pada screening Roots pertama di Bali, poster besar bergambar topeng bertebaran di mana-mana.
Spies ternyata seorang pelukis, musisi, dan pembuat film asal Jerman. Bertahun-tahun ia menghabiskan hidupnya di Bali. Film ini digarap oleh Michael Schindhelm. Ia menggambarkan Spies sebagai sosok yang menghantui lanskap modern Bali. Beberapa adegan menampilkan Spies yang tak terlihat, wajah (rohnya) tertutup topi caping.
Selama film diputar, setidaknya ada dua tokoh yang kerap muncul, yaitu Made Bayak dan Gus Dark. Dua seniman tersebut menampilkan karyanya yang mengangkat isu-isu sosial di Bali. Selama beberapa menit, penonton diajak melihat Bali dari sudut pandang Made Bayak dan Gus Dark.
Ada banyak hal yang dibahas dalam film ini, menjadikan Roots begitu kompleks. Bayangkan, seluruh masalah dan perkembangan Bali dari kedatangan Spies ditampilkan dalam film berdurasi hampir 2 jam, mulai dari perkembangan pariwisata, peristiwa 1965, eksistensi masyarakat Bali, kemacetan, tumpukan sampah, hingga pariwisata Bali yang melenceng dari filosofi masyarakatnya.
Seorang penulis muda, Renaldi Bayu, mengungkapkan ada kesan menakutkan yang ia rasakan ketika menonton Roots. Renaldi menangkap penggambaran surealisme dan upaya membangkitkan hantu kolonialisme. Ketika diskusi berlangsung, director film Roots, Michael, menganggap kesan ini bisa saja muncul karena film ini banyak menggunakan citra malam hari, sebagaimana negara tropis memiliki malam yang panjang dibandingkan siang. Hal ini juga muncul dalam beberapa lukisan Spies yang sebagian besar menggunakan kanvas hitam. “Some of his artworks showcase Bali at night,” ujar Michael.
Michael mengungkapkan film ini bertujuan untuk membahas Bali pasca kolonialisme dengan menggabungkan narasi dari pembuat film (Eropa) dengan sejarah dan realitas Bali masa kini. Maka dari itu, dokumenter ini menyajikan berbagai sudut pandang, termasuk dari masyarakat lokal.
Michael menyebut warisan kolonial menjadi sejarah bersama untuk orang kulit putih yang pernah tinggal di Bali dan masyarakat lokal itu sendiri. “The film reflects an opportunity, you could even say suggestion on how share heritage should be treated by trying to narrate the story in a shared way,” ungkap Michael.
Roots sebagian besar menyoroti eksotisme Pulau Bali, berawal dari fokus budaya menjadi ekonomi pariwisata yang menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Pengembangan pariwisata Bali muncul pada tahun 1930-an ketika Depresi Global terjadi. Spies mengusulkan penggunaan budaya Bali sebagai daya tarik wisatawan luar negeri yang bisa bepergian antar benua. Saat itulah muncul sejumlah tokoh dunia, seperti Charlie Chaplin. Sayangnya, seiring waktu malah terjadi mass tourism yang seolah-olah mengeksploitasi budaya Bali.
“Even you know the whole UNESCO World Heritage Program, which is cultural program, is in the meantime almost a marketing tool for mass tourism, unfortunately. And Bali is a very good example for this or a bad example in a certain way,” ungkap Michael.
Proses penelitian untuk film Roots memakan waktu yang cukup lama, sekitar 7 tahun. Michael pertama kali mendengar nama Walter Spies dari seorang pria tua di kantor surat kabar Rusia. Sepuluh tahun kemudian, Michael mendengar lagi nama Spies dari seorang pengemudi taksi di Jakarta. Pengemudi taksi tersebut mendengar pembicaraan Michael dengan Bahasa Jerman dan menyebutkan bahwa ia mengenal seorang seniman asal Jerman, Walter Spies. Ia merasa ada sesuatu tentang Spies yang perlu gali, hingga akhirnya membawa Michael merencanakan film Roots. Terlebih Spies tak begitu dikenal di negaranya sendiri, sementara di Bali namanya populer di kalangan seniman.
Film ini mulai digarap sebelum pandemi. Namun, tertunda selama tiga tahun karena pandemi. “The first thing I did is actually I wrote the first biography about Walter Spies in German,” ujar Michael.
Nama Roots dipilih karena di daerah tropis banyak akar pohon di atas tanah, melambangkan asal-usul yang masih terlihat. Michael menggambarkan Roots sebagai simbol bahwa warisan masih menjadi bagian dari kehidupan. Meski menghadapi globalisasi, masyarakat Bali masih memiliki akar yang terhubung dengan warisannya.
Sementara itu, Renaldi memaknai Roots sebagai kembali ke akar, kembali mengingat diri. “Bagaimana ajar-ajaran kita seperti filosofi turun-temurun kita jaga,” ujarnya. Renaldi menambahkan bahwa sudut pandang Bali harus segera diubah agar masih bisa bertahan di masa depan. Bali harus mulai peka terhadap situasi, tidak hanya dijadikan komoditas politik.
Diskusi malam itu ditutup oleh Made Bayak. Jika ada kesempatan, Bayak ingin menambah isu perempuan dan domestikasi perempuan dalam film. Pasalnya, selama bertahun-tahun, peran perempuan Bali sangat besar di ranah domestik.