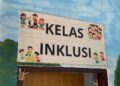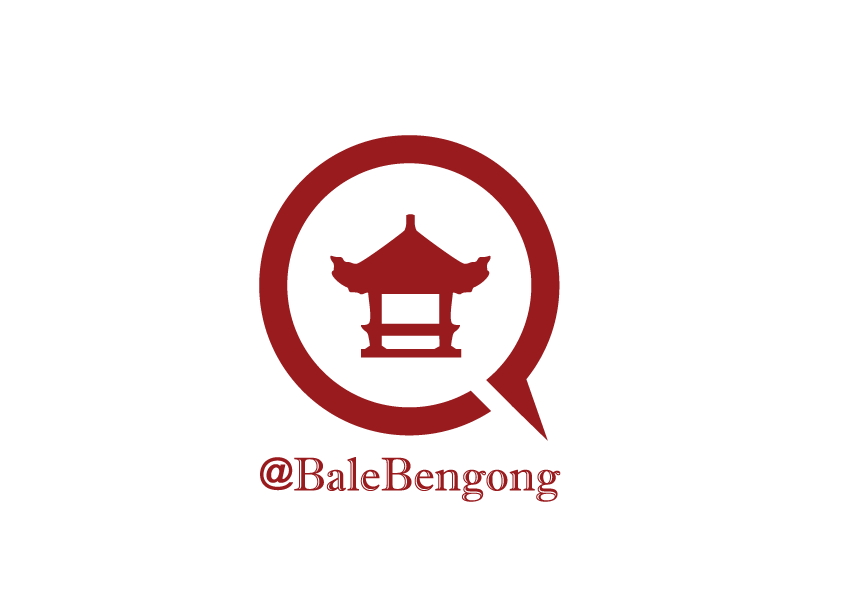“I don’t want my thoughts to die with me, I want to have done something. I’m not interested in power, or piles of money. I want to leave something behind. I want to make a positive contribution – know that my life has meaning. (Saya tidak ingin pemikiran saya mati bersama saya, saya ingin melakukan sesuatu. Saya tidak tertarik pada kekuasaan, atau tumpukan uang. Saya ingin meninggalkan sesuatu, ingin memberikan kontribusi positif – mengetahui bahwa hidup saya memiliki makna)” –Temple Grandin (wanita penyandang autis yang sukses menjadi profesor pertama di Amerika Serikat, bahkan dunia).

Jika teman-teman sudah membaca artikel sebelumnya tentang pemahaman neurodiversitas, apakah kalian masih ingat pembahasan kita tentang pelangi dengan berbagai macam warnanya?
Iya, tidak masalah apapun warnanya, biru, merah, kuning, pada akhirnya semua itu melengkapi pelangi yang indah.
Keberagaman warna tersebut sama seperti keberagaman otak manusia. Perbedaan tersebut bukanlah hal yang harus di cap sebagai keanehan, melainkan keberagaman yang membuat setiap individu istimewa.
Jika diingat kembali, istilah neurodiversitas/keberagaman neurologis digunakan untuk menggambarkan keunikan cara kerja otak setiap individu. Meskipun secara umum otak manusia berkembang dengan pola yang sama, pada kenyataannya tidak ada dua otak yang berfungsi persis serupa. Seseorang disebut neurodivergen ketika cara berpikir, belajar, berkomunikasi, atau berinteraksinya berbeda dari kebanyakan orang yang disebut neurotipikal.
Perbedaan ini tidak selalu berarti kekurangan, melainkan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara sendiri dalam memahami dan merespons dunia di sekitarnya. Karena itu, orang-orang neurodivergen mungkin menghadapi tantangan tertentu, tetapi mereka juga memiliki kelebihan dan potensi unik yang bisa menjadi kekuatan. Maka dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mengembangkan kemampuan tersebut dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna, sehat, dan sejahtera.
Kasus Neurodiversitas Kian Meningkat
Mengutip dari laman Tempo, menurut data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, diperkirakan ada sekitar 2,4 juta anak di Indonesia yang mengalami Gangguan Spektrum Autisme (GSA) atau autisme. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, menurut Presiden Junior Chamber International (JCI) Indonesia Budiman Kusmanto, 1 dari 68 kelahiran di Indonesia menghasilkan bayi dengan sindrom autisme.
Tidak hanya itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, dalam sambutan video pada acara Special Kids Expo (SPEKIX) 2024, juga menyoroti peningkatan jumlah anak dengan autisme di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa saat ini diperkirakan terdapat sekitar 2,4 juta anak Indonesia yang mengalami gangguan spektrum autisme (ASD), dan angkanya terus bertambah setiap tahun. Sementara, dokter spesialis anak dr. Bernie Endyarni Medise, SpA(K), MPH, memperkirakan jumlah kelahiran di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta anak per tahun, dengan rasio satu dari setiap seratus anak terdiagnosis mengidap ASD. Peningkatan ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam upaya penanganan dan penyediaan layanan yang memadai bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus di masa mendatang.
Tidak hanya berhenti di sana, menurut penelitian Getinet Ayano dari Curtin University dan tim di Journal of Affective Disorder (2023) menunjukkan, prevalensi ADHD global pada anak-anak dan remaja mencapai 8 persen atau 1 dari 12 anak. Perkiraan prevalensi dua kali lebih tinggi pada anak laki-laki (10 persen) dibandingkan dengan anak perempuan (5 persen).
Kasus disleksia pun turut memprihatinkan, menurut International pengenalan wajah, dan Dyslexia Association bahwa 10-15% populasi dunia adalah penderita dyslexia. Sejalan dengan itu Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Disleksia Indonesia juga menyoroti bahwa 5 juta dari 50 juta jumlah anak sekolah di Indonesia mengalami disleksia dengan rata-rata 2 juta kasus setiap tahunnya. Belum lagi kasus-kasus lainnya seperti Tourette Sindrom, Dyscalculia, Dysgraphia, yang tidak banyak diperhatikan.
Berdasarkan penuturan Desak Gede Eka Variasih selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Prima Dinas Kesehatan Provinsi Bali, di Bali sendiri untuk pendataan para neurodiversitas tidak secara spesifik dilakukan. “Kalau kita sih jumlah pasien aja, kalau Dinas Kesehatan enggak, enggak sampai ke penyakit. Nah, paling 10 besar penyakit yang kayak gitu-gitu datanya,” ujarnya pada 31 Oktober 2025.
Meski demikian, Kepala Bidang Perlindungan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti, menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada program terkait kesehatan jiwa. Namun, data mengenai neurodiversitas secara spesifik belum sepenuhnya terpantau. Ia menambahkan, program kesehatan jiwa yang ada saat ini lebih berfokus pada kegiatan screening atau deteksi dini. Misalnya, terdapat pemeriksaan khusus bagi anak-anak usia sekolah dengan metode screening tertentu, sedangkan untuk remaja dan orang dewasa, bentuk dan prosedur screening-nya berbeda menyesuaikan dengan kelompok usianya. “Cuma kalau ini di jiwa, itu lebih memang screening deteksi dini gitu. Jadi ada screening di anak sekolah umur sekian screening-nya modelnya seperti ini gitu ada beberapa. Kalau remaja dewasa beda lagi screening-nya,” ungkapnya pada 31 Oktober 2025.
Untuk prosedur screening, dijelaskan bahwa pelaksanaannya dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh para siswa sebagai bagian dari program CKG (Cek Kesehatan Gratis). Kuesioner ini digunakan untuk menilai kondisi psikologis siswa dan mendeteksi dini adanya potensi gangguan jiwa. Setelah kuesioner diisi, pihak Puskesmas akan meninjau hasilnya untuk mengidentifikasi siswa yang memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan psikiater atau tenaga kesehatan jiwa lainnya. “Jadi ada kuesionernya yang harus diisi oleh siswa. Dari situ nanti teman Puskesmas akan melihat, oh, ini dari sekian-sekian persen yang memerlukan konsultasi ke psikiater. Biasanya Puskesmas sudah kerja sama dengan spesialis-spesialis jiwa untuk bisa memberikan edukasi ke para siswa ini kalau misalnya ada permasalahan,” tutur Raka Susanti.
Dalam paradigmanya konsep neurodiversitas sendiri masih abu-abu karena dari segi pelayanan kesehatan, mereka masih kerap disamakan dengan gejala gangguan jiwa, sehingga tidak secara spesifik mendapat pengkategorian khusus atas keberagaman neuro (sel saraf) dalam pemantauan individu-individu tersebut.
Akses Medis Neurodiversitas
Secara umum, akses medis mengacu pada kemampuan seseorang untuk mencari dan memperoleh layanan kesehatan, termasuk rekam medis. Akses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara fisik, kemudahan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan menjadi hal utama. Dari sisi ekonomi, kemampuan finansial menentukan sejauh mana seseorang dapat membayar biaya layanan yang dibutuhkan. Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, karena nilai-nilai setempat dapat membentuk cara individu memandang serta memanfaatkan layanan medis. Di samping itu, ketersediaan sumber daya seperti fasilitas, obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang kompeten menjadi penentu penting apakah layanan benar-benar dapat diberikan secara efektif.
Berbicara akses medis untuk para neurodiversitas sendiri, tidak terlepas dari ketersediaan teknologi dan sumber daya yang mumpuni, untuk memberikan pelayanan terapis yang berkualitas. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri jumlah tenaga kesehatan jiwa masih jauh dari standar minimal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan populasi sekitar 250 juta jiwa, Indonesia hanya memiliki sekitar 451 psikolog klinis (0,15 per 100.000 penduduk), 773 psikiater (0,32 per 100.000 penduduk), dan sekitar 6.500 perawat jiwa (2 per 100.000 penduduk). Padahal, WHO merekomendasikan rasio minimal tenaga psikolog dan psikiater sebesar 1 banding 30 ribu jiwa, atau sekitar 0,03 per 100.000 penduduk.
Jika melihat kondisi di Bali, situasinya pun belum ideal. Berdasarkan data terbaru dari Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bali, tercatat hanya ada 111 psikolog klinis yang terdaftar sebagai anggota wilayah dan 112 orang berdasarkan domisili. Jumlah tersebut belum sebanding dengan total populasi Bali yang mencapai sekitar 4,4 juta jiwa. Artinya, rasio psikolog klinis di Bali masih rendah, yakni sekitar satu psikolog untuk lebih dari 35.000 penduduk. Selain dari segi jumlah, para tenaga ahli ini menghadapi kendala-kendala lain seperti pengalaman menangani individu neurodiversitas hingga keterampilan terhadap teknologi yang terbatas.
Menurut penuturan I Gusti Rai Putra Wiguna, psikiater Bali Mental Health Clinic dan Sudirman Medical Centre, sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Denpasar, mengungkapkan bahwa pemahaman mengenai konsep neurodiversitas baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Saat menempuh pendidikan psikiatri sekitar 15 tahun lalu, konsep tersebut belum dikenal dalam dunia akademik. Ia mengaku baru mengenal istilah dan gagasan neurodiversitas sekitar delapan tahun terakhir. “Terus terang di bangku kuliah itu kami sebenarnya konsepnya awal-awal jadi tahun-tahun itu belum neurodiversity. Saya sendiri baru mengenal konsep neurodiversity ini mungkin 8 tahun terakhir,” ujarnya saat ditemui di Rumah Berdaya Denpasar, pada 24 Oktober 2025. Selain itu, menurutnya masih ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap bahwa neurodiversitas berarti kondisi tersebut harus dibiarkan tanpa penanganan atau terapi. Padahal, pandangan tersebut keliru, karena individu neurodivergen justru tetap memerlukan perhatian dan pertolongan yang tepat sesuai kebutuhannya.
Sementara dari sisi teknologi, penerapan inovasi dalam layanan kesehatan jiwa di Indonesia masih terbilang terbatas. Mengutip artikel Arphandy (2019) dengan judul “Studi Kasus: Penggunaan Terapi Neurofeedback Untuk ADHD, Autisma, dan Gangguan Kecemasan,” dalam Jurnal Psikologi Klinis Indonesia, dinyatakan terapi Neurofeedback masih relatif baru dan belum banyak digunakan oleh para psikolog di Indonesia. Padahal, terapi ini memanfaatkan teknologi kesehatan untuk membantu penanganan berbagai gangguan seperti ADHD, autisme, dan kecemasan. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan metode ini secara lebih luas sebagai alternatif terapi berbasis teknologi. Meski demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan landasan keilmuan yang kuat serta sertifikasi khusus agar terapi dapat dilakukan dengan protokol yang benar dan sesuai standar profesional.
Secara definisi Neurofeedback merupakan sebuah metode yang dapat membantu subjek untuk mengontrol gelombang otak secara sadar (Marzbani, H., dkk, 2016). Protokol Neurofeedback berfokus pada gelombang Alpha, Beta, Theta, Delta, Gamma, atau kombinasinya (Dempster, 2012; Vernon, 2005; dalam Marzbani, II., dkk, 2016). Mengutip Arphandy (2019), kelainan fungsi otak dan gangguan mental ataupun masalah psikologis dapat dijelaskan oleh gambaran gelombang otak atau Brain mapping. Gelombang otak yang abnormal pada area otak tertentu dapat diubah dengan terapi Neurofeedback. Di Indonesia sendiri, masih sulit menemui penelitian yang membahas mengenai penggunaan terapi Neurofeedback terutama di psikologi. Padahal, terapi ini memiliki potensi untuk memberikan hasil yang lebih akurat dalam mendeteksi dan menangani gangguan dibandingkan metode pengamatan atau kuisioner semata. Hal ini karena kuesioner sangat bergantung pada subjektivitas responden dan kondisi emosional saat pengisian, sehingga sering kali menghasilkan data yang kurang konsisten. Sementara itu, Neurofeedback dan Brain mapping memungkinkan pengamatan langsung terhadap aktivitas otak secara objektif dan real-time, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi neuropsikologis seseorang.
Meski penerapannya belum merata, di Indonesia telah terdapat sejumlah klinik dan rumah sakit yang mulai menggunakan terapi Neurofeedback sebagai bagian dari layanan pendukung psikologis dan rehabilitasi mental. Di Bali, penerapan terapi Neurofeedback masih berada pada tahap awal dan umumnya dilakukan di klinik swasta. Kendati demikian, sudah ada rumah sakit umum yang mengadopsi metode ini. Mengutip Website Pemerintah Kabupaten Buleleng, baru-baru ini sejak akhir Agustus 2025, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng kini menghadirkan layanan kesehatan jiwa dengan teknologi terbaru QEEG Neurofeedback. Direktur RSUD Buleleng, dr. Putu Arya Nugraha menegaskan bahwa pihak rumah sakit tengah mengupayakan agar layanan baru tersebut dapat masuk ke dalam skema BPJS sehingga aksesnya dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Selain di Buleleng, fasilitas serupa juga mulai tersedia di Denpasar. Berdasarkan keterangan dr. I Gusti Rai Wiguna, metode Brain Mapping telah tersedia di Sudirman Medical Centre (SMC) sejak April 2025. Antusiasme masyarakat terhadap layanan ini cukup tinggi, terlihat dari daftar tunggu pemeriksaan yang kini mencapai lima hingga tujuh hari. “Ya banyak yang minat, kini yang mau melakukannya musti waiting list 5-7 hari,” ujarnya ketika dihubungi via WhatsApp pada 5 November 2025. Meski demikian, layanan ini belum tercakup oleh BPJS dan masih bersifat mandiri, dengan proses pemeriksaan yang berlangsung sekitar satu jam dan hasil dapat diperoleh dalam waktu lima hari. Harapannya, ke depan teknologi seperti Brain Mapping dan Neurofeedback dapat semakin diperluas di Bali serta terintegrasi dalam sistem layanan publik agar lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Potensi pengembangan terapi berbasis neurosains seperti Neurofeedback sebenarnya cukup besar, terutama seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental dan kemajuan teknologi medis di bidang ini. Namun, perlu diakui bahwa penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan tenaga profesional yang tersertifikasi, belum meratanya fasilitas teknologi, serta belum adanya regulasi atau kebijakan khusus yang secara eksplisit mendorong penggunaan dan standarisasi terapi ini bagi neurodiversitas di Indonesia.
Perjuangan Menuju Inklusif
Selain layanan terapis yang masih terbatas, persoalan akses bagi individu neurodivergen juga muncul pada layanan kesehatan umum lainnya, termasuk layanan gigi dan mulut. Seperti yang diungkap dalam laporan BaleBengong sebelumnya berjudul “Kesehatan Gigi dan Mulut Belum Inklusif, Anak Disabilitas Sulit Mengakses”, anak-anak dengan kondisi neurodivergen terutama autisme menghadapi tantangan besar dalam memperoleh layanan kesehatan gigi yang layak. Banyak dari mereka mengalami sensitivitas sensorik, kesulitan komunikasi, atau kecemasan yang tinggi terhadap prosedur medis, sehingga membutuhkan pendekatan dan perlakuan khusus dari tenaga kesehatan. Namun, di lapangan, jumlah dokter gigi dan perawat yang memiliki keterampilan khusus untuk menangani individu neurodivergen masih sangat terbatas.
Akibatnya, keluarga harus mencari klinik khusus atau memilih jalur layanan dengan biaya yang lebih tinggi. Kondisi ini memperlebar kesenjangan akses, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, yang akhirnya membuat pemeriksaan gigi rutin bagi anak-anak neurodivergen sulit dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut penuturan I Gusti Rai Wiguna, akses medis yang ideal bagi individu neurodivergen seharusnya dirancang dengan prinsip ramah neurodivergen, sebagaimana konsep rumah sakit ramah anak atau ramah lansia. Fasilitas kesehatan perlu menyediakan layanan terintegrasi melalui poli tumbuh kembang yang menghadirkan tim multiprofesional seperti dokter anak, psikiater, psikolog, hingga terapis dalam satu tempat, sehingga pasien tidak perlu berpindah-pindah untuk mendapatkan penanganan menyeluruh. “Jadi sama aja kalau ada rumah sakit ramah anak, rumah sakit ramah lansia, seharusnya ada dong ya layanan ramah neurodivergen. Jadi misalnya ada poli tumbuh kembang dimana, multiprofesional hadir disana. Itu tanpa orang perlu berpindah-pindah tempat,” ujarnya.
Selain itu, aspek lingkungan seperti pencahayaan, desain visual, dan fasilitas pendukung juga harus disesuaikan agar nyaman bagi individu dengan sensitivitas sensorik tinggi. Namun yang terpenting, pemahaman mengenai kondisi neurodivergen perlu dimiliki oleh seluruh tenaga medis, bukan hanya mereka yang bekerja di poli khusus. Sebab, individu neurodivergen tetap dapat mengalami penyakit umum seperti infeksi telinga atau demam berdarah, sehingga dokter spesialis lain dan tenaga keperawatan juga harus memahami cara berinteraksi serta memberikan perawatan yang sesuai.
Dari pengalaman Rai, terkadang masih ada stigma yang melekat di lingkungan medis. Misalnya, pasien dengan skizofrenia yang datang berobat untuk keluhan umum seperti demam sering kali diperlakukan berbeda begitu tenaga medis tahu kondisi psikiatriknya. “Padahal mereka udah ngobrol 10 menit. Hanya karena diberitahu mengalami keadaan ini, orang jadi menghindar,” ujarnya. Hal yang sama juga terjadi pada anak autistik yang datang dengan keluhan fisik atau demam, alih-alih memeriksa kondisi medisnya, tenaga kesehatan justru lebih memperhatikan bagaimana autisnya ditangani. Padahal, mereka datang bukan untuk konsultasi perilaku, melainkan untuk berobat seperti pasien umumnya. “Termasuk anak-anak yang autis mereka nggak fokus pada keluhannya yang sekarang misalnya gangguan fisik atau demam. Mereka fokus pada gimana autisnya ditangani atau nggak. Mereka kan datang untuk keluhan yang lain” ungkap dokter Rai.
Situasi ini menunjukkan bahwa stigma dan kurangnya pemahaman masih menjadi penghalang utama bagi akses kesehatan yang inklusif bagi individu neurodivergen. “Semua tenaga kesehatan mestinya memahami itu. Bagaimana dokter THT nanti kalau mau memeriksa neurodivergen, bagaimana dokter penyakit dalam memeriksa, nah itu penting ya pemahaman itu. Kemudian tenaga medis yang lain misalnya keperawatan bagaimana mengatur ruang rawat enak yang nyaman untuk neurodivergen, ini kan berbeda-beda. Jadi pemahaman itu penting,” jelas dokter Rai.
Hal ini juga dipertegas oleh Atmojo, dkk, dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Peran Tenaga Kesehatan dan Dukungan Keluarga dalam Proses Pemulihan ODGJ di Puskesmas” yang diterbitkan di Jurnal Keperawatan Jiwa, mengungkapkan bahwa petugas kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. Hal ini berguna untuk masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Maka, dengan meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam memberikan layanan yang sensitif terhadap stigma, akan tercipta pelayanan yang lebih efektif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan medis tetapi juga mendukung proses penyembuhan psikologis pasien.
Idealnya, layanan kesehatan bagi individu neurodivergen tidak perlu dipisahkan dalam fasilitas khusus, melainkan dibuat inklusif seperti konsep dasarnya. Mereka seharusnya bisa mengakses layanan di Puskesmas atau layanan BPJS sama seperti masyarakat umum, hanya saja dengan penyesuaian sesuai kebutuhan mereka. Namun, perlu diakui bahwa masih perlu waktu dan usaha yang lebih untuk mewujudkan konsep ini. Karena itu, sementara waktu, keberadaan klinik atau fasilitas khusus bisa menjadi solusi sementara. “Tapi idealnya mereka bisa mengakses layanan umum itu. Jadi layananlah yang perlu beradaptasi,” jelas dokter Rai.
Sebagai gambaran, di Amerika Serikat, Cleveland Clinic telah menunjukkan tingkat perkembangan yang jauh dalam hal pemahaman dan layanan untuk pasien dengan kondisi neurodivergen. Melalui artikel “Caring for Patients with Neurodivergence” di platform Consult QD mereka, dijelaskan tentang pendekatan terpadu dan fasilitas ramah-neurodivergen yang diterapkan untuk memastikan bahwa pasien dengan kebutuhan neurologis khusus mendapatkan perawatan yang sesuai dan inklusif. Seperti diketahui reputasi Cleveland Clinic secara konsisten dianggap sebagai salah satu sistem rumah sakit terbaik di Amerika Serikat dan di dunia, dan sangat dihormati, terutama dalam sistem manajemen teknologinya. Hal ini menunjukkan standar tinggi yang bisa menjadi acuan atau tolak ukur bagi layanan kesehatan di Indonesia untuk terus berbenah dan bergerak ke depan.
Stigma Sosial dan Budaya
Seperti yang kita ketahui, gerakan neurodiversitas berupaya menegaskan bahwa perbedaan kombinasi sel saraf manusia, bukanlah bentuk “penyimpangan,” melainkan bagian dari keberagaman manusia yang patut diterima.
Mengutip penelitian Kusumawati, Abdal & Kurniawan tahun 2025, dengan judul “Analisis Dampak Stigma terhadap Penyakit Mental dan Upaya Pengurangannya di Masyarakat”, dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, menunjukkan bahwa stigma berdampak negatif pada akses layanan kesehatan, integrasi sosial, dan kesejahteraan psikologis pasien. Stigma yang melekat terhadap gangguan mental membuat banyak individu merasa malu dan takut untuk mencari pertolongan. Situasi ini semakin diperparah oleh persepsi sosial yang masih menganggap gangguan mental sebagai tanda kelemahan atau bahkan sesuatu yang berbahaya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sekitar 6% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Namun, sebagian besar memilih untuk menyembunyikan kondisi mereka atau tidak mencari bantuan medis karena khawatir akan mendapatkan label negatif seperti “kerasukan,” “karma,” “gila” atau “tidak normal”.
Oleh karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi kognitif dengan cara menata ulang pola pikir masyarakat agar lebih terbuka dan inklusif. Di samping itu, penguatan kapasitas individu dengan gangguan mental menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka dan mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Menurut Khalida Zia Br Siregar (2024, dalam Kusumawati, 2025), dukungan dari keluarga serta kelompok sebaya (peer support) juga berperan krusial sebagai fondasi utama dalam proses pemulihan.
Maka, upaya menghapus stigma dan membangun masyarakat yang lebih inklusif perlu diiringi dengan dukungan nyata melalui program pelatihan dan komunitas pendamping bagi individu neurodivergen. Inisiatif seperti ELMO di Surabaya, PUPA Center di Jakarta, dan gerakan Walk for Autism Jakarta menunjukkan bahwa kolaborasi antara keluarga, tenaga profesional, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Program PUPA, misalnya, menekankan pentingnya pengembangan life skill dan kesiapan kerja agar individu neurodivergen dapat hidup mandiri dan berdaya. Sementara, Walk for Autism berfokus pada edukasi publik serta membangun jejaring dukungan antar keluarga penyandang autisme. Upaya-upaya semacam ini membuktikan bahwa perubahan paradigma terhadap gangguan mental dan neurodiversitas tidak hanya bisa dicapai melalui ruang medis, tetapi juga didukung dengan tindakan kolektif yang menumbuhkan empati, pemberdayaan, dan ruang partisipasi yang setara bagi mereka.
Kesadaran dan fasilitas bagi individu neurodivergen di Indonesia, khususnya di Bali, masih sangat terbatas. Namun bukan berarti tidak menunjukkan perkembangan. Perlahan penyediaan fasilitas yang inklusif dan pemahaman stigma penting dilakukan. Bali yang dikenal sebagai daerah internasional memiliki potensi besar, sekaligus tantangan, mengingat banyaknya wisatawan dan pendatang dari berbagai negara, termasuk mereka yang berada dalam spektrum neurodivergen. Namun, tanpa fasilitas dan pemahaman yang memadai, potensi tersebut justru dapat menimbulkan persoalan, baik dalam pelayanan publik, interaksi sosial, maupun persepsi budaya terhadap perilaku yang berbeda.
Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan literasi publik mengenai neurodiversitas di Bali. Maka diperlukan pemahaman bersama antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan penyedia layanan kesehatan dalam menghapus stigma, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta kesempatan bagi mereka untuk hidup berdaya di tengah masyarakat.