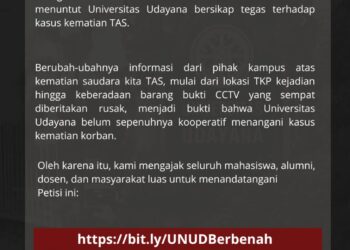Jika petani sawah menanti hujan, maka petani garam menanti cuaca terik.
Ada sekitar 2.000 mg natrium yang harus dipenuhi petani garam untuk tiap orang Indonesia per harinya. Namun, musim penghujan mengguyur Bali sejak akhir tahun 2020 lalu. Bahkan bagi petani garam tradisional kondisi ini membuatnya tak bisa beroperasi sama sekali.
Padahal proses dari air laut menjadi garam memerlukan tahapan panjang. Meski tidak ada pengkristalan air laut yang gagal menjadi garam, tetapi ada proses yang semakin lama termakan waktu.
Seperti halnya pembuatan garam Kusamba yang terletak di pesisir Pantai Pesinggahan, Klungkung. Hanya ada tiga petani garam yang memanen air laut di pesisir Pantai Pesinggahan itu.
Proses pembuatan garam di sana menjadi salah satu pembuat garam tanpa unsur plastik. Pembuatan garam diawali dari pengambilan air laut menggunakan teku lalu disiramkan ke pasir, biasanya proses ini disebut nabuh. Pasir yang sudah disiram dijemur selama 6 jam di bawah panas matahari yang terik.
Setelah pasir kering, dilanjutkan dengan nyacain. Proses ini berupa penggeburan kristal garam dengan pasir menggunakan alat dari kayu berbentuk ruas-ruas seperti sisir. Kemudian, pasir yang kering dikumpulkan menggunakan keranjang bernama sok kenong. Proses ini disebut ngaudang.
Pasir-pasir kering ini ditaruh ke dalam bak penyosoran.
Proses dalam bak inilah yang menjadi pemisahan antara garam dan pasir. Pasir akan disosor atau disiram menggunakan air laut yang sudah diproses. Proses ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian, karena kristal-kristal dalam pasir akan mengalir melalui lubang kecil yang berada di bawah bak penyosoran. Air dari bak ini ditampung dalam belong, bak yang terbuat dari batang pohon kelapa.
Air yang disiramkan ke pasir melalui beberapa proses. Ni Wayan Suriasih, petani garam Kusamba yang sudah sejak tahun 1980-an memanen air laut menjadi garam menceritakan, setiap petani garam memiliki cita rasa garam yang berbeda. Salah satu pengaruhnya berada pada tahap penyiraman air laut ke dalam bak penyosoran.
“Di sana (tahap penyosoran) seninya membuat garam. Kalau air yang digunakan nyosor itu air nomor 1, maka air itu disebut yeh wayah, air yang siap dijadikan garam,” tuturnya.
Yeh wayah didapatkan dari tirisan air hasil beberapa kali penyiraman pasir yang didiamkan sehari. Sedangkan air lau yang baru dicari masuk dalam jenis air nomor 3. Sehingga untuk menjadi yeh wayah, perlu melalui proses disiramkan beberapa kali lagi.
Keesokan harinya, yeh wayah sudah siap dijemur di palungan untuk pengkristalan. Perlu dua hari untuk proses penjemuran menjadi garam di bawah matahari yang terik. Selama dua hari penjemuran yang terik, Suriasih dapat memanen sekitar 30 kg garam.

Alat Tradisional
Menantunya, Ni Ketut Purniasih yang sekaligus menjadi penerus petani garam menyebutkan alat-alat yang digunakan membuat garam masih tradisional. Mereka menjadi salah satu petani garam yang menolak menggunakan plastik untuk mengkristalkan air laut.
“Kalau jemur pakai karet atau plastik, orang yang tau rasa garam, akan tahu perbedaannya. Kalau jemur pakai palungan (terbuat dari batang pohon kelapa) rasanya gurih dan ada sedikit rasa manis. Kalau pakai plastik atau karet, rasanya asin kepahitan,” sebut Ketut yang juga berprofesi menjadi guru.
Sebelum pandemi, Ketut dan mertuanya memasarkan garamnya ke wisatawan yang berkunjung ke kubu pembuatan garamnya. Penghasilannya tidak selalu dari hasil jual. Namun, tamu memberikan donasi sukarela karena ia sambut wisatawan dengan atraksi prosesi pembuatan garam.
Pandemi mengubah pola penghasilannya. Kini ia hanya memiliki pasar lokal yang membeli produk laut itu. Ditambah lagi musim penghujan yang terus mengguyur lahan garamnya, sehingga sama sekali ia tak bisa berproduksi.
Alat tradisional menjadi andalan untuk mempertahankan kualitas rasa gurih. Namun, musim hujan tiba, waktunya Ketut dan Mertuanya beristirahat memanen air laut. Karena memanen air laut menjadi garam di tengah hujan adalah mustahil. [b]
kampungbet