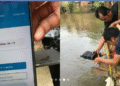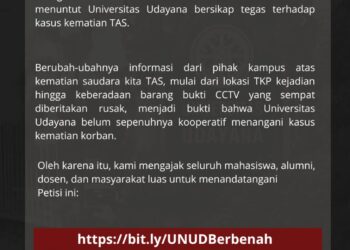I Wayan Aden, 30-an tahun, tiba-tiba menubruk temannya dari belakang.
Sore itu, mereka berjalan menyusuri sungai kecil di dalam hutan bakau di Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Keduanya terjatuh di lumpur.
Mereka lalu saling bergulat di lumpur. Dengan lagak seperti orang berkelahi keduanya saling melempar lumpur kecoklatan. Bukannya marah, teman Aden malah tertawa. Mereka bangkit, lalu berjalan kembali menyusuri semacam saluran sungai dengan air setinggi mata kaki tersebut.
Di belakang, sekitar 300 orang lainnya menyusul mereka. Semua berpakaian kurang lebih sama, hanya mengenakan sarung Bali yang digulung hingga pangkal paha seperti celana pegulat. Semua peserta laki-laki bertelanjang dada.
Hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi di Desa Kedonganan itu pun riuh oleh teriakan mereka. Kamis sore itu, hutan bakau di desa di sisi selatan Bandara I Gusti Ngurah Rai itu pun riuh oleh teriakan mereka.
Ketika sampai di tengah hutan bakau di mana terdapat lumpur berwarna kecoklatan dengan tekstur liat, mereka saling melempar atau mengoleskan lumpur itu. Tak hanya ke tubuh mereka sendiri tapi juga ke teman-temannya.
Pada Kamis sehari setelah Nyepi sore itu, warga adat Desa Kedonganan sedang melakukan tradisi mebuug-buugan. Tradisi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 1920-an. Namun, akibat letusan Gunung Agung Bali pada 1963 dan kemudian pembantaian pada 1965, tradisi ini pun berhenti. Sejak tahun lalu, warga melaksanakan kembali Mebuug-buugan.
“Karena itu, kami senang sekali bisa menghidupkan kembali tradisi yang sudah lama mati,” kata Aden.
Made Sukada, sekretaris Desa Adat Kedonganan mengatakan tradisi mebuug-buugan berasal dari kata buug, yang dalam bahasa Bali berarti lumpur. Hal ini tak lepas dari proses di mana mereka saling melempar atau mengoleskan lumpur ke tubuh mereka. Tradisi ini, menurutnya, pada dasarnya bermakna filosofis dan masih terkait dengan Hari Raya Nyepi.
“Ada korelasi mendalam antara Hari Raya Nyepi dengan mebuug-buugan,” kata Sukada. Dia menyatakan, pada saat Hari Nyepi, umat Hindu di Bali penyucian Bhuana Agung dan Bhuana Alit. Secara sederhana, Bhuana Agung adalah alam dan jagat raya, sedangkan Bhuana Alit adalah mikrokosmos atau lingkungan kecil manusia.
Untuk penyucian Bhuana Agung, umat Hindu melakukan upacara menjelang Nyepi. Setelah itu, pada puncak hari Nyepi, umat Hindu melakukan Catur Brata Penyepian atau empat pantangan yaitu tidak bekerja (amati karya), tidak menyalakan api (amati geni), tidak bepergian (amati lelungan), dan tidak bersenang-senang (amati lelanguan).
“Setelah Catur Brata Penyepian, kami harus melakukan mulat sarira atau instropeksi dengan pikiran jernih dan tenang. Ritual mebuug-buugan adalah simbol di mana kita melakukan pembersihan diri itu,” kata Sukada.
Sebagai bagian dari tradisi Mebuug-buugan, para peserta juga melakukan pembersihan diri. Begitu pada Kamis lalu. Setelah saling melumuri badan dengan lumpur, ratusan peserta dari anak-anak sampai orang tua itu, berjalan menuju sisi barat Desa Kedonganan di mana terdapat pantai berpasir putih.
Pesan Lingkungan
Meskipun menjadi ritual adat, mebuug-buugan juga memiliki pesan untuk pelestarian lingkungan. “Pesannya jelas, lingkungan harus tetap ada agar kami bisa tetap melakukan tradisi ini,” kata I Made Sudarsana, pengurus desa yang juga menghidupkan lagi tradisi ini.
Menurut alumni S2 Institut Seni Indonesia (ISI) Solo tersebut, sejak dulu tradisi mebuug-buugan selalu dilaksanakan di tengah hutan bakau. Hutan di sisi timur desa ini termasuk wilayah Teluk Benoa yang akan direklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).
Desa Adat Kedonganan sendiri termasuk salah satu dari sekitar 20 desa adat di Bali selatan yang sudah menolak rencana reklamasi. Warga juga melakukan beberapa kali aksi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa di desa sendiri maupun bersama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI). Meskipun demikian, pengurus desa adat berkali-kali menyatakan agar tradisi mebuug-buugan tidak dihubungkan dengan aksi tolak reklamasi.
“Kami hanya murni melaksanakan kembali tradisi di desa kami. Tidak ada hubungan dengan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa,” kata Bendesa Adat I Ketut Puja. Meskipun demikian, dia tetap mempersilakan jika ada warga yang membawa isu penolakan dalam ritual kali ini selama tidak terlalu ditonjolkan.
Dalam pelaksanaan mebuug-buugan kali ini, beberapa kelompok pemuda toh tetap membawa suara penolakan terhadap rencana reklamasi. Ada yang mengenakan ikat kepala Bali Tolak Reklamasi ataupun membawa spanduk “Desa Adat Kedonganan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Batalkan Perpres No 51 tahun 2014”.
Mereka membentangkan spanduk tersebut pada saat sembahyang di Pura Desa. Spanduk itu juga dibawa dari Pura Desa ke lokasi mebuug-buugan yang berjarak sekitar 500 meter dari pura. Mereka lalu mengikatnya di pinggir hutan bakau yang akan direklamasi PT TWBI.
Selain terkait isu reklamasi, Sukaja mengatakan tradisi mebuug-buugan juga mengingatkan agar warga tetap menjaga lingkungan terutama keberadaan hutan bakau. Karena lokasi mebuug-buugan berada di tengah hutan bakau, maka warga mau tak mau harus menjaga hutan bakau tersebut.
Kedonganan sendiri termasuk dalam wilayah Prapat Benoa yang memiliki hutan bakau terluas di Bali. Menurut data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Unda Anyar, di kawasan yang menghubungkan segi tiga emas pariwisata Bali yaitu Nusa Dua – Kuta – Sanur ini terdapat 1.373,5 hektar hutan bakau.
Dari luas hutan mangrove tersebut, sebagian di antaranya dalam kondisi rusak seluas 253,4 hektar. Namun, secara umum, hutan bakau di wilayah Desa Kedonganan masih terjaga, termasuk di lokasi mebuug-buugan.
“Tradisi mebuug-buugan mengingatkan kepada kami untuk menjaga hutan bakau sekaligus menolak reklamasi. Sebab, jika ada reklamasi, di mana lagi kami akan melakukan tradisi kami,” kata Sukaja. [b]