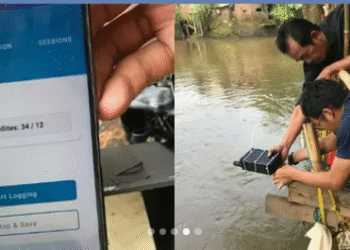Agamben menganggap fotografi adalah gambaran dari Penghakiman Terakhir.
Saya terbiasa untuk memotret hal-hal sepele yang hanya menarik bagi diri sendiri. Sebagian besar objek foto saya adalah pemandangan yang sembarang, kucing, anjing, atau orang-orang terdekat saya bersama kegiatannya.
Kadang-kadang saya memotret ranting pohon dengan latar langit karena saya senang sekali melihat pemandangan tersebut. Seringkali, saya tidak menyunting foto yang telah dihasilkan. Jadi jika foto tersebut miring atau memiliki warna yang kurang menarik, itulah yang saya tampilkan di laman media sosial saya.
Apa adanya, dan mungkin agak mengganggu bagi mereka yang paham akan estetika fotografi. Foto-foto yang saya hasilkan secara keseluruhan mungkin tidak memiliki daya pikat bagi orang lain di luar saya sendiri. Mungkin. Akan tetapi, inilah suatu hal yang, bagi saya, menarik dari fotografi itu sendiri.
Fotografi membebaskan orang yang berada di belakang jendela bidik kamera untuk memilih dan kemudian memotret apapun. Misalnya, ketika berada di meja makan yang sama, saya dan kamu bebas untuk memotret entah itu makanan yang tersaji di meja, orang yang sedang menyuapkan makanan ke dalam mulut, atau detail kecil seperti lalat yang hinggap di bibir mangkuk. Kita semua bebas untuk menampilkan apapun dalam foto.
Hal ini senada dengan gagasan Giorgio Agamben, seorang filsuf Italia, pada salah satu esainya dalam karyanya, Profanations (2007). Agamben beranggapan bahwa fotografi adalah gambaran dari Penghakiman Terakhir (The Last Judgement).
Dalam Penghakiman Terakhir, ketika kerumunan manusia terhampar di hadapan Yang Kudus, Ia tentu tidak menghakimi semuanya sekaligus. Penghakiman itu akan dilakukan secara satu per satu; Ia memilih satu manusia di antara sekian banyak dalam satu waktu.
Sama seperti fotografi, di antara sekian banyaknya hal yang terhampar dalam suatu waktu, sang fotografer akan fokus pada satu objek dan mengabaikan hal lainnya. Dan sama seperti manusia yang akan mendapatkan kemuliaan setelah penghakiman, objek dalam foto juga akan mendapatkan “keabadian”-nya setelah dipotret. Ia akan berada dalam sebuah bingkai bernama foto, selamanya selagi foto tersebut ada. Fotografi membebaskan subjeknya untuk memulai dari mana.
Fotografi, terlepas dari definisi teknisnya untuk melukis cahaya, adalah pembekuan realitas. Ia mereproduksi suatu kenyataan yang hanya akan terjadi sekali saja. Ia mengulang apa yang secara eksistensial tidak bisa diulang kembali—hal yang hanya ada di masa lampau yang tentunya sudah kita lalui.
Ada dua hal yang kemudian bersinggungan di sini, yaitu realitas dan yang-lampau. Maka dari itu, Roland Barthes menyebut bahwa esensi atau noeme dari sebuah foto adalah “That-has-been” atau “Yang-sudah-terjadi.” Dalam Camera Lucida: Reflections of Photography (1982), filsuf Prancis ini menyebutkan bahwa sudah merupakan sebuah kepastian bahwa objek yang ada dalam sebuah foto memang benar pernah ada-di-sana. Dan sebaliknya, foto tersebutlah yang bisa menjadi sarana pembuktiannya.
Saya tentu punya sosok fotografer profesional yang saya favoritkan. Akan tetapi, saya juga begitu senang melihat hasil karya para fotografer amatir. Mereka dapat menampilkan sebuah realitas dengan apa adanya. Foto yang mereka hasilkan terasa jujur dan tanpa “topeng” apapun sebab memang begitulah kenyataannya. Kekaburan objek, pencahayaan yang kadang tidak memadai, garis-garis lurus yang tampak miring, ketidaksiapan objek untuk difoto, dan lain sebagainya. Keteledoran-keteledoran ini yang membuat fotografer amatir justru semakin dekat dengan noeme fotografi itu sendiri.
Keamatiran dalam memotret dan menyunting, atau bahkan ketiadaan penyuntingan dalam fotografi, malah membuat sebuah foto menjadi menarik di mata saya. Ini menyebabkan tidak adanya kebimbangan atas realitas objek dalam foto tersebut. Foto tersebut sederhana, tanpa tipuan, dan tanpa “riasan” apapun.
ustru bagi saya inilah ihwal yang paling sulit dalam fotografi: memperlihatkan apa yang benar-benar terjadi tanpa harus bergantung pada penyuntingan dan properti pemercantik foto lainnya. Walaupun dalam dunia fotografi profesional penyuntingan mesti dilakukan untuk menambah nilai estetika dan bahkan penekanan makna yang ingin disampaikan melalui sebuah foto. Dan bagi saya, hal itu pun sama sekali tidak ada salahnya.

Napak Tilas
Album foto keluarga masih tersimpan rapi dalam lemari ruang tengah rumah saya. Foto pernikahan papa dan mama, foto telanjang saya dan kakak saya saat bayi, foto rumah saya yang waktu itu sedang dibangun, foto anjing peliharaan saya, foto pentas tari saya saat masih duduk di taman kanak-kanak, dan foto-foto lainnya, semuanya masih tertambat dengan baik.
Dengan melihat foto-foto tersebut, saya bisa melakukan napak tilas perjalanan kehidupan saya dan keluarga. Saya percaya bahwa kami pernah ada di situ, melakukan itu, di waktu itu, bersama orang-orang itu. Saya melihat foto-foto tersebut untuk percaya pada Yang-sudah-terjadi. Dengan begitu, secara tidak langsung saya percaya terhadap foto tersebut. Inilah salah satu fungsi penting dari fotografi bagi saya: menciptakan rasa percaya.
Akan tetapi, kini fotografi sudah menjadi suatu hal yang begitu biasa, bahkan lebih banal daripada kegiatan foto-foto untuk dokumentasi keluarga. Sekarang kamera bukanlah barang mewah sebab hampir setiap ponsel pintar kita dilengkapi dengan fitur kamera. Kita bisa memotret apapun, kapanpun, dimanapun, sebanyak apapun yang kita mau.
Banalnya fotografi juga didukung oleh adanya sosial media. Sebuah foto kini tidak dibuat untuk memperlihatkan Yang-sudah-terjadi secara gamblang sebab ia dapat direkayasa dengan mudah. Contohnya filter-filter pada aplikasi Snapchat dan fitur Instastory pada aplikasi Instagram. Bisa jadi saya memiliki wajahmu dan kamu memiliki wajah saya dalam satu bingkai. Di waktu lain, bisa jadi saya punya telinga dan hidung anjing.
Barthes menyebut bahwa “apa yang menjadi karakter dari masyarakat maju adalah bahwa mereka kini mengonsumsi gambar dan tidak lagi, seperti masyarakat di masa lalu; percaya.” Nah, kalau begini, Barthes tampak seperti seorang kakek yang merasa bahwa kehidupan generasinya adalah bentuk kehidupan yang terbaik dan karenanya harus dicontoh.
Akan tetapi, untuk argumennya soal konsumsi gambar, saya mau tidak mau harus setuju. Pasalnya, kini masyarakat semakin dimudahkan dengan adanya media Instagram. Di sana, kita bisa berbagi foto dan video apapun, dan karenanya juga mengonsumsinya. Lingkarannya berputar pada produksi dan konsumsi. Walaupun begitu, saya pikir, hal tersebut tidak bisa dikatakan seratus persen salah. Justru Instagram memperlihatkan banyak imaji-imaji yang segar, meski kita dibuat untuk belajar menelaah foto mana yang bisa dipercaya.
Terlepas dari itu, budaya Instagram seringkali membuat saya penat lalu bertanya-tanya, apa motif seseorang dalam memotret, ya? Apakah engagement yang tinggi? Hobi? Cari uang? Atau hanya sekadar memotret saja? Apapun itu, kepenatan saya seringkali berujung pada kegiatan berjalan-jalan dan memotret apapun yang menarik di depan saya.
Menjadi flaneur—seseorang yang keluyuran tanpa tujuan yang pasti—dan memotret apapun yang tersedia di depan mata, saya merasa bebas dan bisa belajar menelaah sekitar. Kini hal tersebut bisa dilakukan semua orang; semua orang bisa menjadi fotografer. Perkara bagus atau tidaknya adalah masalah selera sebab kembali lagi, kitalah pemegang otoritas dalam fotografi. Seperti kata Agamben, kita sebagai subjek dalam fotografi adalah Yang Kudus dalam Penghakiman Terakhir!
Maka dari itu, banalnya fotografi justru bisa menjelma momentum bagi siapapun untuk belajar. Bagi saya, para fotografer yang tengah belajar, mereka yang bisa disebut sebagai amatir, adalah yang secara tidak langsung menawarkan kejujuran dalam karyanya. Itu yang menjadi nilai plus mereka dibanding fotografer profesional. Lewat foto-fotonya, mereka tidak akan membuat kita susah payah untuk percaya pada Yang-sudah-terjadi. Dengan begitu, setidaknya kita tidak akan menjadi sepesimis Barthes; masih ada alasan bagi kita untuk tetap percaya pada kekuatan sebuah foto. [b]






![[Esai Foto] Kontemplasi di Atas Selat Bali](https://balebengong.id/wp-content/uploads/2018/01/Ketapang-Gilimanuk-16.jpg)