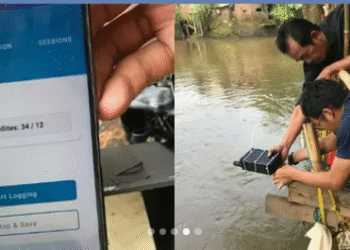Gerimis telah reda, matahari segera tenggelam.
Hujan sore ini singgah sementara. Kedatangannya hanya untuk meredam debu jalanan. Tak sampai membasuh kotoran daun-daun, apalagi mengisi got-got yang kering.
Sasih Kesanga tak lagi bersemi dalam hujan dan deru angin kencang, senggama anjing tak lagi nampak ramai di rurung-rurung, mungkin alam sudah tak pandai mengatur diri.
Kalender Bali tak lagi tepat dalam memprediksi. Alam sengaja berevolusi ataukah karena manusia yang pikirannya mulai panas hingga mempengaruhi cuaca.
Aku teringat kata-kata Kakek dulu. Saat itu kerentaannya masih dapat dipaksa menggarap sawah. Ia bertutur, “Yan, meski langit tak sepenuhnya menjawab doa manusia, kita mesti bersyukur atas apapun yang menjadi kehendaknya, sebab sejak jaman dimulai Ia tak pernah salah dalam memberi, hanya saja manusia yang terlalu ambisius dalam memuaskan keinginan.”
Kakek juga mengatakan bahwa hujan yang turun usai tawur adalah suatu petanda baik untuk kita. Bahwa persembahan telah diterima. Dewa-dewa bergembira dan bhuta kala telah ter-somiya. Kini bersamaan dengan memudarnya ingatan itu, tumbuh pula keyakinanku bahwa kakek juga sedang berbahagia. Sebab Ia telah pergi ke rumah Para Dewa menjadi pengayah setia Sang Dewa junjungannya, meski Ia telah kehilangan raga yang diyanginya. Di sana, tiada lagi Ia menemukan kekalutan dan duka seperti di atas tanah.
Di atas leneng yang caping bekas tabrak truk, aku duduk dalam lamunan. Memandangi jalanan yang mulai sepi oleh kendaraan, tetapi seperti tahun sebelumnya sebentar lagi kelenggangan bakal tergantikan oleh riuh teriakan.
Kulkul di sudut balai banjar telah dibunyikan dengan hitungan empat kali ketukan yang dipukul secara berulang-ulang. Mengingatkan pemuda dan pemudi untuk berkumpul. Satu per satu dari mereka mulai berdatangan, memakai kain bawahan hitam dengan baju serba hitam pula.
Para lelaki bersiap dengan mengenakan sepatu, sedangkan para perempuan membawa sebatang bambu sepanjang satu meter, yang ujungnya disumpal serabut kelapa. Mereka akan mengarak ogoh-ogoh menuju bencingah, diiringi tetabuhan gamelan, obor, kulkul-kulkul kecil dan sorakan. Sekejap jalanan disulap meriah dalam parade kegembiraan.
Aku masih nyaman di atas leneng, memperhatikan lalu lalang orang-orang. Tidak saja yang muda, para orang tua pun ikut merayakan Pangerupukan. Malam ini, mereka punya kesempatan terbebas dari rutinitas harian, bebas dari tanggung jawab pekerjaan dan bebas dari kewajiban adat. Meski tetap dalam tugas domestik, mengawasi anak-anak. Seolah kini jalanan telah mereka kuasai, merebutnya dari kuasa roda-roda bermesin yang telah lama merenggut kebebasan pejalan kaki.
Ini adalah kali ke tiga aku dan keluarga menyambut tahun baru Saka di desa sejak sepuluh tahun di rantauan. Menjadi pegawai swasta di Kalimantan Barat, membabu untuk perusahaan sawit. Seperti buah yang telah berjarak dengan akar, rasa di antara aku dan lingkungan desa, membuat kami memutuskan untuk tinggal di Denpasar selepas pulang dari rantauan, tiga tahun lalu.
Dari tiga hari lalu, aku, istriku dan kedua anakku sudah menginap di Desa. Menyambut sepi dalam suasana desa dan meninggalkan sepi di kota. Di rumah tua, kami mencoba menyambungkan kembali kenangan yang putus bertahun-tahun. Antara kami dengan mereka; antara aku dan keluargaku dengan ayah, ibu, paman dan saudara-saudaraku.
Tilam pada Sasih Kesanga, dikatakan malam yang paling gelap dalam setahun. Bulan mati yang mengantar perubahan Sasih, dari Kesanga menuju Sasih Kedasa. Namun, gelap sepertinya tak selalu berpasangan dengan sunyi. Gelap yang dianggap paling gelap, kali ini justru benar-benar meriah oleh arak-arakan ogoh-ogoh dan nyala api obor.
Seiring binar-binar kemeriahan itu meluap, aku menepi dalam kesendirian.
Bayangan pohon digerakkan oleh udara, menyambut pagi yang kini bebas dari dengungan mesin. Suara-suara alam terdengar nyaring. Burung, ayam, anjing dan ocehan anak-anak tetangga yang sedang bermain begitu jelas di telinga. Hari ini telinga punya kesempatan untuk beristirahat, sekaligus menelisik suara-suara asing.
Pagi bergerak lamban, beberapa kali istriku menawarkan makan, tetapi ku tolak. ku katakan bahwa sedang berpusa, mengosongkan lambung selama dua puluh empat jam. Sebagai penghormatan pada sumber makanan, pada sang pemberi hidup, sekaligus berniat untuk belajar mengendalikan nafsu.
Aku menengok jalanan, yang seakan mati oleh waktu. Tiga orang pecalang berjalan lewat di depan rumah. Ku ingat salah seorang adalah kawan baik saat sekolah dasar. Namanya Tomblos, Ia dikenal sebagai murid nakal dan ditakuti. Selain karena bertubuh besar dia jago berkelahi. Satu kelemahannya adalah susah menghafal huruf, dan itu juga yang menyebabkan Ia tak naik kelas dua kali.
Sampai akhirnya kami duduk dalam satu bangku di kelas empat, lalu bersama mengakhiri sekolah dasar. Kami saling berbagi peran. Ia berusaha melindungiku dari kenakalan anak-anak lain dan aku membantunya saat ulangan umum. Kini Ia nampak jauh berubah, lebih dewasa, berwibawa dengan pakaian hitam dan kain poleng. Ia menjadi penerus tradisi, menjaga keberlangsungan tradisi yang konon perlahan tergerus moderenisasi zaman.
Ia melihat dengan senyum sembari menaikkan satu alis, berdiri memperhatikan lalu menyapa dengan salam. Ku dekati jalanan yang sedang menyepi. Kami menyatu dalam tanya jawab seputar kabar, obrolan soal pekerjaan yang selalu berakhir dengan pujian.
Ia mengajak mencari kopi di wantilan untuk mengobrol lebih panjang, meski sudah kukatakan sedang berpuasa, namun Ia memaksa. Katanya kalau pulang harus mebraya, di wantilan sedang ada kumpul-kumpul. Kutahu ini hari Nyepi dan sesuai agama seharusnya mengamalkan Catur Brata Penyepian di antaranya tidak bepergian dan berpesta. Ajakannya justru berbalik dari yang semestinya. Namun, kecanggungan padanya justru membuatku menjadi menasaran.
Kami berjalan di jalan lengang menuju Wantilan yang hanya lima ratus meter dari rumah, sembari memperhatikan dua pecalang lain di depan kami. Mereka berjalan dan sebentar-sebentar berhenti, memunguti plastik bekas air kemasan yang dibuang sembarang selepas kemeriahan ogoh-ogoh kemarin. Dari belakang, kami berdua mengikuti yang dilakukan dua pecalang itu.
Kami tiba di depan gapura tembok bata, suasana nampak lengang. Rumput-rumput yang baru dicukur dan sepasang pohon beringin keramat seolah menatap kami dalam diam. Dua pecalang tadi masuk ke jalan lain untuk memantau kondisi rurung-rurung. Tomblos mengiringiku menuju wantilan bagian belakang, bangunan serba guna yang lebih sering dipakai ruang persiapan pertunjukan, tempat mebat dan beristirahat.
Perlahan suara-suara orang mulai terdengar. Kudapati orang-orang sedang berkumpul di beberapa meja. Ada lima meja bulat yang setiap kursi telah penuh diisi lima orang. Beberapa orang terbaring tidur di atas dipan bambu. Seorang duduk di bangku panjang.
Seorang yang duduk di atas bangku panjang mendekati kami, Ia menyalamiku dan bertanya, “Gus, kapan pulang?” Kujawab, “Empat hari yang lalu, Jik. Sehari sebelum melasti ke pantai.”
Ia mengajak kami duduk. Menyeduhkan kami kopi saset dalam gelas plastik tanpa menawarkan terlebih dahulu. Pak Dewa, yang raut wajahnya tak asing dalam ingatan adalah mantan guru agama saat di sekolah dasar. Dia yang tak pernah absen mengingatkan kami untuk melafalkan mantra Tri Sandya dengan benar.
Kini, meski tatapan matanya tak berubah sejak terakhir kami bertemu, namun usianya tetap kentara, mengikis dimakan waktu. Meskipun wibawanya masih bertahan, kata Tomblos Ia kini menjabat kelihan adat.
Puasaku batal oleh segelas kopi buatan Pak Dewa. Entah mengapa aku tak mampu menolak dalam kata maupun tindakan. Kali ini, aku merasakan tawaran seorang Kelihan Adat menang oleh rayuan sarapan pagi seorang istri. Kami bertiga mengamati orang-orang yang mengisi meja bulat, yang sama sekali tak memperhatikan kedatanganku. Mereka seperti mempunyai dunia sendiri, dengan kartu-kartu cekian dan harapan-harapan akan kemenangan.
Perlahan Tomblos dan Pak Dewa larut dalam obrolan tentang hal-hal teknis mengenai perbaikan Pura dan soal kedatangan calon DPRD minggu lalu, yang bersosialisai dengan tawaran proposal. Jika Ia menang, maka dana punia untuk Pura Desa akan dilunasi seratus persen dari dua puluh lima persen yang sudah diberikan saat sosialisasi. Proposal-proposal yang masih tersendat, semua dijanjikan akan cair dalam waktu empat puluh lima hari setelah pelantikan.
Dalam diam aku hanya mendengarkan. Kuperhatikan lagi orang-orang yang sedang larut dalam permainan ceki. Mereka rasanya tidak punya beban atas kehidupan. Pikiranku mulai bergejolak seolah tak menerima situasi di depan mata. Bagaimana bisa seorang mantan guru agama sekolah dasar, yang menjejali kami dengan ajaran-ajaran kepatuhan pada agama kini membiarkan perjudian di tengah hari suci.
Bukankah Catur Brata Penyepian mesti dijalankan sesuai yang seharusnya agama ajarkan? Dan oleh seorang Kelihan Adat, salah satu pimpinan adat tertinggi malah dibiarkan berjalan, bahkan diamini menjadi hiburan saat Nyepi.
Hatiku berteriak kencang, tetapi tak sampai mengucap satu kata pun. Semua buku-buku sastra dan ceramah-ceramah cendikiawan Hindu di Pura Jagatnatha, semuanya seolah hanya konsumsi pikiran, yang semata-mata sebagai obat penenang kepenatan. Tattwa hanya sebagai pemanis bagi para pecandu, bukan penawar kemabukan yang harus diwujudkan dalam perlakuan.
Kopi telah berkurang dari gelasnya. Tinggal seperempat gelas dan kehangatannya memudar tak seperti saat baru diseduh. Pikiranku berada di tempat lain, tetapi telinga masih setia mendengarkan obrolan mereka. Tiba-tiba Pak Dewa menyentuh bahu kananku. Wajahnya mengarah pada Tombos, “Lama tidak kelihatan mebraya di Desa, sudah sukses dia sekarang.” Satu kalimat itu, sindiran ataukah pemantik agar aku ikut dalam obrolan mereka?
Aku hanya tersenyum menunduk. “Dia sekarang sudah jadi orang kota, sejak pulang dari Kalimantan.” Tomblos menambahkan dan ditimpali oleh Pak Dewa, “Bagaimana kabar Kalimantan?” Pertanyaan ambigu dari Pak Dewa ini mengarah padaku, seolah berniat mengorek detail-detail perjalanan panjang kehidupanku.
Meski bingung darimana memulai, tetap kubalas pertanyaanya dengan terbata-bata. “Saya mendapat pengalaman bagus, Jik. Sebelumnya baik-baik saja. Tapi akhir-akhir ini Kalimantan panas. Karena ulah para bos, hutan menjadi berkurang, sengaja dibakar untuk ladang sawit baru. Dan kebetulan istri saya bisa pindah tugas ke Bali. Ini menjadi momentum bagus, sekalian juga agar anak-anak dapat tumbuh dan belajar di tanah kelahiran bapaknya, maka kami memutuskan untuk pulang. Dan soal kebebasan beragama, tidak seperti Bali, di sana kami menjadi minoritas. Kami ingin anak-anak mengerti tentang ajaran agama dengan lebih baik.” Kuharap mampu memuaskan pertanyaannya dan semoga Ia tak lagi meneruskan dengan bertanya lebih dalam soal itu.
Pak Dewa membalas, seolah tidak ada hubungannya dengan pertanyaan dia sebelumnya. “Gus, Kamu cukup beruntung, bisa melihat rumahmu, Bali, dari kejauhan. Melihat dengan lebih menyeluruh, tentu akan mudah bagimu memperbaiki jika suatu saat terjadi kerapuhan.”
Pak Dewa menyalakan korek kayu, membakar ujung rokoknya. Dia tidak lagi meneruskan pertanyaan soal kabar Kalimantan, tentang cerita ku tak lagi dirasa penting, justru kali ini Ia berbicara seperti seorang guru bijaksana. “Seringkali kita berhadapan dengan situasi dan orang-orang yang bertentangan dengan ideologi di kepala kita. Namun, itu bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk tidak berkawan. Seperti ajaran Rwa Bhineda, siang yang selalu menerima malam, dan begitu pula sebaliknya, tapi mereka tetap saling menjaga agar senantiasa seimbang dan harmonis. Pertentangan bukan untuk menjadi pembeda di antara kita, apalagi menjadikan kita musuh.”
Ia membaca pikiranku, apa iya? Mungkin saat menyambung obrolan dengan Tomblos Ia telah mengamati gerak-gerikku sejak pertama duduk. Bagaimana bisa? Tidak mungkin! Bisa saja Ia hanya ingin mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku ajukan soal apa yang terjadi di sini. Seolah sengaja menunjukkan ketidak-berpihakannya pada pesan leluhur.
Tomblos tanpa kata, hanya dengan bahasa tubuh Ia mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pak Dewa. Aku merasa menjadi minoritas, kali ini di antara orang-orang yang seagama, sedesa, di bawah satu payung ajaran leluhur. Pertanyaanku soal kegelisahan terhadap situasi ini telah terjawab, meski pertanyaan itu belum sempat terucapkan. Namun pergolakan di pikiranku malah bertambah kencang, dan menghadirkan jarak baru antara aku dan mereka.
“Nyepi hanya sekali dalam setahun. Para leluhur kita telah memberikan ruang satu hari untuk tubuh dan alam ini beristirahat. Mengapa kita tak bisa mengendalikan diri, cukup hanya dengan beristirahat sehari saja? Bukankah Catur Brata Penyepian yang dibangga-banggakan itu mesti kita jaga, tidak hanya lestari dalam tulisan dan kata.” Pertanyaan ini kulemparkan pada dua orang di sampingku. Tomblos diam, Ia melempar muka ke arah Pak Dewa.
Pak Dewa menjawab, “Gus, apa yang kamu sampaikan itu benar, dan pesan dan ajaran leluhur semestinya harus tetap dilestarikan agar tak punah. Apalagi tujuannya untuk kebaikan….” Sebelum meneruskan pembicaraannya, Ia menoleh ke arah orang-orang. Ia dipanggil oleh seorang yang duduk di meja bulat, diminta untuk menggantikan bermain.
Sebelum beranjak Ia menepuk bahu kanan ku lagi dan melanjutkan ucapannya, yang seolah tiada hubungannya dengan pertanyaan ku barusan, “Gus, semuanya telah berubah tidak lagi perlahan tapi begitu cepat, wewidangan desa, ladang, sawah dan semua yang kasat mata, mungkin kau sudah bisa lihat. Tetapi setidaknya sikap masyarakat masih sama.”
Ia berdiri, raut wajahnya berubah menatap orang-orang yang sedang bermain ceki. “Beberapa tahun belakangan, banyak beton-beton telah berdiri di sepanjang aliran sungai, deretan bangunan permanen untuk bule-bule yang sedang tergila-gila dengan budaya Bali. Dan kau tahu, itu semua milik orang-orang Jakarta. Sawah kini hanya tinggal setengahnya, sudah digantikan dengan vila-vila. Aliran air subak yang dibangga-banggakan, mulai tak teratur sebab beton-beton itu telah membunuh telabah-telabah, ikan plestimah mati dimakan plastik. Dan sikap kita masih sama, bertoleransi terhadap perubahan.”
Ia tersenyum pada ku, kemudian melanjutkan. “Toleransi terhadap apapun! Ya begitulah kita. Bisa kau lihat nanti malam, di tengah-tengah masyarakat kita yang menyepi, mereka yang menempati bangunan-bangunan megah itu akan berpesta dengan paket-paket wisata Nyepi.”
“Jik! Berhenti nutur. Ayolah main, biar pas lima orang.” Seseorang dari meja bulat memanggil Pak Dewa.
Tanpa menggubris Ia melanjutkan, kini suaranya lebih dalam dan pelan. “Gus, kau lihat orang-orang di sana…” Sembari menatap kembali kumpulan meja-meja bulat. “Mereka itu bukannya berpesta, mereka sedang beristirahat dari letih menghadapi perubahan zaman. Esok usai hari Raya, yang masih punya sawah akan kembali mencangkul, yang sawahnya telah berganti vila akan kembali meburuh, dan yang memiliki kewajiban adat akan kembali ngayahan adat. Meskipun dalam judi kau lihat mereka nista, tapi mereka tak selicik orang-orang Jakarta yang menguasai sebagian tanah di desa ini.” Ia beranjak, menuju salah satu meja bulat dan menggantikan seorang pemain.
Hanya aku dan Tomblos di bangku panjang. Kami saling berpandangan tak menyambung lagi obrolan barusan. Seolah kami sepaham, meski ucapan Pak Dewa telah terbawa angin. Aku berpamitan dengan Tomblos dan hanya memberi senyum pada Pak Dewa.
Jalanan masih sepi, matahari yang terik telah tertutup mendung tipis. Anjing-anjing berkeliaran bebas di jalanan, mereka memunguti bekas-bekas bungkusan nasi yang terhambur sembarangan.
Tiba di rumah, istriku menyambut dengan wajah muram. Kulihat tangannya sedang membawa saputangan basah dan ember kecil. Anakku yang nomor dua terbaring di lantai beralaskan tikar. Kata istriku sejak pagi Ia mual dan muntah-muntah. Kutempelkan tangan di dahinya. Ia demam dan menggigil, panasnya begitu tinggi.
Harus dibawa ke rumah sakit, begitu pikirku. Namun hari ini adalah Nyepi, dilarang membawa kendaraan bepergian, apalagi rumah sakit jaraknya lebih dari 15 kilometer dari rumah. Itu pun jika ada dokter yang berjaga. Dalam kebingungan istriku mendesak agar segera dibawa ke rumah sakit.
“Bli, carilah bantuan tetua adat atau pecalang untuk membantu kita, bawa Kadek ke rumah sakit!” Ia seolah menyalahkan kepergianku sejak tadi pagi dari rumah.
Aku pergi ke wantilan bagian belakang dengan tergesa-gesa. Kudapati pemandangan sama, hanya Tomblos yang tak ada di tempat semula. Kutemui Pak Dewa, kujelaskan persoalan yang sedang kuhadapi. Tanpa banyak kata, Ia menyuruh seorang untuk mengikutinya dan Ia meninggalkan permainan. Ia memintaku untuk segera pulang menunggu di rumah, aku mengiyakan.
Anakku kembali muntah-muntah. Kini panasnya bertambah. Istriku tidak sabar menanti datangnya bantuan. Seketika itu pun terdengar dari luar, suara sirene mobil pecalang. Tomblos ada di kursi setir dan Pak Dewa duduk di sampingnya. Mereka meminta segera membawa anak ku masuk. Kami dalam satu mobil pergi menuju rumah sakit. Tiada percakapan di antara kami. Hanya deru mobil dan sirene yang amat keras di tengah-tengah jalanan lengang. Tiada kendaraan lain selain kami. Mobil melaju dengan cepat. Beberapa kali kami diberhentikan di perbatasan desa tetangga oleh para pecalang, tapi tak lebih dari semenit kami dapat melanjutkan lagi.
Rumah sakit tidak ikut menyepi. Orang-orang masih lalu lalang, lampu tetap menyala. Yang sakit masih terkapar di ruangannya, perawat tetap siaga, dan seperti biasa suara-suara manusia masih bercampur antara tangisan, rintihan dan perdebatan pendamping pasien dengan kasir. Istriku dan Tomblos mengantar anakku ke UGD, sedangkan aku ditemani Pak Dewa mengurusi administrasi.
Suara hujan terdengar bersahutan dan angin mulai menusuk-nusuk kulit. Malam masih terasa lamban, meski anak ku telah mendapat kamar dan dokter sudah menetapkan diagnosos. Kami bertiga, Aku, Tomblos dan Pak Dewa duduk di bangku panjang. Kali ini bukan berhadapan dengan meja-meja bulat tapi di depan kamar rawat inap. Tanpa obrolan kami memandang ke-arah jendela dari lantai tiga rumah sakit. Malam ini semuanya seolah mati, tiada beda antara kota dan desa, tanpa nyala lampu.
Catatan Kaki
Sasih Kesanga : adalah sebutan bulan pada kalender Bali, yang jumlahnya 35 hari dalam satu sasih. Sasih Kesanga adalah, bulan kesembilan.
Tawur : adalah upacara penyucian alam yang bertujuan Nyomia bhutakala (menetralisir kekuatan bhutakala). Tawur Kesanga dilakukan saat hari Pangerupukan, sehari menjelang Nyepi.
Leneng : Tempat duduk di depan gerbang rumah orang Bali, biasanya terbuat dari beton berbentuk persegi panjang. Dahulu sering dipakai tempat ngobrol, dan memantau orang-orang baru yang lalu lalang di desa.
Kulkul : Kentungan yang terbuat dari kayu khusus, di tempatkan di balai kulkul yang bangunannya tinggi dan lokasinya di tengah-tengah pemukiman. Dibunyikan sebagai penanda waktu berkumpul warga desa.
Balai Banjar : Balai tempat berkumpulnya warga banjar, untuk musyawarah atau keperluan persiapan upacara. Banjar adalah bagian dari Desa, biasanya satu Desa Adat bisa terdiri dari beberapa banjar, meski di beberapa daerah ada terdapat satu desa adat dengan satu banjar.
Pecalang : Pengaman desa, sebagai relawan yang bertugas di bawah arahan Desa Adat.
Mebraya : berkengkrama dengan braya (keluarga) atau bisa bermaksud dengan berkawan.
Catur Brata Penyepian : Empat pantangan saat hari Nyepi, di antaranya tidak menyalakan api (amati geni), tidak bekerja (Amati Karya), tidak bepergian (Amati Lelungan) dan tidak mengadakan hiburan (Amati Lelanguan).
Rurung : Gang-gang kecil di desa.
Mebat : Adalah kegiatan membuat lawar dan sate untuk keperluan upacara, biasanya dilakukan oleh laki-laki.
Telabah : Kali-kali kecil, sebagai aliran air untuk mengairi subak-subak.
Plestimah : Sebutan untuk ikan-ikan kecil di sungai dan kali, bentuknya seperti ikan teri.
Tattwa : Ajaran filsafat dalam Hindu Bali, yang berupa tutur atau penjelasan dari sastra-sastra Bali, seperti dari kekidungan, kakawin dan lontar-lontar.
Tri Sandya : Mantram dalam agama Hindu yang disusun dalam enam bait, yang dilantunkan dalam tiga waktu. Menjelang matahari terbit, saat matahari tepat di atas kepala dan saat matahari terbenam.
Rwa Bhineda : Konsep ini boleh diterjemahankan sebagai dualisme, Rwa Bhineda bermakna bahwa kehidupan tergantung pada keseimbangan antara dua unsur yang berlawanan.
Kelihan Adat : Salah satu pimpinan di Desa Adat. Kelihan artinya yang tertua.
Wewidangan Desa : Wilayah desa.
Cekian : atau permainannya disebut meceki, adalah permainan yang menggunakan kartu ceki atau Koa (dalam Bahasa Minang). Biasanya dipakai untuk taruhan.
Ngayahan Adat : Ngayah adalah kegiatan adat yang dilakukan secara sukarela, sesuai dengan kewajiban anggota adat.